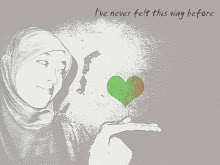AKHLAK
A. Pengertian Akhlak
Pengertian akhlak dari segi bahasa adalah perangai, tabiat, watak dasar kebiasaan, sopan dan santun agama. Dengan demikian pengertian yang diberikab Jamil Shaliba dalam bukunya al mu’jam sl falsafi, halaman 539.
Secara linguistic kata khlak merupakan isim jamid atau isim ghoiru mustaq yaitu isim yang tidak mempunyai akar kata, melainkan kata itu memang begitu adanya. Kata khlak adalah jamak dari kholqun atau khuluq yang artinya sama dengan akhlak sebagaimana telah dsebutkan di atas. Baik kata khlak atau khuluq kedua-duanya dijumpai pemakaiannya di dalam al-qur’an maupun hadis.
Akhlak dari segi bahasa ini embantu kita dalam menjelaskan pengertian akhlak dari segi istilah. Namun demikian pengertian akhlak dari segi bahasa ini sering digunakan untuk mengartikan akhlak secara umum. Akibatnya segala sesuatu perbuatan yang sudah dibiasakandalam masyarakat, atau nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat disebut akhlak. Demikian pula aturan baik dan buruk yang berasal dari pemikiran manusia, seperti etika, moral, adat kebiasaan juga dinamakan akhlak. Persepsi ini tidak sepeniuhnya benar, sebab antara akhlak, moral, etika, adat kebiasaan terdapat perbedaan. Akhak bersumber pada agama, sedangkan yang lainnya berasal dari pemikiran manusia.
Perlu dijelaskan akhlak menurut istilah yang diberikan para ahli dibidangnya. Ibnu miskawaih, sebagai pakar bidang akhlak terkemuka dalam kitabnya Tahzibul Akhlak. Dalam masalah ini ia termasuk pemikir islam yang terkenal. Dalams etiap pembahasan akhlak islam, pemikirannya selalu menjadi perhatian orang. Ia mengatakan bahwa akhlak adalah:
حال للنفس داعية لها الي افعالها من غير فكر وروية
Artinya: sikap yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa melakukan pemikiran dan pertimbangan lagi.
Dalam konsepnya, akhlak adalah suatu sikap mental (halun linnafs) yang mendorong untuk berbuat tanpa piker dan pertimbangan. Keadaan atau sikap jiwa ini tebragi menjaaaaadi du: ada yang berasal dari watak (tempramen) dan ada yang berasal dari ebiasaan dan latihan. Dengan kata lain tingkah laku manusia mengandung dua unsure : unsure watak naluri dan unsure usaha lewat kebiasaan dan latihan.
Sementara itu Imam A- Ghazali mengatkan bahwa ahlak tidak hanya terbatas pada apa yang dikenal dengan “teori menengah” dalam keutamaan seperti apa yang disebut aristotelels, dan pada sejumlah sifat keutamaan yang bersifat pribadi, tetapi juga menjangkau sejumlah sifat keutamaan akali dan amali, perorangan dan masyarakat. Semua sifat ini bekerja dalam satu kerangka umum yang mengarah kepada suatu sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.
Akhlak menurut al ghazali mempunyai tiga dimensi:
- Dimensi diri, yakni orang dengan dirinya dan Tuhannya, seperti ibadah dan sholat.
- Dimensi social, yakni masyarakat, pemerintah dan pergaulan sesamanya.
- Dimensi metafisis, yakni akidah dan pegangan dasarnya.
al ghazali member definisi akhlak sebagai berikut:
عبرةعن هيئة في النفس را شخة,عنها تصدرالافعال بسهولة ويسري من غير حاجة الي فكر و روية فان كانت الهيئة بحيث تصدر عنها لافعل بجميلة المحمودة عقل و شرعا سميت تلك الهيئة خلقا حسنا وان كان الصادر عنها الافعال القبيحة سميت الهيئة التى هى المصدر خلق شيئا
Artinya: akhlak adalah suatu siskap (hay’ah) yang mengakar dalam jiwa yang dariny lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa perlu kepada pikiran dan pertimbangan. Jika sikap itu yang darinya lahir perbuatan yang baik dan terpuji, baik dari segi akal dan syara’, maka ia disebut akhklak yang baik. Dan jika yang lahir darinya perbuatan tercela, maka sikap tersebut disebut akhlak tercela”.
Dengan demikian, akhlak itu mempunyai empat syarat:
- Perbuatan baik dan buruk
- Kesanggupan melakukannya
- Mengetahuinya
- Sikap mental yang membuat jiwa cenderung pada salah satu dua sifat tersebut, sehingga mudah melakukan yang baik atau yang buruk.
Sedangkan menururt al farabi, ia menjelaskan akhlak itu bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan yang merupakan tujuan tertinggi yang dirindui dan diusahakan oleh stiap orang. Jika diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa seluruh definisi akhklak sebagaimana tersebut di atas tidak bertentangan melainkan sdaling melengkapi, yaitu suatu sifat yang tertanam kuat dalam jiwa yang tampakdalam perbuatan lahiriah yang dilakuakn dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran lagi dan sudah menjadi kebiasaan.
Dorongan lain yang tersembunyi dalam diri manusia adalah berpegang pada nilai-nilai moral dan ini tergolong pada kategri nilai-nilai utama yang dalam konteksnya biasa disebut dengan akhlak yang baik. Manusia memiliki kecenderungan terhadap banyak hal, diantaranya ada yang member manfaat secara fisik kepadanya, misalnya senang tehadap harta. Sebab harta memang member manfaat kepada manusia dalam menutupi berbagai kebutuhan materil.
Lebih lanjut perkataan moral berasal dari bahasa latin “mores” kata jamak dari “mos” yang berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia moral diterjemahkan dalam arti susila. Yang dimaksud dengan moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan yang wajar. Jadi sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan yang oleh umum diterima yang meliputi kelompok social atau lingkungtan tertentu. Dengan demikian jelas kesamaan etika dan moral. Namun ada pula perbedaannya, yakni etika lebih bersifat teori sedangkan moral lebih bersifat praktis. Sedangkan menurut Zakiah Daradjat moral adfalah suatu masalah yang menjadi perhyatian orang dimana saja baik dalam masyarakat yang telah maju maupun masyarakat yang masih terbelakang.
Etika
Etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan apa yag seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada yang lainnya, menyetakan tujuan yang harus dituju oleh manusia didalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Dapat diketahui bahwa etika untuk menyelidiki segalaperbuatan manusia kemudian menetapkan hukun seperti ini, karena perbuatan manusia ada yang timbul tiada dengan kehendak seperti bernafas, detak jantung dan memicingkan mata, maka ini bukanlah pokok persoalan etika. Dan tidak dapat member hukum baik atau buruk.
Dan apabila ada perbuatan yang timbul karena kehendak dan setelah piker matang-matang akan buah adan akibatya, maka itulah yang disebut dengan perbuatan kehendak, perbuatan mana harus diberi hukum baik atau buruk dan dapat dituntut.
Menurut pandangan filsafat etika memandang prilaku perbuatan manusia secara universal sedangkan moralsecara local menyatakan ukuran dan etika menjelaskan ukuran itu.
Abu a’la al maududi memberikan garis tegas antara moral sekuler dengan moraql islam. Moral sekuler adalah yang bersumber dari ikiran prasangka manusia yang beraneka ragam. Sedangkan moral islam bersandar pada bimbingan dan petunjuk Tuhan dalam al qur’an.
Sejarah perkembangan akhlak
Akhlak pada zaman Yunani dan Abad Pertengahan
Diduga yang pertama kali mengadakan penyelidikan tentang akhak yang berdasarkan ilmu pengetahuan ialah bangsa Yunani. Ahli-ahli filsafat Yunani kuno tidak banyak memperhatikan pada akhlak, tapi kebanyakan penyelidikannya mengenai alam sehingga datangnya Sephistician (500-450 S-M).arti sephisticians adalah orang yang bijaksana. (sufisemm artinya orang-orang yang bijak). Pada masa itu akhlak terungkap dengan kata etika dengan arti yang sama.
Golongan ahli-ahli flsafat dan menjadi guru yang tersebar dibeberapa negri. Buah pikiran dan pendapat mereka berbeda-beda akan tetapi tujuan mereka adalah satu yaitu menyiapkan angkatan muda bangsa Yunani agar menjadi nasionalis yang baik lagi merdeka dan mengetahui kebijakn mereka terhdap tanah airnya.
Pandangan tentang kewajiban-kewajiban ini menimbulkan pandangan mengenai sebagian tradisi lama dan pelajaran-pelajaran yang dilakukan oleh orang-orang yang dahulu, yang demikian itu tentu membangkitkan kemarahan kaum yang konserfatif. Kemudian datag filsafah yang lain dan ia pun menentang dan mengecam mereka. Dan ia pun menuduh mereka suka mempermainkan dan memutar balikkan kenyataan. Oleh karena itu buruklah nama mereka. Kemudian datang pula sokrates dengan menghadapkan perhatiannya kepada penyelidikan didalam akhlak dan hubungan manusia satu dengan yang lainnya.
Socrates terpandang sebagai perintis ilmu akhlak, karena ia pertama yang mengusahakan dengan sungguh-sungguh membentuk perhubungan manusia dengan dasar ilmu pengetahuan. Dia berpendapat bahwa akhlak dan bentuk perhubungan itu tidak menjadi benar kecuali bila didasarkan kepada ilmu pengetahuan, sehingga ia berpendapat bahwa keutamaan itu adalah ilmu.
Karena tidak diketahuinya pandangan Socrates mengenai tujuan yang terakhir tentang akhlak atau ukuran untuk mengetahui baik dan buruk sebuah perbuatan, maka timbullah beberpa golongan yang berbeda-beda pendapatnya tentang tujuan akhlalk, lalu muncul beberapa paham mengenai akhlak sejak zaman itu hingga sekarang ini. “Cynics” dan “Cyrenics” kedua pengikut Socrates.
Diantara perjalanan mereka adalah bahwa ketuhanan itu bersih dari segala kebutuhan dan sebaik-baik manusia adalah berperangai dengan akhlak ketuhanan. Diantara pemimpin paham ini yang terkenal ialah Diogenes meninggal pada tahum 323 SM. Dia member pelajaran kepada kawan-kawannya supaya membuang beban yang ditentukan oleh ciptaan manusia dan perannya.
Adapun cyrenics berpendapat bahwa mencari kelezatan menjauhi kepediahn ialah satu-satunya tujuan yang benar untuk hidup, dan perbuatan itu dinamai utama bila timbul kelezatan yang lebih besar dari kepedihan. Tatkala Cynics berpendapat bahwa kebahagiaan itu menghilangkan kejahatan dan menguranginya sedapat mungkin. Cynics berpendapat bahwa kebahagiaan itu dalam mencari kelzaqtan dan mengutamakannya.
Plato pada 427-347 SM seornag ahli filsafat Athenadan murid dari Socrates. Pandangannya didalm akhlak berdasarkan teori contoh ideal, pendpaatnya bahwa dibelakang yang lahir ii ada alam lain ialah alam rohani dan dia pun berpendapat pula di dalam alam ruhani ini ada kekuatan bermacam-macam dan kekuatan itu timbul dari pertimbangan tundukknya kekuatan pada hukum akal, dia berpendapat bahwa poko-pokok keutamaan ada empat antara lain, hikmah/ kebijaksanaan, keberanian, keperwiraan dan keadilan.
Lalu datang aristoteles murid plato yang membangun satu faham yang khas yang mana pengikutnya disebut paripatetik karena mereka memberikan pelajaran sambil berjalan. Ia berpendapat bahwa tujuan akhir manusia mengenai segala perbuatannya adalah bahagia ia berpendpat bahwa jalan mencapai kebahagiaan adalah mempergunakan kekuatan akal pikiran sebaik-baiknya.
Lalu datang stoics berpendirian sebagai paham cynics paham ini banyak diikuti filsafat Yunani dan Romawi dan pengikutnya yang termasyhur adalah Scena, Epicurus, dan kaisar marcul orleus.
Pada akhir abad ketiga masehi tersebarlah kabar agama nasrani di eropa yang merubah pikiran manusia tentang akhlakl dan membawa poko-pokok akhlak yang tercantum dalam Taurat.
Akhlak pada Bangsa Arab (sebelum dan sesudah Islam)
Bangsa Arab pada zaman jahiliyyah tidak memiliki ahli-ahli filsafat yang mengajarkan pada aliran tertentu, sebagimana yang ada pada kalangan bangsa Yunani. Yang demikian itu karena penyelidikan ilmu tidak terjadi kecuali di Negara-negara maju, sedangkan bangsa arab pada masa itu masih jahiliyyah mereka hanya menyesuaikan ahli-ahli hikamat dan ahli syaiiir yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemunkaran. Setelah masukny isalm akhlak itu mesti didasarkan pada isi ajaran al qur’an dan hadis. Sedikit dari bangsa arab yang telah maju yang menyelidiki akhlak berdasarkan ilmu pengetahuan. Karena mereka telah merasa puas mengambil akhlak dari agama, mereka tidak merasa butuh kepada penyelidikan ilmiyah mengenai dasar nilai baik dan buruk. Oleh karena itu agama menjadi dasar kebanyakan buku-buku yang ditulis tentang akhlak.
B. Akhlak Mulia Rasulullah sebagai Uswatun Hasanah
Dalam hal akhlakul karimah, selayaknya kita meneladani akhlak beliau. Bahwa Rasulullah saw senantiasa banyak merendah dan berdoa sepenuh hati. Beliau selalu memohon kepada Allah swt agar menghias dirinya dengan adab-adab yang baik dan akhlak yang mulia. Didalam doanya RAsulullah mengatakan “ya Allah, baguskanlah untukku dan akhlakku”.
Diantara pebuatan baik adalah pergaulan yang baik, perbuatan mulia, perkataan yang lembut, mendermakan kebaikan, memberi makan, menyebarkan salam, mengunjungi orang muslim yang sakit baik yang berbuat baik maupun yang berbuat durhaka, mengantarkan jenazah orang muslim, bertetangga secara baik apakah itu muslim maupun kafir, dan lain-lain.
Anas r.a berkata “Rasulullah tidak membiarkan nasehat yang baik melainkan mengajak kami kepadanya dan menyuruh kami mengerjakannya. Beliau tidak membiarkna menipu atau mengatakan: mencela dan tidak pula membiarkan sesuatu melainkan mengingatkan kami dan melarang kami melakukannya. Dari semua itu cukuplah surat annahl ayat 90. Yang artinya:
•
Artinya: “ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl 90)
Akhlak Rasulullah menjadi pedoman bagi masyarakat sejak dulu hingga sekarang. Sifat beliau merupakan suatu tenaga yang mempertalikan antara anggota-anggota masyarakat itu dengan satu ikatan yang teguh, dan pimpinan beliau menjadi ilham kebaikan umat islam dari dahulu hingga sekarang.
C. Macam-macam Akhlak
1. Akhlakul Karimah
Akhlakul karimah atau akhlak yang mulia amat banyak jumlahnya, namun dapat dilihat dari segi hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia, akhlak mulia itu dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama akhlak mulia kepada Allah, kepada diri sendiri dan terhadap sesame manusia.
a. Akhlak terhadap Allah
Titik tolak akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Dia memiliki sifa-sifat terpuji demikian Agung sifat itu, yang jangankan manusia, malaikat pun tidak akan menjangkau hakikat-Nya.
Banyak alas an mengapa manusia harus berakhlak baik terhadap Allah. Diantaranya adalah hal-hal sebagai berikut:
Karena Allah terlah menciptakan manusia dengan segala keistimewaan dan kesempurnaannya. Sebagai yang diciptakan sudah sepantasnya manusia berterimakasih kepada yang menciptakannya.
Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (QS at-tiin: 4).
Karena Allah telah memberikan perlengkapan panca indera hati nurani dan naluri kepada manusia. Semua potensi jasmani dan rohani amat tinggi nilainya, karena dengan potensi tersebut manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dalam berbagai bidang kehidupan yang membawa pada kejayaan
•
Artinya: dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. (QS an-nahl 78)
Karena ALalh menyediakan berbagai bahan dan sarana kehidupan yang terdpat di bumi, seperti tumbuhan, air, udara, binatang dsb. Semua itu tunduk kepada kemauan manusia atau siap untuk dimanfaatkan.
• •
Artinya: Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia -Nya dan Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-JAtsiyah 12-13)
Dengan keterangan diatas sudah sepantasnya dan sewajarnya manusia berakhlak baik dan taat kepada Allah, dan alangkah tidak wajarbnya bila manusia durhaka terhadapa Allah.
“Hai anak Adam taatlah kamu kepada Tuhanmu niscaya kamu dinamakan orang yang berkal da janganlah kamu durhaka kepadaNya sehingga kamu dinamakan oragn yang Bodoh”. (HR. Abu Na’im)
b. Akhlak yang Baik terhadap Diri Sendiri
Selaku individu, manusi diciptakan oleh Allah swt dengan segala kelengkapan jasmaniayah dan rohaniyahnya. Ia diciptakan dengan dilengkapai rohani seperti akal pikiran, hati nurani, naluri dan kecakapan batiniyah atau bakat. Dengan kelengkapan rohani ini manusia dapat memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya secara konseptual dan terencana, dapat menimbang antara baik dan salah dapat memberikan kasih sayang yang selanjutnya dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan peradaban yang mengangkat harkat dan martabatnya.
Disamping itu seorang muslim juga beriman dan percaya bahwa yang dapat membersihkan jiwa dan menyelamatkannya iman yang baik, amal yang salih, sedangkan yang mengotori dan merusaknya adalah dampak negative dari kekafiran dan perbuatan maksiat.
Untuk menjalankan perintah Allah d an bimbingan Nabi Muhammad saw maka setiap umat islam harus berakhlak dan bersikap sebagai berikut:
1. hindarkan makanan beracun/ keras
2. hindarkan perbuatan yang tidak baik
3. memelihara kesucian jiwa
4. pemaaf dan pemohon maaf
5. sikap sederhana dan jujur
6. hindarkan perbuatan tercela
Manusia yang berakhlak baik terhadap dirinya sendiri adalah manusia yang terbina sumber dayanya secara optimal.
c. Akhlak Yang Baik Terhadap Sesama Manusia
Manusia adalah sebagai makhluk sisoal yang kelanjutan eksistensinya secara fungsional dan optimal banyak banyak bergantung pada orang lain. Untuk itu ia perlu bekerjasama dan saling tolong menolong dengan orang lain. Oleh karenanya ia perlu menciptakan suasana yang baik satu dan lalinnya sa;ing berakhlak yang baik. Caranya dapat dilakukan dengan memuliakannya, memberikan bantuan, pertolongan dan menghargainya.
2. Akhlak Madzmumah
Akhlak yang tercela secara umum adalah lawan atau kebalikan dari akhlak yang baik. Berdasarkan petunjuk islam, dijumpai berbagai macam akhlak tercela, diantaranya:
a. takabbur
b. berbohong
c. dengki
d. bakhil
D. Sendi-Sendi Akhlak
Akhlak dalam wujud pengembangannya dibedakan menjadi dua yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Jika ia sesuai dengan perintah Allah dan RasulNya yang kemudian menghasilkan akhlak terpuji, maka itulah yang dinamakan akhlak mahmudah.
Sedangkan jika ia sesuai dengan apa yang dilarang Allah dan RAsulnya dan melahirkan perbuatan yang buruk, maka itulah yang disebut sebagai akhlak madzmummah.
1. Akhlak Mulia
Tentang akhlak yang terpuji menurut Imam Al- Ghazali ada empat sendi yang cukup mendasarkan menjadi induk seluruh akhlak, yaitu:
a. kekuatan ilmu wujudnya adalah hikmah (kebijaksanaan), yaitu keadaan jiwa yang bias menentukan hal-hal yang benar diantara yang salah dalam urusan ikhtiyariyah (perbuatan yang dilaksanakan dengan pilihan dan kemauan sendiri)
b. kekuatan marah wujudnya adalah syaja’ah (berani) yaitu keadaan kekuatan amarah yang tunduk pada akal pada waktu dilahirkan atau dikekang.
c. Kekuatan nafsu syahwat wujudnya adalah ‘iffah (perwira) yaitu keadaan syahwat yang terdidik oleh akal dan syari’at agama
d. Kekuatan keseimbangan diantara kekuatan yang tiga diatas wujudnya ialah adil yaitu kekuatan jiwa yang dapat menuntun amarah dan syahwat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hikmah.
Dari empat sendi akhlak terpuji di atas akan lahir perbuatan-perbuatan seperti: jujur, suka memberi, tawadhu’, tabah, tinggi cita-cita, pemaaf, kasih saying terhdap sesama, berai dalam kebenaran, menghormati orang lain, sabar, pemalu, pemurah, memlihara rahasia, konaah, menjaga diri dalam ketaatan, dll.
2. Akhlak Tercela
Untuk akhlak tercela pun ada sendi-sendi yang patut diketahui yang menjadi sumber timbulnya perbuatan perbuatan yang tidak baik. Yaitu:
• khubsan wa jarbazah (keji dan pintar busuk)
• tahawwur (berani tapi sembrono), jubun (penakut) dan khauran (lemah)
• syarhan (rakus) dan jumud
• zalim
Keadaan ini adalah pangkal yang menetukan corak hidup manusia.
E. Hukum-Hukum Akhlak
Akhlak adalah sifat yang harus dimiliki setiap muslim ketika sedang melakukan aktivitas. Sifat tersebut berkaitan dengan kativitas yang dilakukan atau ditinggalkan oleh seseorang. Sifat tersebut ada yang hasan (terpuji), qabih (tercela) dan ada yang khayr (baik) dan syarr (buruk). Dalam hal ini silam telah mengatur sifat perbuatan tersebut dalamkonteks hubungan manusia dengan dirinya. Artinya, bagaimana seseorang memperhatikan kesempurnaan perbuatannya dengan menjadikan sifat tertentu sebagai sifat perbuatannya. Semua itu telah diatur oleh islam dalam bentuk hokum syara’ yang spesifik, dan tidak diserahkan kepada manusia itu sendiri untuk menentukannya. Sebab, jika diserahkan kepada manusia untuk menentukan sendiri sifat perbuatannya, apsti dia hanya akan melihat dari aspek yang menguntungkan atau merugikan bagi dirinya. Ini artinya, jika hal itu menguntungkan, ia dianggap baik dan sebaliknya jika merugikan, ia dianggap buruk. Disisi lain, ia akan menggunakan standard benda sebagai standar terpuji dan tercela, seperti manis digambarkan dengan baik, sedangkan pahit akan digambarkan dengan buruk. Meskipun masalah sifat tersebut ditetapkan oleh syara’, tetapi syari’at islam tidak banyak membahas hokum tersebut secara detail.
Dilihat dari aspek cirri khasnya: ada beberapa cirri khas yang ditetapkan oleh Allah swt dalam maslaah akhlak ini antara lain:
1. Akhlak tidak bisa dipisahkan dari hokum syara’, termasuk semua bentuk ketentuan hukum syara’ yang lain. Seperti khusu’ adalah sifat perbuatan orang yang sedang mengerjakan sholat, yang tidak ada pada orang diluar sholat. Jujur, amanah dan menunaikan janji adalah sifat perbuatan orang yang melakukan mu’ammalah (berhubungan dengan orang lain).
2. Akhlak juga tidak bias didasarkan pada ‘illat, sehingga tidak ada satu ‘illat pun dalam masalah akhklak. Jujur, amanah dan menunaikan janji diperintahkan semata-mata karena hukumya adalah wajib menurut syara’, yang kewaibannya telah ditentukan oleh nash, bukan disebabkan adanya ‘illat tertentu. Maka kejujuran, amanah dan menepati janji tersebut tidak bias dilandaskan oleh seorang muslim karena keuntungan material, atau mengharapkan pujian orang dan sebagainya.
3. Akhlak juga tunduk pada manfaat tertentu. Sebab, orang yang melakukan hukum akhlak kadang-kadang malah mendapatkan kerugian, bukan keuntungan. Contoh, sifat berani dan menentang ketika mengingatkan penguasa yang zalim adalah sifat pengemban dakwah yang mulia. Sesuatu yang bias mengakibatkan orang tersebu6t menemui ajalnya. Sebagimana sebda Nabi Saw:
“ penghulu para syahid adalah Hamzah bin ‘Abdul Muthollib, serta orang yang berdiri didepan penguasa dzalim, lalu memerintahkan (kema’rufan) dan mencegah (kemunkaran) atasnya, kemudian dia pun membunuhnya.” (HR. Hakim dari Jabir).
4. Akhlak sama dengan akidah. Akhlak merupakam tuntunan fitrah manusia. Memuliakan tamu dan mebmantu orang yang memerlukan adlah sangat selaras dengan fitrah manusia yaitu naluri mempertahankan diri. Khusu’ dan tawaddu’ juga selaras dengan fitrah manusia yaitu naluri beragama. Kasih sayang dan keta’atan juga sesuai dengan fitrah manusia yaitu naluri menyayangi.
Dari aspek pengaruh: jika sifat perbuatan (akhlak) tersebut dimiliki oleh seorang muslim ketika melakukan aktivitas, maka akan mempunyai pengaruh yang signifikan, antara lain:
1. Melaksanakan akhlak dengan taklif syar’I yang lain akan menjadikan seorang muslim memiliki kepribadian yang khas ketika berinteraksi dengan khalayak ramai. Mereka pun percaya dengan kata-kata dan perbuatannya.
2. Akhlak akan bias menumbuhkan kasih sayang dan sikap hormat khususnya antara sesama anggota keluarga, dan umumnya dengan aggota masyarakat.
3. Orang yang mempunyai sifat perbuatan (akhak) yang terpuji akan mendapatkan pahala yang banyak disisi Allah swt di akhirat. Bahkan orang yang mempunyai akhlak yang mulia didunia akan dekat dengan Rasulullah saw di akhirat. Sabda baginda Nabi:
“Sesungguhnya orang yang paling aku cintai diantara kalian, dan lebih dekat kepada ku temmpatnya di hari kiamat adalah siapa saja yang diantara kalian yang paling baik akhlaknya.” (HR Bukhori).
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Hafidz. 2004. Dirkursus Islam Politik Spiritual. Bogor: Al-Azhar Press.
Ardani. 2001. Akhlak Tasawwuf. Jakarta: CV. Karya Mulia.
[ Read More ]
A. Pengertian Akhlak
Pengertian akhlak dari segi bahasa adalah perangai, tabiat, watak dasar kebiasaan, sopan dan santun agama. Dengan demikian pengertian yang diberikab Jamil Shaliba dalam bukunya al mu’jam sl falsafi, halaman 539.
Secara linguistic kata khlak merupakan isim jamid atau isim ghoiru mustaq yaitu isim yang tidak mempunyai akar kata, melainkan kata itu memang begitu adanya. Kata khlak adalah jamak dari kholqun atau khuluq yang artinya sama dengan akhlak sebagaimana telah dsebutkan di atas. Baik kata khlak atau khuluq kedua-duanya dijumpai pemakaiannya di dalam al-qur’an maupun hadis.
Akhlak dari segi bahasa ini embantu kita dalam menjelaskan pengertian akhlak dari segi istilah. Namun demikian pengertian akhlak dari segi bahasa ini sering digunakan untuk mengartikan akhlak secara umum. Akibatnya segala sesuatu perbuatan yang sudah dibiasakandalam masyarakat, atau nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat disebut akhlak. Demikian pula aturan baik dan buruk yang berasal dari pemikiran manusia, seperti etika, moral, adat kebiasaan juga dinamakan akhlak. Persepsi ini tidak sepeniuhnya benar, sebab antara akhlak, moral, etika, adat kebiasaan terdapat perbedaan. Akhak bersumber pada agama, sedangkan yang lainnya berasal dari pemikiran manusia.
Perlu dijelaskan akhlak menurut istilah yang diberikan para ahli dibidangnya. Ibnu miskawaih, sebagai pakar bidang akhlak terkemuka dalam kitabnya Tahzibul Akhlak. Dalam masalah ini ia termasuk pemikir islam yang terkenal. Dalams etiap pembahasan akhlak islam, pemikirannya selalu menjadi perhatian orang. Ia mengatakan bahwa akhlak adalah:
حال للنفس داعية لها الي افعالها من غير فكر وروية
Artinya: sikap yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa melakukan pemikiran dan pertimbangan lagi.
Dalam konsepnya, akhlak adalah suatu sikap mental (halun linnafs) yang mendorong untuk berbuat tanpa piker dan pertimbangan. Keadaan atau sikap jiwa ini tebragi menjaaaaadi du: ada yang berasal dari watak (tempramen) dan ada yang berasal dari ebiasaan dan latihan. Dengan kata lain tingkah laku manusia mengandung dua unsure : unsure watak naluri dan unsure usaha lewat kebiasaan dan latihan.
Sementara itu Imam A- Ghazali mengatkan bahwa ahlak tidak hanya terbatas pada apa yang dikenal dengan “teori menengah” dalam keutamaan seperti apa yang disebut aristotelels, dan pada sejumlah sifat keutamaan yang bersifat pribadi, tetapi juga menjangkau sejumlah sifat keutamaan akali dan amali, perorangan dan masyarakat. Semua sifat ini bekerja dalam satu kerangka umum yang mengarah kepada suatu sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.
Akhlak menurut al ghazali mempunyai tiga dimensi:
- Dimensi diri, yakni orang dengan dirinya dan Tuhannya, seperti ibadah dan sholat.
- Dimensi social, yakni masyarakat, pemerintah dan pergaulan sesamanya.
- Dimensi metafisis, yakni akidah dan pegangan dasarnya.
al ghazali member definisi akhlak sebagai berikut:
عبرةعن هيئة في النفس را شخة,عنها تصدرالافعال بسهولة ويسري من غير حاجة الي فكر و روية فان كانت الهيئة بحيث تصدر عنها لافعل بجميلة المحمودة عقل و شرعا سميت تلك الهيئة خلقا حسنا وان كان الصادر عنها الافعال القبيحة سميت الهيئة التى هى المصدر خلق شيئا
Artinya: akhlak adalah suatu siskap (hay’ah) yang mengakar dalam jiwa yang dariny lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa perlu kepada pikiran dan pertimbangan. Jika sikap itu yang darinya lahir perbuatan yang baik dan terpuji, baik dari segi akal dan syara’, maka ia disebut akhklak yang baik. Dan jika yang lahir darinya perbuatan tercela, maka sikap tersebut disebut akhlak tercela”.
Dengan demikian, akhlak itu mempunyai empat syarat:
- Perbuatan baik dan buruk
- Kesanggupan melakukannya
- Mengetahuinya
- Sikap mental yang membuat jiwa cenderung pada salah satu dua sifat tersebut, sehingga mudah melakukan yang baik atau yang buruk.
Sedangkan menururt al farabi, ia menjelaskan akhlak itu bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan yang merupakan tujuan tertinggi yang dirindui dan diusahakan oleh stiap orang. Jika diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa seluruh definisi akhklak sebagaimana tersebut di atas tidak bertentangan melainkan sdaling melengkapi, yaitu suatu sifat yang tertanam kuat dalam jiwa yang tampakdalam perbuatan lahiriah yang dilakuakn dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran lagi dan sudah menjadi kebiasaan.
Dorongan lain yang tersembunyi dalam diri manusia adalah berpegang pada nilai-nilai moral dan ini tergolong pada kategri nilai-nilai utama yang dalam konteksnya biasa disebut dengan akhlak yang baik. Manusia memiliki kecenderungan terhadap banyak hal, diantaranya ada yang member manfaat secara fisik kepadanya, misalnya senang tehadap harta. Sebab harta memang member manfaat kepada manusia dalam menutupi berbagai kebutuhan materil.
Lebih lanjut perkataan moral berasal dari bahasa latin “mores” kata jamak dari “mos” yang berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia moral diterjemahkan dalam arti susila. Yang dimaksud dengan moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan yang wajar. Jadi sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan yang oleh umum diterima yang meliputi kelompok social atau lingkungtan tertentu. Dengan demikian jelas kesamaan etika dan moral. Namun ada pula perbedaannya, yakni etika lebih bersifat teori sedangkan moral lebih bersifat praktis. Sedangkan menurut Zakiah Daradjat moral adfalah suatu masalah yang menjadi perhyatian orang dimana saja baik dalam masyarakat yang telah maju maupun masyarakat yang masih terbelakang.
Etika
Etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan apa yag seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada yang lainnya, menyetakan tujuan yang harus dituju oleh manusia didalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Dapat diketahui bahwa etika untuk menyelidiki segalaperbuatan manusia kemudian menetapkan hukun seperti ini, karena perbuatan manusia ada yang timbul tiada dengan kehendak seperti bernafas, detak jantung dan memicingkan mata, maka ini bukanlah pokok persoalan etika. Dan tidak dapat member hukum baik atau buruk.
Dan apabila ada perbuatan yang timbul karena kehendak dan setelah piker matang-matang akan buah adan akibatya, maka itulah yang disebut dengan perbuatan kehendak, perbuatan mana harus diberi hukum baik atau buruk dan dapat dituntut.
Menurut pandangan filsafat etika memandang prilaku perbuatan manusia secara universal sedangkan moralsecara local menyatakan ukuran dan etika menjelaskan ukuran itu.
Abu a’la al maududi memberikan garis tegas antara moral sekuler dengan moraql islam. Moral sekuler adalah yang bersumber dari ikiran prasangka manusia yang beraneka ragam. Sedangkan moral islam bersandar pada bimbingan dan petunjuk Tuhan dalam al qur’an.
Sejarah perkembangan akhlak
Akhlak pada zaman Yunani dan Abad Pertengahan
Diduga yang pertama kali mengadakan penyelidikan tentang akhak yang berdasarkan ilmu pengetahuan ialah bangsa Yunani. Ahli-ahli filsafat Yunani kuno tidak banyak memperhatikan pada akhlak, tapi kebanyakan penyelidikannya mengenai alam sehingga datangnya Sephistician (500-450 S-M).arti sephisticians adalah orang yang bijaksana. (sufisemm artinya orang-orang yang bijak). Pada masa itu akhlak terungkap dengan kata etika dengan arti yang sama.
Golongan ahli-ahli flsafat dan menjadi guru yang tersebar dibeberapa negri. Buah pikiran dan pendapat mereka berbeda-beda akan tetapi tujuan mereka adalah satu yaitu menyiapkan angkatan muda bangsa Yunani agar menjadi nasionalis yang baik lagi merdeka dan mengetahui kebijakn mereka terhdap tanah airnya.
Pandangan tentang kewajiban-kewajiban ini menimbulkan pandangan mengenai sebagian tradisi lama dan pelajaran-pelajaran yang dilakukan oleh orang-orang yang dahulu, yang demikian itu tentu membangkitkan kemarahan kaum yang konserfatif. Kemudian datag filsafah yang lain dan ia pun menentang dan mengecam mereka. Dan ia pun menuduh mereka suka mempermainkan dan memutar balikkan kenyataan. Oleh karena itu buruklah nama mereka. Kemudian datang pula sokrates dengan menghadapkan perhatiannya kepada penyelidikan didalam akhlak dan hubungan manusia satu dengan yang lainnya.
Socrates terpandang sebagai perintis ilmu akhlak, karena ia pertama yang mengusahakan dengan sungguh-sungguh membentuk perhubungan manusia dengan dasar ilmu pengetahuan. Dia berpendapat bahwa akhlak dan bentuk perhubungan itu tidak menjadi benar kecuali bila didasarkan kepada ilmu pengetahuan, sehingga ia berpendapat bahwa keutamaan itu adalah ilmu.
Karena tidak diketahuinya pandangan Socrates mengenai tujuan yang terakhir tentang akhlak atau ukuran untuk mengetahui baik dan buruk sebuah perbuatan, maka timbullah beberpa golongan yang berbeda-beda pendapatnya tentang tujuan akhlalk, lalu muncul beberapa paham mengenai akhlak sejak zaman itu hingga sekarang ini. “Cynics” dan “Cyrenics” kedua pengikut Socrates.
Diantara perjalanan mereka adalah bahwa ketuhanan itu bersih dari segala kebutuhan dan sebaik-baik manusia adalah berperangai dengan akhlak ketuhanan. Diantara pemimpin paham ini yang terkenal ialah Diogenes meninggal pada tahum 323 SM. Dia member pelajaran kepada kawan-kawannya supaya membuang beban yang ditentukan oleh ciptaan manusia dan perannya.
Adapun cyrenics berpendapat bahwa mencari kelezatan menjauhi kepediahn ialah satu-satunya tujuan yang benar untuk hidup, dan perbuatan itu dinamai utama bila timbul kelezatan yang lebih besar dari kepedihan. Tatkala Cynics berpendapat bahwa kebahagiaan itu menghilangkan kejahatan dan menguranginya sedapat mungkin. Cynics berpendapat bahwa kebahagiaan itu dalam mencari kelzaqtan dan mengutamakannya.
Plato pada 427-347 SM seornag ahli filsafat Athenadan murid dari Socrates. Pandangannya didalm akhlak berdasarkan teori contoh ideal, pendpaatnya bahwa dibelakang yang lahir ii ada alam lain ialah alam rohani dan dia pun berpendapat pula di dalam alam ruhani ini ada kekuatan bermacam-macam dan kekuatan itu timbul dari pertimbangan tundukknya kekuatan pada hukum akal, dia berpendapat bahwa poko-pokok keutamaan ada empat antara lain, hikmah/ kebijaksanaan, keberanian, keperwiraan dan keadilan.
Lalu datang aristoteles murid plato yang membangun satu faham yang khas yang mana pengikutnya disebut paripatetik karena mereka memberikan pelajaran sambil berjalan. Ia berpendapat bahwa tujuan akhir manusia mengenai segala perbuatannya adalah bahagia ia berpendpat bahwa jalan mencapai kebahagiaan adalah mempergunakan kekuatan akal pikiran sebaik-baiknya.
Lalu datang stoics berpendirian sebagai paham cynics paham ini banyak diikuti filsafat Yunani dan Romawi dan pengikutnya yang termasyhur adalah Scena, Epicurus, dan kaisar marcul orleus.
Pada akhir abad ketiga masehi tersebarlah kabar agama nasrani di eropa yang merubah pikiran manusia tentang akhlakl dan membawa poko-pokok akhlak yang tercantum dalam Taurat.
Akhlak pada Bangsa Arab (sebelum dan sesudah Islam)
Bangsa Arab pada zaman jahiliyyah tidak memiliki ahli-ahli filsafat yang mengajarkan pada aliran tertentu, sebagimana yang ada pada kalangan bangsa Yunani. Yang demikian itu karena penyelidikan ilmu tidak terjadi kecuali di Negara-negara maju, sedangkan bangsa arab pada masa itu masih jahiliyyah mereka hanya menyesuaikan ahli-ahli hikamat dan ahli syaiiir yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemunkaran. Setelah masukny isalm akhlak itu mesti didasarkan pada isi ajaran al qur’an dan hadis. Sedikit dari bangsa arab yang telah maju yang menyelidiki akhlak berdasarkan ilmu pengetahuan. Karena mereka telah merasa puas mengambil akhlak dari agama, mereka tidak merasa butuh kepada penyelidikan ilmiyah mengenai dasar nilai baik dan buruk. Oleh karena itu agama menjadi dasar kebanyakan buku-buku yang ditulis tentang akhlak.
B. Akhlak Mulia Rasulullah sebagai Uswatun Hasanah
Dalam hal akhlakul karimah, selayaknya kita meneladani akhlak beliau. Bahwa Rasulullah saw senantiasa banyak merendah dan berdoa sepenuh hati. Beliau selalu memohon kepada Allah swt agar menghias dirinya dengan adab-adab yang baik dan akhlak yang mulia. Didalam doanya RAsulullah mengatakan “ya Allah, baguskanlah untukku dan akhlakku”.
Diantara pebuatan baik adalah pergaulan yang baik, perbuatan mulia, perkataan yang lembut, mendermakan kebaikan, memberi makan, menyebarkan salam, mengunjungi orang muslim yang sakit baik yang berbuat baik maupun yang berbuat durhaka, mengantarkan jenazah orang muslim, bertetangga secara baik apakah itu muslim maupun kafir, dan lain-lain.
Anas r.a berkata “Rasulullah tidak membiarkan nasehat yang baik melainkan mengajak kami kepadanya dan menyuruh kami mengerjakannya. Beliau tidak membiarkna menipu atau mengatakan: mencela dan tidak pula membiarkan sesuatu melainkan mengingatkan kami dan melarang kami melakukannya. Dari semua itu cukuplah surat annahl ayat 90. Yang artinya:
•
Artinya: “ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl 90)
Akhlak Rasulullah menjadi pedoman bagi masyarakat sejak dulu hingga sekarang. Sifat beliau merupakan suatu tenaga yang mempertalikan antara anggota-anggota masyarakat itu dengan satu ikatan yang teguh, dan pimpinan beliau menjadi ilham kebaikan umat islam dari dahulu hingga sekarang.
C. Macam-macam Akhlak
1. Akhlakul Karimah
Akhlakul karimah atau akhlak yang mulia amat banyak jumlahnya, namun dapat dilihat dari segi hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia, akhlak mulia itu dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama akhlak mulia kepada Allah, kepada diri sendiri dan terhadap sesame manusia.
a. Akhlak terhadap Allah
Titik tolak akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Dia memiliki sifa-sifat terpuji demikian Agung sifat itu, yang jangankan manusia, malaikat pun tidak akan menjangkau hakikat-Nya.
Banyak alas an mengapa manusia harus berakhlak baik terhadap Allah. Diantaranya adalah hal-hal sebagai berikut:
Karena Allah terlah menciptakan manusia dengan segala keistimewaan dan kesempurnaannya. Sebagai yang diciptakan sudah sepantasnya manusia berterimakasih kepada yang menciptakannya.
Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (QS at-tiin: 4).
Karena Allah telah memberikan perlengkapan panca indera hati nurani dan naluri kepada manusia. Semua potensi jasmani dan rohani amat tinggi nilainya, karena dengan potensi tersebut manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dalam berbagai bidang kehidupan yang membawa pada kejayaan
•
Artinya: dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. (QS an-nahl 78)
Karena ALalh menyediakan berbagai bahan dan sarana kehidupan yang terdpat di bumi, seperti tumbuhan, air, udara, binatang dsb. Semua itu tunduk kepada kemauan manusia atau siap untuk dimanfaatkan.
• •
Artinya: Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia -Nya dan Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-JAtsiyah 12-13)
Dengan keterangan diatas sudah sepantasnya dan sewajarnya manusia berakhlak baik dan taat kepada Allah, dan alangkah tidak wajarbnya bila manusia durhaka terhadapa Allah.
“Hai anak Adam taatlah kamu kepada Tuhanmu niscaya kamu dinamakan orang yang berkal da janganlah kamu durhaka kepadaNya sehingga kamu dinamakan oragn yang Bodoh”. (HR. Abu Na’im)
b. Akhlak yang Baik terhadap Diri Sendiri
Selaku individu, manusi diciptakan oleh Allah swt dengan segala kelengkapan jasmaniayah dan rohaniyahnya. Ia diciptakan dengan dilengkapai rohani seperti akal pikiran, hati nurani, naluri dan kecakapan batiniyah atau bakat. Dengan kelengkapan rohani ini manusia dapat memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya secara konseptual dan terencana, dapat menimbang antara baik dan salah dapat memberikan kasih sayang yang selanjutnya dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan peradaban yang mengangkat harkat dan martabatnya.
Disamping itu seorang muslim juga beriman dan percaya bahwa yang dapat membersihkan jiwa dan menyelamatkannya iman yang baik, amal yang salih, sedangkan yang mengotori dan merusaknya adalah dampak negative dari kekafiran dan perbuatan maksiat.
Untuk menjalankan perintah Allah d an bimbingan Nabi Muhammad saw maka setiap umat islam harus berakhlak dan bersikap sebagai berikut:
1. hindarkan makanan beracun/ keras
2. hindarkan perbuatan yang tidak baik
3. memelihara kesucian jiwa
4. pemaaf dan pemohon maaf
5. sikap sederhana dan jujur
6. hindarkan perbuatan tercela
Manusia yang berakhlak baik terhadap dirinya sendiri adalah manusia yang terbina sumber dayanya secara optimal.
c. Akhlak Yang Baik Terhadap Sesama Manusia
Manusia adalah sebagai makhluk sisoal yang kelanjutan eksistensinya secara fungsional dan optimal banyak banyak bergantung pada orang lain. Untuk itu ia perlu bekerjasama dan saling tolong menolong dengan orang lain. Oleh karenanya ia perlu menciptakan suasana yang baik satu dan lalinnya sa;ing berakhlak yang baik. Caranya dapat dilakukan dengan memuliakannya, memberikan bantuan, pertolongan dan menghargainya.
2. Akhlak Madzmumah
Akhlak yang tercela secara umum adalah lawan atau kebalikan dari akhlak yang baik. Berdasarkan petunjuk islam, dijumpai berbagai macam akhlak tercela, diantaranya:
a. takabbur
b. berbohong
c. dengki
d. bakhil
D. Sendi-Sendi Akhlak
Akhlak dalam wujud pengembangannya dibedakan menjadi dua yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Jika ia sesuai dengan perintah Allah dan RasulNya yang kemudian menghasilkan akhlak terpuji, maka itulah yang dinamakan akhlak mahmudah.
Sedangkan jika ia sesuai dengan apa yang dilarang Allah dan RAsulnya dan melahirkan perbuatan yang buruk, maka itulah yang disebut sebagai akhlak madzmummah.
1. Akhlak Mulia
Tentang akhlak yang terpuji menurut Imam Al- Ghazali ada empat sendi yang cukup mendasarkan menjadi induk seluruh akhlak, yaitu:
a. kekuatan ilmu wujudnya adalah hikmah (kebijaksanaan), yaitu keadaan jiwa yang bias menentukan hal-hal yang benar diantara yang salah dalam urusan ikhtiyariyah (perbuatan yang dilaksanakan dengan pilihan dan kemauan sendiri)
b. kekuatan marah wujudnya adalah syaja’ah (berani) yaitu keadaan kekuatan amarah yang tunduk pada akal pada waktu dilahirkan atau dikekang.
c. Kekuatan nafsu syahwat wujudnya adalah ‘iffah (perwira) yaitu keadaan syahwat yang terdidik oleh akal dan syari’at agama
d. Kekuatan keseimbangan diantara kekuatan yang tiga diatas wujudnya ialah adil yaitu kekuatan jiwa yang dapat menuntun amarah dan syahwat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hikmah.
Dari empat sendi akhlak terpuji di atas akan lahir perbuatan-perbuatan seperti: jujur, suka memberi, tawadhu’, tabah, tinggi cita-cita, pemaaf, kasih saying terhdap sesama, berai dalam kebenaran, menghormati orang lain, sabar, pemalu, pemurah, memlihara rahasia, konaah, menjaga diri dalam ketaatan, dll.
2. Akhlak Tercela
Untuk akhlak tercela pun ada sendi-sendi yang patut diketahui yang menjadi sumber timbulnya perbuatan perbuatan yang tidak baik. Yaitu:
• khubsan wa jarbazah (keji dan pintar busuk)
• tahawwur (berani tapi sembrono), jubun (penakut) dan khauran (lemah)
• syarhan (rakus) dan jumud
• zalim
Keadaan ini adalah pangkal yang menetukan corak hidup manusia.
E. Hukum-Hukum Akhlak
Akhlak adalah sifat yang harus dimiliki setiap muslim ketika sedang melakukan aktivitas. Sifat tersebut berkaitan dengan kativitas yang dilakukan atau ditinggalkan oleh seseorang. Sifat tersebut ada yang hasan (terpuji), qabih (tercela) dan ada yang khayr (baik) dan syarr (buruk). Dalam hal ini silam telah mengatur sifat perbuatan tersebut dalamkonteks hubungan manusia dengan dirinya. Artinya, bagaimana seseorang memperhatikan kesempurnaan perbuatannya dengan menjadikan sifat tertentu sebagai sifat perbuatannya. Semua itu telah diatur oleh islam dalam bentuk hokum syara’ yang spesifik, dan tidak diserahkan kepada manusia itu sendiri untuk menentukannya. Sebab, jika diserahkan kepada manusia untuk menentukan sendiri sifat perbuatannya, apsti dia hanya akan melihat dari aspek yang menguntungkan atau merugikan bagi dirinya. Ini artinya, jika hal itu menguntungkan, ia dianggap baik dan sebaliknya jika merugikan, ia dianggap buruk. Disisi lain, ia akan menggunakan standard benda sebagai standar terpuji dan tercela, seperti manis digambarkan dengan baik, sedangkan pahit akan digambarkan dengan buruk. Meskipun masalah sifat tersebut ditetapkan oleh syara’, tetapi syari’at islam tidak banyak membahas hokum tersebut secara detail.
Dilihat dari aspek cirri khasnya: ada beberapa cirri khas yang ditetapkan oleh Allah swt dalam maslaah akhlak ini antara lain:
1. Akhlak tidak bisa dipisahkan dari hokum syara’, termasuk semua bentuk ketentuan hukum syara’ yang lain. Seperti khusu’ adalah sifat perbuatan orang yang sedang mengerjakan sholat, yang tidak ada pada orang diluar sholat. Jujur, amanah dan menunaikan janji adalah sifat perbuatan orang yang melakukan mu’ammalah (berhubungan dengan orang lain).
2. Akhlak juga tidak bias didasarkan pada ‘illat, sehingga tidak ada satu ‘illat pun dalam masalah akhklak. Jujur, amanah dan menunaikan janji diperintahkan semata-mata karena hukumya adalah wajib menurut syara’, yang kewaibannya telah ditentukan oleh nash, bukan disebabkan adanya ‘illat tertentu. Maka kejujuran, amanah dan menepati janji tersebut tidak bias dilandaskan oleh seorang muslim karena keuntungan material, atau mengharapkan pujian orang dan sebagainya.
3. Akhlak juga tunduk pada manfaat tertentu. Sebab, orang yang melakukan hukum akhlak kadang-kadang malah mendapatkan kerugian, bukan keuntungan. Contoh, sifat berani dan menentang ketika mengingatkan penguasa yang zalim adalah sifat pengemban dakwah yang mulia. Sesuatu yang bias mengakibatkan orang tersebu6t menemui ajalnya. Sebagimana sebda Nabi Saw:
“ penghulu para syahid adalah Hamzah bin ‘Abdul Muthollib, serta orang yang berdiri didepan penguasa dzalim, lalu memerintahkan (kema’rufan) dan mencegah (kemunkaran) atasnya, kemudian dia pun membunuhnya.” (HR. Hakim dari Jabir).
4. Akhlak sama dengan akidah. Akhlak merupakam tuntunan fitrah manusia. Memuliakan tamu dan mebmantu orang yang memerlukan adlah sangat selaras dengan fitrah manusia yaitu naluri mempertahankan diri. Khusu’ dan tawaddu’ juga selaras dengan fitrah manusia yaitu naluri beragama. Kasih sayang dan keta’atan juga sesuai dengan fitrah manusia yaitu naluri menyayangi.
Dari aspek pengaruh: jika sifat perbuatan (akhlak) tersebut dimiliki oleh seorang muslim ketika melakukan aktivitas, maka akan mempunyai pengaruh yang signifikan, antara lain:
1. Melaksanakan akhlak dengan taklif syar’I yang lain akan menjadikan seorang muslim memiliki kepribadian yang khas ketika berinteraksi dengan khalayak ramai. Mereka pun percaya dengan kata-kata dan perbuatannya.
2. Akhlak akan bias menumbuhkan kasih sayang dan sikap hormat khususnya antara sesama anggota keluarga, dan umumnya dengan aggota masyarakat.
3. Orang yang mempunyai sifat perbuatan (akhak) yang terpuji akan mendapatkan pahala yang banyak disisi Allah swt di akhirat. Bahkan orang yang mempunyai akhlak yang mulia didunia akan dekat dengan Rasulullah saw di akhirat. Sabda baginda Nabi:
“Sesungguhnya orang yang paling aku cintai diantara kalian, dan lebih dekat kepada ku temmpatnya di hari kiamat adalah siapa saja yang diantara kalian yang paling baik akhlaknya.” (HR Bukhori).
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Hafidz. 2004. Dirkursus Islam Politik Spiritual. Bogor: Al-Azhar Press.
Ardani. 2001. Akhlak Tasawwuf. Jakarta: CV. Karya Mulia.
BAB II
PENGERTIAN EVALUASI, EVALUASI PENDIDIKAN DAN HUBUNGAN ANTARA PENGUKURAN DAN PENILAIAN SERTA FUNGSI, TUJUAN, KEGUNAAN, KLASIFIKASI, OBJEK DAN SUBJEK SERTA RUANG LINGKUP EVALUASI PENDIDIKAN
A. PENGERTIAN EVALUASI DAN EVALUASI PENDIDIKAN
Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris education; dalam bahasa Arab: At-Taqdir; dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Dengan demikian secara harfiyah dapat evaluasi pendidikan diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.
Adapun dari segi istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Edwind Wandt dan Gerald W. Brown (1977) evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Apabila definisi Edwind Wandt dan Gerald W. Brown (1977) digunakan untuk memberi definisi tentang evaluasi pendidikan, maka evaluasi pendidikan itu dapat diberi pengertian sebagai suatu tindakan atau kegiatan (yang dilaksanakan dengan maksud untuk) atau suatu proses (yang berlangsung dalam rangka) menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan (yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan, atau yang terjadi di lapangan pendidikan). Atau singkatnya evaluasi pendidikan adalah kegiatan atau proses penentuan nilai pendidikan sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya.
Menurut Guba dan Lincoln evaluasi merupakan suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan. Sesuatu yang dipertimbangkan itu bisa berupa orang, benda, kegiatan atau keadaan tertentu. dari konsep diatas ada dua hal yang menjadi karakteristik evaluasi. Pertama, evaluasi merupakan suatu proses. Artinya, dalam suatu pelaksanaan evaluasi mestinya terdiri dari beberapa macam tindakan yang harus dilakukan. Kedua, evaluasi berhubungan dengan pemberian nilai atau arti. Artinya, evaluasi dapat menunjukan kualitas yang dinilai.
Lembaga Administrasi Negara mengemukakan batasan mengenai evaluasi pendidikan sebagai berikut:
Evaluasi pendidikan adalah:
1) Proses atau kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan, dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan;
2) Usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik bagi penyempurnaan pendidikan.
Bagan di bawah ini menunjukkan pada kita bahwa dalam proses penilaian dilakukan pembandingan antara informasi-informasi yang telah berhasil dihimpun dengan kriteria tertentu, untuk kemudian diambil keputusan atau dirumuskan kebijaksanaan tertentu. Kriteria atau tolak ukur yang di pegangi tidak lain adalah tujuan yang sudah ditentukan terlebih dahulu sebelum kegiatan pendidikan itu dilaksanakan.
BAGAN TENTANG EVALUASI PENDIDIKAN
B. HUBUNGAN ANTARA PENILAIAN (EVALUATION) DENGAN PENGUKURAN (MEASUREMENT)
Pengukuran dalam bahasa Inggris disebut dengan measurement dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran tertentu.
Evaluasi memiliki makna yang berbeda dengan pengukuran. Pengukuran pada umumnya berkenaan dengan masalah kuantitatif untuk mendapatkan informasi yang diukur. Oleh sebab itu, dalam proses penngukuran diperlukan alat bantu tertentu. denagn demikian, antara evaluasi dan pengukuran tidak bisa disamakan walaupun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Evaluasi akan lebih tepat manakala didahului oleh proses pengukuran, sebaliknya hasil pengukuran tidak akan memiliki arti apa-apa manakala tidak dikaitkan dengan proses evaluasi. Jadi, pengukuran itu hanya bagian dari evaluasi dan tes bagian dari pengukuran. Ini berarti sebelum dilakukan evaluasi, didahului oleh pengukuran. Dan pengukuran adalah hasil dari suatu tes.
Dari penjelasan di atas, maka pengukuran adalah proses pengumpulan data yang diperlukan dalam rangka memberikan judgement yakni berupa keputusan terhadap sesuatu.
Pengukuran yang bersifat kuantitatif itu dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu
1. Pengukuran yang dlakukan bukan untuk menguji sesuatu. Misalnya pengukuran yang dilakukan penjahit pakaian.
2. Pengukuran yang dilakukan untuk menguji sesuatu. Misalnya pengukuran untuk menguji daya tahan perbaja terhadap tekanan berat.
3. Pengukuran untuk menilai, yang dilakukan dengan jalan menguji sesuatu. Misalnya pengukuran kemajuan belajar peserta didik dalam rangka mengisi nilai rapor yang dilakukan dengan menguji mereka dalam bentuk tes hasil belajar.
Pengukuran jenis ketiga inilah yang digunakan dalam dunia pendidikan.
Penilaian berarti menilai sesuatu. Sedangkan menilai adalah mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mendasarkan diri atau berpegang pada ukuran baik dan buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh dan sebagainya. Jadi penilaian itu sifatnya adalah kualitatif.
Sedangkan evaluasi adalah mencakup dua kegiatan tadi, yaitu pengukuran dan penilaian. Evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk menilai sesuatu. Untuk dapat menentukan nilai dari sesuatu yang sedang dinilai itu dilakukanlah pengukuran, dan wujud dari pengukuran itu adalah pengujian, dan pengujian inilah yang dalam dunia kependidikan dikenal dengan istilah tes.
Lebih lanjut dikatakan bahwa istilah penilaian mempunyai arti yang lebih luas di bandingkan dengan istilah pengukuran. Sebab pengukuran itu sebenarnya hanyalah merupakan suatu langkah atau tindakan yang kiranya perlu diambil dalam rangka pelaksanaan evaluasi. Dikatakan “perlu diambil” karena tidak semua penilaian itu harus senantiasa di dahului oleh tindakan pengukuran secara lebih nyata.
Namun demikian tidak dapat disangkal adanya kenyataan bahwa evaluasi dalam bidang pendidikan-(khususnya evaluasi terhadap prestasi belajar peserta didik)- sebagian besar bersumber dari hasil-hasil pengukuran. Evaluasi mengenai proses pembelajaran disekolah tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik apabila evaluasi itu tidak didasarkan atas data yang bersifat kuantitatif. Inilah sebabnya mengapa dalam praktek masalah pengukuran mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses evaluasi. Baik buruknya evaluasi akan bergantung pada hasil- hasil pengukuran yang mendahuluinya. Hasil pengukuran yang kurang cermat akan memberikan hasil evaluasi yang kurang cermat pula ; sebaliknya teknik pengukuran yang tepat diharapkan dapat memberikan landasan yang kokoh untuk mengadakan evaluasi yang tepat.
Dalam rangka mempertegas perbedaan pengukuran dengan penilaian Wandt dan Brown mengatakan bahwa, pengukuran adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas atau kuantitas dari sesuatu; ia akan memberikan jawaban atas pertanyaan How much?. Adapun penilaian atau evaluasi adalah tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu, dan akan memberikan jawaban atas pertanyaan, What value?.
Perbedaan lainnya antara pengukuran dan penilaian adalah bahwa penilaian lebih banyak melibatkan unsur subyektifitas daripada pengukuran. Dalam hal ini Stanley dan Hopkins berpendapat bahwa: “penilaian selalu melibatkan lebih banyak unsur subyektifitas daripada pengukuran, tapi suatu pengukuran yang paling obyektif sekalipun tidak akan terlepas dari unsur subyektifitas.”
Dalam proses penilaian hasil belajar, pengukuran mempunyai peranan yang sangat penting. Yakni, untuk mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan tujuan penilaian yang bersangkutan.
C. FUNGSI EVALUASI PENDIDIKAN
Secara umum, evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidak-tidaknya memiliki tiga macam fungsi pokok yaitu
a. Mengukur kemajuan
b. Menunjang penyusunan rencana
c. Memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali
Seperti telah di kemukakan dalam pembicaraan terdahulu, evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk mengukur dan selanjutnya menilai, sampai dimanakah tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan. Apabila tujuan yang telah dirumuskan itu direncanakan untuk dicapai secara bertahap, maka dengan evaluasi yang berkesinambungan akan dapat di pantau, tahapan manakah yang sudah dapat di selesaikan, tahapan manakah yang berjalan dengan mulus, dan mana pula tahapan yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Walhasil dengan evaluasi terbuka kemungkinan bagi evaluator untuk mengukur seberapa jauh atau seberapa besar kemajuan atau perkembangan program yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah dirumuskan.
Setidak-tidaknya ada dua macam kemungkinan hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi; yaitu:
1) Hasil evaluasi itu ternyata menggembirakan, sehingga dapat memberikan rasa lega bagi evaluator, sebab tujuan yang telah ditentukan dapat di capai sesuai dengan yang direncanakan
2) Hasil evaluasi ternyata tidak menggembirakan atau bahkan mengkhawatirkan, dengan alasan bahwa adanya penyimpangan-penyimpangan, hambatan dan kendala, sehingga mengharuskan evaluator bersikap waspada. Ia perlu memikirkan dan dan melakukan pengkajian ulang terhadap rencana yang telah disusun atau mengubah dan memperbaiki cara pelaksanaannya. Berdasar data hasil evaluasi itu selanjutnya dicari metode-metode lain yang dipandang lebih tepat dan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sudah barang tentu perubahan-perubahan itu membawa dampak atau konsekuensi berupa perencanaan ulang (re-plening). Dengan demikian dapat di katakan bahwa evaluasi itu memiliki fungsi: menunjang penyusunan rencana.
Evaluasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan, akan membuka peluang bagi evaluator untuk membuat perkiraan, apakah tujuan yang telah dirumuskan akan dapat di capai pada waktu yang telah di tentukan,ataukah tidak. Apabila berdasar data hasil evaluasi itu diperkirakan bahwa tujuan tidak akan dapat di capai sesuai dengan rencana, maka evaluator akan berusaha untuk mencari dan menemukan factor-faktor penyebabnya, serta mencari dan menemukan jalan keluar atau cara-cara pemecahannya. Bukan tidak mungkin, bahwa atas dasar data hasil evaluasi itu evaluator perlu mengadakan perubahan-perubahan, penyempurnaan-penyempurnaan yang menyangkut organisasi, tata kerja, atau mungkin juga perbaikan terhadap tujuan organisasi itu sendiri. Jadi, kegiatan evaluasi pada dasarnya juga di maksudkan untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan usaha.
Adapun secara khusus, fungsi evaluasi dalam dunia pendidikan dapat ditillik dari tiga segi, yaitu:
a. Segi psokologis
b. Segi didaktik
c. Segi administratif.
Secara psikologis, kegiatan evaluasi dalam bidang pendidikan di sekolah dapat disoroti dari dua sisi. Yaitu dari sisi peserta didik dan dari sisi pendidik.
Bagi peserta didik, evaluasi pendidikan secara psikologis akan memberikan pedoman atau pegangan batin kepada mereka untuk mengena kapasitas dan status dirinya masing-masing ditengah-tengah kelompok atau kelasnya. Dengan dilakukannya evaluasi hasil belajar siswa misalnya, maka para siswa akan mengetahui apakah dirinya termsuk siswa yang berkemampuan tinggi, berkemampuan rata-rata, ataukah berpengetahuan rendah.
Bagi pendidik, evaluasi pendidikan akan memberikan kepastian atau ketetapan hati kepada diri peserta tersebut. Sedah sejauh manakah kiranya usaha yang telah dilakukannya selama ini telah membawa hasil, sehingga ia secara psikologis memiliki pedoman atau pegangan batin yang pasti guna menentukan langkah-langkah apa saja yang di pandang perlu dilakukan selanjutnya. Misalnya dengan menggunakan metode-metode mengajar tertentu, hasil-hasil belajar siswa telah menunjukkan adanya peningkatan daya serap terhadap materi yang telah diberikan kepada para siswa tersebut; karena itu atas dasar hasil evaluasi tersbut penggunaan metode mengajar tadi akan terus dipertahankan. Begitupun sebaliknya.
Bagi peserta didik, secara didaktik evaluasi pendidikan akan dapat memberikan dorongan (motivasi) kepada mereka untuk dapat memperbaiki, meningkatkan dan mempertahankan prestasinya.
Bagi pendidik, secara didaktik evaluasi pendidikan itu setidak-tidaknya memiliki lima macam fungsi, yaitu:
1. Memberikan landasan untuk menilai hasil usaha (prestasi) yang telah di capai oleh peserta didiknya
2. Memberikan informasi yang sangat berguna, guna mengetahui posisi masing-masing peserta didik di tengah-tengah kelompoknya.
3. Memberikan bahan yang penting untuk memilih dan kemudian menetapkan status peserta didik.
4. Memberikan pedoman untuk mencari dan menemukan jalan keluar bagi peserta didik yang memang memerlukannya.
5. Memberikan petunjuk tentang sudah sejauh manakah program pengajaran yang telah di tentukan telah dapat dicapai.
Adapun secara administrative, evaluasi pendidikan setidak-tidaknya memiliki tiga macam fungsi, yaitu:
1. Memberikan laporan
2. Memberikan bahan-bahan keterangan (data)
3. Memberikan gambaran
Menurut Wina Sanjaya dalam bukunya Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran ada bberapa fungsi evaluais, yakni :
a. Evaluasi merupakan alat yang penting sebagai umpan balik bagi siswa.
b. Evaluasi merupakan alat untuk mengetahui bagaimana ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan.
c. Evaluasi dapat memberikan informasi untuk mengembangkan program kurikulum.
d. Informasi dari hasil evaluasi dapat digunkan oleh siswa untuk mengambil keputusan secara individual khususnya dalam menentukan masa depan sehubungan dengan pemilihan bidang pekerjaan.
e. Evaluasi berguna untuk para pengembang kurikulum dalam menentukan kejelasan tujuan khusus yang ingin dicapai.
f. Evaluasi berfungsi sebagai umpan balik untuk semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan di sekolah.
D. TUJUAN EVALUASI PENDIDIKAN
1. Tujuan umum
Secara umum, tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan ada dua, yaitu :
a. Untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang di alami oleh para peserta didik, setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. dengan kata lain tujuan umum dari evaluasi dalam pendidika adalah untuk memperoleh data pembuktian, yang akan menjadi petunjuk sampai di mana tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian tujuan-tujuan kurikuler, setelah mereka menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
b. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pembelajaran yang telah di pergunakan dalam prses pembelajaran.tujuan kedua dari evaluasi pendidikan adalah untuk mengukur dan menilai sampai dimanakah efektivitas mengajar dan metode-metode mengajar yang telah diterapkan atau dilaksanakan oleh pendidik, serta kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh peserta didik.
2. Tujuan khusus
Tujuan khusus dari kegiatan evaluasi dalam bidang pendidikan adalah :
a. Untu merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Tanpa adanya evaluasi maka tidak mungkin timbul kegairahan atau rangsangan pada diri peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing.
b. Untuk mencari dan menemukan factor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya.
E. KEGUNAAN EVALUASI PENDIDIKAN
Di antara kegunaan yang dapat dipetik dari kegiatan evaluasi dalam bidang pendidikan adalah :
1. Terbukanya kemungkinan bagi evaluator guna memperoleh informasi tentang hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pelaksanaan program pendidikan.
2. Terbukanya kemungkinan untuk dapat diketahuinya relevansi antara program pendidikan yang telah dirumuskan dengan ujuan yang hendak dicapai.
3. Terbukanya kemungkinan unuk dapat dilakukannya usaha perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan progam pendidikan yang dipandang lebih berdaya guna dan berhasil guna, sehingga tujuan yang dicita-citakan, akan dapat dicapai dengan hasil yang sebaik-baiknya.
F. KLASIFIKASI EVALUASI PENDIDIKAN
Klasifikasi atau penggolongan evaluasi dalam bidang pendidikan sangat beragam. Sangat beragamnya pengklasifikasian atas evaluasi pendidikan itu disebabkan karena sudut pandang yang saling berbeda dalam melakukan pengklasifikasian tersebut. Salah satu cara pengklasifikasian terhadap evaluasi pendidikan itu adalah dengan jalan membedakan evaluasi pendidikan tersebut atas tiga kategori, yaitu:
1. Klasifikasi evaluasi pendidikan yang didasarkan pada fungsi evaluasi dalam proses pendidikan.
Dilihat dari segi fungsi yang dimiliki maka evaluasi pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu:
a. Evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebuthuan psikologis
b. Evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan didaktik
c. Evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebuutuhan administrative.
2. Klasifikasi evaluasi pendidikan yang didasarkan pada pemanfaatan informasi yang bersumber dari kegiatan evaluasi itu sendiri.
Dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan pendidikan, evaluasi dalam bidang pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu:
a. Evaluasi pendidikan yang mendasarkan diri pada banyaknya orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan pendidikan.
Evaluasi jenis ini dapat dibedakan menjadi dua golongan:
1) Evaluasi pendidikan dalam rangka pengambilan keputusan pndidikan yang bersifat individual.
Yang dimaksud dengan keputusan pendidikan yang bersifat individual adalah keputusan-keputusan pendidikan yang dibuat oleh individu-individu yang secara langsung hanya menyangkut individu tertentu. contoh keputusan rektor untuk membebaskan seorang mahasiswa dari kewajiban membayar SPP karena mahasiswa tersebut setelah di evaluasi ternyata adalah mahasiswa terbaik.
2) Evaluasi pendidikan dalam rangka pengambilan keputusa pedidikan yang bersifat institusional. Maksudnya adalah keputusan pendidikan yang dibuat oleh lembaga pendidikan tertentu ditujukan untuk orang banyak.
b. Evaluasi pendidikan yang mendasarkan diri pada jenis atau macamnya keputusan pendidikan.
Berdasarkan klasifikasi ini, maka evaluasi pendidikan dibedakan menjadi empat golongan, yaitu :
1) Evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan yang bersifat didaktik. Contoh keputusan mengenai keharusan bagi murid kelas VI yang akan mengikuti UN unuk mengikuti les tambahan. Keputusan ini diambil setelah memperhatikan hasil evaluasi belajar yang rendah.
2) Evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan yang bersifat bimbingan dan penyuluhan. Contoh keputusan untuk menyelenggarakan ceramah keagamaan secara rutin seperti ceramah mengenai kenakalan remaja.
3) Evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan yang bersifat administrative. Contoh penentuan siswa yang dapat dinyatakan naik kelas atau tinggal kelas dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai hasil belajar yang tercantum dalam buku rapor.
4) Evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan penelitian ilmiah atau riset. Contoh sebuah perguruan tinggi mengdakan riset tentang evaluasi dalam rangka mengatahui kualitas tes seleksi penerimaan calon mahasiswa baru, terutama dari segi validitas dan reliabilitasnya. Hasil penelitian tersebut selanjutnya digunakan untuk memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan mutu tes seleksi itu.
3. Evaluasi pendidikan yang dilatar belakangi oleh pertanyaan dimana atau pada bagian manakah evaluasi itu dilaksanakan dalam rangka proses pendidikan.
Dari klasifikasi ini dapat dibedakan menjadi dua gologan:
a. Evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan ditengah-tengah atau pada saat berlangsungnya proses pembelajaran.
b. Evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan seelah seluruh unit pelajaran selesai diajarkan.
G. OBYEK EVALUASI PENDIDIKAN
Obyek atau sasaran evaluasi pendidikan ialah segala sesuatu yang betalian dengan kegiatan atau proses pendidikan, yang dijadikan titik pusat perhatian atau pengamatan, karena pihak penilai (evaluator) ingin memperoleh informasi tentang kegiatan atau proses pendidikan tersebut. Salah satu cara untuk mengenal atau mengetahui obyek dari evaluasi pendidikan adalah dengan jalan menyorotinya dari tiga segi, yaitu dari segi input, transformasi dan out put. Ditilik dari segi input ini maka obyek dari evaluasi pendidikan meliputi tiga aspek, yaitu:
1. Aspek kemampuan
Untuk dapat diterima sebagai calon peserta didik dalam rangka mengikuti program pendidikan tertentu, maka para calon peserta didik harus memiliki kemampuan yang sesuai atau memadai, sehingga dalam mengikuti proses pembelajaran pada program pendidikan tertentu itu nantiya peserta didik tidak akan mengalami banyak hambatan atau kesulitan.
sehubungan dengan itu, maka bekal kemampuan yang dimiliki calon peserta didik perlu untuk dievaluasi terlebih dahulu, guna mengetahui sampai sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing calon peserta didik dalam mengikuti program tertentu. adapun alat yang biasa dipergunakan dalam rangka mwngevaluasi kemampuan peserta didik itu adalah tes kemampuan (aptitude test)
2. Aspek kepribadian
Kepribadian adalah sesuatu yang terdapat pada diri seseorang, dan menampakkan bentuknya dalam tingkah laku. Sebelum mengikuti program pendidikan tertentu, para calon peserta didik perlu terlebih dahulu dievaluasi kepribadiannya masing-masing, sebab baik buruknya kepribadian mereka secara psikologis akan dapat memperngaruhi keberhasilan mereka dalam mengikuti program pendidikan tertentu. evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui atau mengungkapkan kepribadian seseorang adalah dengan jalan menggunakan tes kepribadian (personality test).
3. Aspek sikap
Sikap pada dasarnya adalah merupakan bagian dari tingkah laku manusia, sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang memancar keluar. Karena sikap ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam pergaulan, maka memperoleh informasi mengenai sikap sseorng adalah hal yang sangat penting. Karena itu maka aspek sikap perlu dinilai atau di evaluasi terlebih dahulu bagi calon peserta didik sebelum mengikuti program pendidikan tertentu.
Selanjutnya apabila disoroti dari segi transformasi maka obyek dari evaluasi pendidikan itu meliputi :
a. Kurikulum atau materi pelajaran
b. Metode mengajar dan teknik penilaian
c. Sarana atau media pendidikan.
d. System administrasi
e. Guru dan unsur-unsur personal lainnya.
Adapun dari segi output, yang menjadi sasaran evaluasi pendidikan adalah tingkat pencapaian atau prestasi belajar yang berhasil diraih oleh masing-masing peeserta didk, setelah mereka terlibat dalam proses pendidikan selama jangka waktu yang telah ditentukan.
H. SUBYEK EVALUASI PENDIDIKAN
Subyek atau pelaku evaluasi pendidikan ialah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi dalam bidang pendidikan.
Berbicara tentang subyek evaluasi pendidikan di sekolah kiranya perlu dikemukakan disini bahwa mengenai siapa yang disebut sebagai subyek evaluasi pendidikan itu akan sangat bergantung pada, atau ditentukan oleh suatu aturan yang menetapkan pembagian tugas untuk melakukan evaluasi tersebut. Jadi subyek evaluasi pendidikan itu dapat berbeda-beda orangnya.
Dalam kegiatan valuasi pendidikan dimana sasaran evalusinya adalah prestasi belajar siswa, maka subyek evaluasinya adalah guru atau dosen yang mengasuh mata pelajaran tertentu. jika evaluasi yang dilakukan itu sasarannya adalah sikap peserta didik, maka subyek evaluasinya adalah guru atau petugas yang sebelum melaksanakan evaluasi tentang sikap itu, terlebih dahulu telah memperoleh pendidikan atau latihan (training) mengenai cara-cara menilai sikap seseorang. Adapun apabila sasaran yang di evaluasi adalah kepribadian peserta didik, dimana pengukuran tentang kepribadian itu dilakukan dengan menggunakan instrument berupa test yang sifatnya baku. Maka subyek evaluasinya tidak bisa lain kecuali seorang psikolog.
I. RUANG LINGKUP EVALUASI PENDIDIKAN
Secara umum ruang lingkup dari evaluasi dalam bidang pendidikan di sekolah mencakup tiga komponen utama yaitu :
1. Evaluasi program pengajaran
Evaluasi atau penilaian terhadap program pengajaran akan mencakup tiga hal, yaitu:
a. Evaluasi terhadap tujuan pengajaran
b. Evaluasi terhdap isi program pngajaran
c. Evaluasi terhadap strategi belajar mengajar.
2. Evaluasi proses pelaksanaan pengajaran
Evaluasi mengenai proses peaksanaan pengajaran akan mencakup :
a. Kesesuaian antara proses belajar mengajar yang berlangsung, dengan garis-garis besar program pengajaran yang telah ditentukan.
b. Kesiapan guru dalam melaksanakan program pengajaran.
c. Kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.
d. Minat atau perhatian siswa didalam mengikuti pelajaran.
e. Keaktifan atau partisipasi siswa selama proses pembelajaran berlangsung.
f. Peranan bimbingan dan penyuluhan terhadap siswa yang memerlukannya.
g. Komunikasi dua arah antara guru dan murid selama proses pembelajaran berlangsung.
h. Pemberian dorongan atau motivasi terhadap siswa.
i. Pemberian tugas-tugas kepada siswa dalam rangka penerapan teori-teori yang diperoleh didalam kelas dan upaya menghilangkan dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah.
3. Evaluasi hasil belajar
Evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik ini mencakup:
a. Evaluasi mengenai tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai dalam unit-unit program pengajaran yang bersifat terbatas.
b. Evaluasi mengenai tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan-tujuan umum pengajaran.
DAFTAR PUSTAKA
Sudijono, Anas. 1996. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.
Sanjaya, Wina. 2008. Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: Prenada media Group.
Mudjijo. 1995. Tes Hasil Belajar. Jakarta: Bumi Aksara.
[ Read More ]
PENGERTIAN EVALUASI, EVALUASI PENDIDIKAN DAN HUBUNGAN ANTARA PENGUKURAN DAN PENILAIAN SERTA FUNGSI, TUJUAN, KEGUNAAN, KLASIFIKASI, OBJEK DAN SUBJEK SERTA RUANG LINGKUP EVALUASI PENDIDIKAN
A. PENGERTIAN EVALUASI DAN EVALUASI PENDIDIKAN
Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris education; dalam bahasa Arab: At-Taqdir; dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Dengan demikian secara harfiyah dapat evaluasi pendidikan diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.
Adapun dari segi istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Edwind Wandt dan Gerald W. Brown (1977) evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Apabila definisi Edwind Wandt dan Gerald W. Brown (1977) digunakan untuk memberi definisi tentang evaluasi pendidikan, maka evaluasi pendidikan itu dapat diberi pengertian sebagai suatu tindakan atau kegiatan (yang dilaksanakan dengan maksud untuk) atau suatu proses (yang berlangsung dalam rangka) menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan (yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan, atau yang terjadi di lapangan pendidikan). Atau singkatnya evaluasi pendidikan adalah kegiatan atau proses penentuan nilai pendidikan sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya.
Menurut Guba dan Lincoln evaluasi merupakan suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan. Sesuatu yang dipertimbangkan itu bisa berupa orang, benda, kegiatan atau keadaan tertentu. dari konsep diatas ada dua hal yang menjadi karakteristik evaluasi. Pertama, evaluasi merupakan suatu proses. Artinya, dalam suatu pelaksanaan evaluasi mestinya terdiri dari beberapa macam tindakan yang harus dilakukan. Kedua, evaluasi berhubungan dengan pemberian nilai atau arti. Artinya, evaluasi dapat menunjukan kualitas yang dinilai.
Lembaga Administrasi Negara mengemukakan batasan mengenai evaluasi pendidikan sebagai berikut:
Evaluasi pendidikan adalah:
1) Proses atau kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan, dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan;
2) Usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik bagi penyempurnaan pendidikan.
Bagan di bawah ini menunjukkan pada kita bahwa dalam proses penilaian dilakukan pembandingan antara informasi-informasi yang telah berhasil dihimpun dengan kriteria tertentu, untuk kemudian diambil keputusan atau dirumuskan kebijaksanaan tertentu. Kriteria atau tolak ukur yang di pegangi tidak lain adalah tujuan yang sudah ditentukan terlebih dahulu sebelum kegiatan pendidikan itu dilaksanakan.
BAGAN TENTANG EVALUASI PENDIDIKAN
B. HUBUNGAN ANTARA PENILAIAN (EVALUATION) DENGAN PENGUKURAN (MEASUREMENT)
Pengukuran dalam bahasa Inggris disebut dengan measurement dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran tertentu.
Evaluasi memiliki makna yang berbeda dengan pengukuran. Pengukuran pada umumnya berkenaan dengan masalah kuantitatif untuk mendapatkan informasi yang diukur. Oleh sebab itu, dalam proses penngukuran diperlukan alat bantu tertentu. denagn demikian, antara evaluasi dan pengukuran tidak bisa disamakan walaupun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Evaluasi akan lebih tepat manakala didahului oleh proses pengukuran, sebaliknya hasil pengukuran tidak akan memiliki arti apa-apa manakala tidak dikaitkan dengan proses evaluasi. Jadi, pengukuran itu hanya bagian dari evaluasi dan tes bagian dari pengukuran. Ini berarti sebelum dilakukan evaluasi, didahului oleh pengukuran. Dan pengukuran adalah hasil dari suatu tes.
Dari penjelasan di atas, maka pengukuran adalah proses pengumpulan data yang diperlukan dalam rangka memberikan judgement yakni berupa keputusan terhadap sesuatu.
Pengukuran yang bersifat kuantitatif itu dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu
1. Pengukuran yang dlakukan bukan untuk menguji sesuatu. Misalnya pengukuran yang dilakukan penjahit pakaian.
2. Pengukuran yang dilakukan untuk menguji sesuatu. Misalnya pengukuran untuk menguji daya tahan perbaja terhadap tekanan berat.
3. Pengukuran untuk menilai, yang dilakukan dengan jalan menguji sesuatu. Misalnya pengukuran kemajuan belajar peserta didik dalam rangka mengisi nilai rapor yang dilakukan dengan menguji mereka dalam bentuk tes hasil belajar.
Pengukuran jenis ketiga inilah yang digunakan dalam dunia pendidikan.
Penilaian berarti menilai sesuatu. Sedangkan menilai adalah mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mendasarkan diri atau berpegang pada ukuran baik dan buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh dan sebagainya. Jadi penilaian itu sifatnya adalah kualitatif.
Sedangkan evaluasi adalah mencakup dua kegiatan tadi, yaitu pengukuran dan penilaian. Evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk menilai sesuatu. Untuk dapat menentukan nilai dari sesuatu yang sedang dinilai itu dilakukanlah pengukuran, dan wujud dari pengukuran itu adalah pengujian, dan pengujian inilah yang dalam dunia kependidikan dikenal dengan istilah tes.
Lebih lanjut dikatakan bahwa istilah penilaian mempunyai arti yang lebih luas di bandingkan dengan istilah pengukuran. Sebab pengukuran itu sebenarnya hanyalah merupakan suatu langkah atau tindakan yang kiranya perlu diambil dalam rangka pelaksanaan evaluasi. Dikatakan “perlu diambil” karena tidak semua penilaian itu harus senantiasa di dahului oleh tindakan pengukuran secara lebih nyata.
Namun demikian tidak dapat disangkal adanya kenyataan bahwa evaluasi dalam bidang pendidikan-(khususnya evaluasi terhadap prestasi belajar peserta didik)- sebagian besar bersumber dari hasil-hasil pengukuran. Evaluasi mengenai proses pembelajaran disekolah tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik apabila evaluasi itu tidak didasarkan atas data yang bersifat kuantitatif. Inilah sebabnya mengapa dalam praktek masalah pengukuran mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses evaluasi. Baik buruknya evaluasi akan bergantung pada hasil- hasil pengukuran yang mendahuluinya. Hasil pengukuran yang kurang cermat akan memberikan hasil evaluasi yang kurang cermat pula ; sebaliknya teknik pengukuran yang tepat diharapkan dapat memberikan landasan yang kokoh untuk mengadakan evaluasi yang tepat.
Dalam rangka mempertegas perbedaan pengukuran dengan penilaian Wandt dan Brown mengatakan bahwa, pengukuran adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas atau kuantitas dari sesuatu; ia akan memberikan jawaban atas pertanyaan How much?. Adapun penilaian atau evaluasi adalah tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu, dan akan memberikan jawaban atas pertanyaan, What value?.
Perbedaan lainnya antara pengukuran dan penilaian adalah bahwa penilaian lebih banyak melibatkan unsur subyektifitas daripada pengukuran. Dalam hal ini Stanley dan Hopkins berpendapat bahwa: “penilaian selalu melibatkan lebih banyak unsur subyektifitas daripada pengukuran, tapi suatu pengukuran yang paling obyektif sekalipun tidak akan terlepas dari unsur subyektifitas.”
Dalam proses penilaian hasil belajar, pengukuran mempunyai peranan yang sangat penting. Yakni, untuk mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan tujuan penilaian yang bersangkutan.
C. FUNGSI EVALUASI PENDIDIKAN
Secara umum, evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidak-tidaknya memiliki tiga macam fungsi pokok yaitu
a. Mengukur kemajuan
b. Menunjang penyusunan rencana
c. Memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali
Seperti telah di kemukakan dalam pembicaraan terdahulu, evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk mengukur dan selanjutnya menilai, sampai dimanakah tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan. Apabila tujuan yang telah dirumuskan itu direncanakan untuk dicapai secara bertahap, maka dengan evaluasi yang berkesinambungan akan dapat di pantau, tahapan manakah yang sudah dapat di selesaikan, tahapan manakah yang berjalan dengan mulus, dan mana pula tahapan yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Walhasil dengan evaluasi terbuka kemungkinan bagi evaluator untuk mengukur seberapa jauh atau seberapa besar kemajuan atau perkembangan program yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah dirumuskan.
Setidak-tidaknya ada dua macam kemungkinan hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi; yaitu:
1) Hasil evaluasi itu ternyata menggembirakan, sehingga dapat memberikan rasa lega bagi evaluator, sebab tujuan yang telah ditentukan dapat di capai sesuai dengan yang direncanakan
2) Hasil evaluasi ternyata tidak menggembirakan atau bahkan mengkhawatirkan, dengan alasan bahwa adanya penyimpangan-penyimpangan, hambatan dan kendala, sehingga mengharuskan evaluator bersikap waspada. Ia perlu memikirkan dan dan melakukan pengkajian ulang terhadap rencana yang telah disusun atau mengubah dan memperbaiki cara pelaksanaannya. Berdasar data hasil evaluasi itu selanjutnya dicari metode-metode lain yang dipandang lebih tepat dan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sudah barang tentu perubahan-perubahan itu membawa dampak atau konsekuensi berupa perencanaan ulang (re-plening). Dengan demikian dapat di katakan bahwa evaluasi itu memiliki fungsi: menunjang penyusunan rencana.
Evaluasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan, akan membuka peluang bagi evaluator untuk membuat perkiraan, apakah tujuan yang telah dirumuskan akan dapat di capai pada waktu yang telah di tentukan,ataukah tidak. Apabila berdasar data hasil evaluasi itu diperkirakan bahwa tujuan tidak akan dapat di capai sesuai dengan rencana, maka evaluator akan berusaha untuk mencari dan menemukan factor-faktor penyebabnya, serta mencari dan menemukan jalan keluar atau cara-cara pemecahannya. Bukan tidak mungkin, bahwa atas dasar data hasil evaluasi itu evaluator perlu mengadakan perubahan-perubahan, penyempurnaan-penyempurnaan yang menyangkut organisasi, tata kerja, atau mungkin juga perbaikan terhadap tujuan organisasi itu sendiri. Jadi, kegiatan evaluasi pada dasarnya juga di maksudkan untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan usaha.
Adapun secara khusus, fungsi evaluasi dalam dunia pendidikan dapat ditillik dari tiga segi, yaitu:
a. Segi psokologis
b. Segi didaktik
c. Segi administratif.
Secara psikologis, kegiatan evaluasi dalam bidang pendidikan di sekolah dapat disoroti dari dua sisi. Yaitu dari sisi peserta didik dan dari sisi pendidik.
Bagi peserta didik, evaluasi pendidikan secara psikologis akan memberikan pedoman atau pegangan batin kepada mereka untuk mengena kapasitas dan status dirinya masing-masing ditengah-tengah kelompok atau kelasnya. Dengan dilakukannya evaluasi hasil belajar siswa misalnya, maka para siswa akan mengetahui apakah dirinya termsuk siswa yang berkemampuan tinggi, berkemampuan rata-rata, ataukah berpengetahuan rendah.
Bagi pendidik, evaluasi pendidikan akan memberikan kepastian atau ketetapan hati kepada diri peserta tersebut. Sedah sejauh manakah kiranya usaha yang telah dilakukannya selama ini telah membawa hasil, sehingga ia secara psikologis memiliki pedoman atau pegangan batin yang pasti guna menentukan langkah-langkah apa saja yang di pandang perlu dilakukan selanjutnya. Misalnya dengan menggunakan metode-metode mengajar tertentu, hasil-hasil belajar siswa telah menunjukkan adanya peningkatan daya serap terhadap materi yang telah diberikan kepada para siswa tersebut; karena itu atas dasar hasil evaluasi tersbut penggunaan metode mengajar tadi akan terus dipertahankan. Begitupun sebaliknya.
Bagi peserta didik, secara didaktik evaluasi pendidikan akan dapat memberikan dorongan (motivasi) kepada mereka untuk dapat memperbaiki, meningkatkan dan mempertahankan prestasinya.
Bagi pendidik, secara didaktik evaluasi pendidikan itu setidak-tidaknya memiliki lima macam fungsi, yaitu:
1. Memberikan landasan untuk menilai hasil usaha (prestasi) yang telah di capai oleh peserta didiknya
2. Memberikan informasi yang sangat berguna, guna mengetahui posisi masing-masing peserta didik di tengah-tengah kelompoknya.
3. Memberikan bahan yang penting untuk memilih dan kemudian menetapkan status peserta didik.
4. Memberikan pedoman untuk mencari dan menemukan jalan keluar bagi peserta didik yang memang memerlukannya.
5. Memberikan petunjuk tentang sudah sejauh manakah program pengajaran yang telah di tentukan telah dapat dicapai.
Adapun secara administrative, evaluasi pendidikan setidak-tidaknya memiliki tiga macam fungsi, yaitu:
1. Memberikan laporan
2. Memberikan bahan-bahan keterangan (data)
3. Memberikan gambaran
Menurut Wina Sanjaya dalam bukunya Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran ada bberapa fungsi evaluais, yakni :
a. Evaluasi merupakan alat yang penting sebagai umpan balik bagi siswa.
b. Evaluasi merupakan alat untuk mengetahui bagaimana ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan.
c. Evaluasi dapat memberikan informasi untuk mengembangkan program kurikulum.
d. Informasi dari hasil evaluasi dapat digunkan oleh siswa untuk mengambil keputusan secara individual khususnya dalam menentukan masa depan sehubungan dengan pemilihan bidang pekerjaan.
e. Evaluasi berguna untuk para pengembang kurikulum dalam menentukan kejelasan tujuan khusus yang ingin dicapai.
f. Evaluasi berfungsi sebagai umpan balik untuk semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan di sekolah.
D. TUJUAN EVALUASI PENDIDIKAN
1. Tujuan umum
Secara umum, tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan ada dua, yaitu :
a. Untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang di alami oleh para peserta didik, setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. dengan kata lain tujuan umum dari evaluasi dalam pendidika adalah untuk memperoleh data pembuktian, yang akan menjadi petunjuk sampai di mana tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian tujuan-tujuan kurikuler, setelah mereka menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
b. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pembelajaran yang telah di pergunakan dalam prses pembelajaran.tujuan kedua dari evaluasi pendidikan adalah untuk mengukur dan menilai sampai dimanakah efektivitas mengajar dan metode-metode mengajar yang telah diterapkan atau dilaksanakan oleh pendidik, serta kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh peserta didik.
2. Tujuan khusus
Tujuan khusus dari kegiatan evaluasi dalam bidang pendidikan adalah :
a. Untu merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Tanpa adanya evaluasi maka tidak mungkin timbul kegairahan atau rangsangan pada diri peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing.
b. Untuk mencari dan menemukan factor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya.
E. KEGUNAAN EVALUASI PENDIDIKAN
Di antara kegunaan yang dapat dipetik dari kegiatan evaluasi dalam bidang pendidikan adalah :
1. Terbukanya kemungkinan bagi evaluator guna memperoleh informasi tentang hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pelaksanaan program pendidikan.
2. Terbukanya kemungkinan untuk dapat diketahuinya relevansi antara program pendidikan yang telah dirumuskan dengan ujuan yang hendak dicapai.
3. Terbukanya kemungkinan unuk dapat dilakukannya usaha perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan progam pendidikan yang dipandang lebih berdaya guna dan berhasil guna, sehingga tujuan yang dicita-citakan, akan dapat dicapai dengan hasil yang sebaik-baiknya.
F. KLASIFIKASI EVALUASI PENDIDIKAN
Klasifikasi atau penggolongan evaluasi dalam bidang pendidikan sangat beragam. Sangat beragamnya pengklasifikasian atas evaluasi pendidikan itu disebabkan karena sudut pandang yang saling berbeda dalam melakukan pengklasifikasian tersebut. Salah satu cara pengklasifikasian terhadap evaluasi pendidikan itu adalah dengan jalan membedakan evaluasi pendidikan tersebut atas tiga kategori, yaitu:
1. Klasifikasi evaluasi pendidikan yang didasarkan pada fungsi evaluasi dalam proses pendidikan.
Dilihat dari segi fungsi yang dimiliki maka evaluasi pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu:
a. Evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebuthuan psikologis
b. Evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan didaktik
c. Evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebuutuhan administrative.
2. Klasifikasi evaluasi pendidikan yang didasarkan pada pemanfaatan informasi yang bersumber dari kegiatan evaluasi itu sendiri.
Dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan pendidikan, evaluasi dalam bidang pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu:
a. Evaluasi pendidikan yang mendasarkan diri pada banyaknya orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan pendidikan.
Evaluasi jenis ini dapat dibedakan menjadi dua golongan:
1) Evaluasi pendidikan dalam rangka pengambilan keputusan pndidikan yang bersifat individual.
Yang dimaksud dengan keputusan pendidikan yang bersifat individual adalah keputusan-keputusan pendidikan yang dibuat oleh individu-individu yang secara langsung hanya menyangkut individu tertentu. contoh keputusan rektor untuk membebaskan seorang mahasiswa dari kewajiban membayar SPP karena mahasiswa tersebut setelah di evaluasi ternyata adalah mahasiswa terbaik.
2) Evaluasi pendidikan dalam rangka pengambilan keputusa pedidikan yang bersifat institusional. Maksudnya adalah keputusan pendidikan yang dibuat oleh lembaga pendidikan tertentu ditujukan untuk orang banyak.
b. Evaluasi pendidikan yang mendasarkan diri pada jenis atau macamnya keputusan pendidikan.
Berdasarkan klasifikasi ini, maka evaluasi pendidikan dibedakan menjadi empat golongan, yaitu :
1) Evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan yang bersifat didaktik. Contoh keputusan mengenai keharusan bagi murid kelas VI yang akan mengikuti UN unuk mengikuti les tambahan. Keputusan ini diambil setelah memperhatikan hasil evaluasi belajar yang rendah.
2) Evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan yang bersifat bimbingan dan penyuluhan. Contoh keputusan untuk menyelenggarakan ceramah keagamaan secara rutin seperti ceramah mengenai kenakalan remaja.
3) Evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan yang bersifat administrative. Contoh penentuan siswa yang dapat dinyatakan naik kelas atau tinggal kelas dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai hasil belajar yang tercantum dalam buku rapor.
4) Evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan penelitian ilmiah atau riset. Contoh sebuah perguruan tinggi mengdakan riset tentang evaluasi dalam rangka mengatahui kualitas tes seleksi penerimaan calon mahasiswa baru, terutama dari segi validitas dan reliabilitasnya. Hasil penelitian tersebut selanjutnya digunakan untuk memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan mutu tes seleksi itu.
3. Evaluasi pendidikan yang dilatar belakangi oleh pertanyaan dimana atau pada bagian manakah evaluasi itu dilaksanakan dalam rangka proses pendidikan.
Dari klasifikasi ini dapat dibedakan menjadi dua gologan:
a. Evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan ditengah-tengah atau pada saat berlangsungnya proses pembelajaran.
b. Evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan seelah seluruh unit pelajaran selesai diajarkan.
G. OBYEK EVALUASI PENDIDIKAN
Obyek atau sasaran evaluasi pendidikan ialah segala sesuatu yang betalian dengan kegiatan atau proses pendidikan, yang dijadikan titik pusat perhatian atau pengamatan, karena pihak penilai (evaluator) ingin memperoleh informasi tentang kegiatan atau proses pendidikan tersebut. Salah satu cara untuk mengenal atau mengetahui obyek dari evaluasi pendidikan adalah dengan jalan menyorotinya dari tiga segi, yaitu dari segi input, transformasi dan out put. Ditilik dari segi input ini maka obyek dari evaluasi pendidikan meliputi tiga aspek, yaitu:
1. Aspek kemampuan
Untuk dapat diterima sebagai calon peserta didik dalam rangka mengikuti program pendidikan tertentu, maka para calon peserta didik harus memiliki kemampuan yang sesuai atau memadai, sehingga dalam mengikuti proses pembelajaran pada program pendidikan tertentu itu nantiya peserta didik tidak akan mengalami banyak hambatan atau kesulitan.
sehubungan dengan itu, maka bekal kemampuan yang dimiliki calon peserta didik perlu untuk dievaluasi terlebih dahulu, guna mengetahui sampai sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing calon peserta didik dalam mengikuti program tertentu. adapun alat yang biasa dipergunakan dalam rangka mwngevaluasi kemampuan peserta didik itu adalah tes kemampuan (aptitude test)
2. Aspek kepribadian
Kepribadian adalah sesuatu yang terdapat pada diri seseorang, dan menampakkan bentuknya dalam tingkah laku. Sebelum mengikuti program pendidikan tertentu, para calon peserta didik perlu terlebih dahulu dievaluasi kepribadiannya masing-masing, sebab baik buruknya kepribadian mereka secara psikologis akan dapat memperngaruhi keberhasilan mereka dalam mengikuti program pendidikan tertentu. evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui atau mengungkapkan kepribadian seseorang adalah dengan jalan menggunakan tes kepribadian (personality test).
3. Aspek sikap
Sikap pada dasarnya adalah merupakan bagian dari tingkah laku manusia, sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang memancar keluar. Karena sikap ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam pergaulan, maka memperoleh informasi mengenai sikap sseorng adalah hal yang sangat penting. Karena itu maka aspek sikap perlu dinilai atau di evaluasi terlebih dahulu bagi calon peserta didik sebelum mengikuti program pendidikan tertentu.
Selanjutnya apabila disoroti dari segi transformasi maka obyek dari evaluasi pendidikan itu meliputi :
a. Kurikulum atau materi pelajaran
b. Metode mengajar dan teknik penilaian
c. Sarana atau media pendidikan.
d. System administrasi
e. Guru dan unsur-unsur personal lainnya.
Adapun dari segi output, yang menjadi sasaran evaluasi pendidikan adalah tingkat pencapaian atau prestasi belajar yang berhasil diraih oleh masing-masing peeserta didk, setelah mereka terlibat dalam proses pendidikan selama jangka waktu yang telah ditentukan.
H. SUBYEK EVALUASI PENDIDIKAN
Subyek atau pelaku evaluasi pendidikan ialah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi dalam bidang pendidikan.
Berbicara tentang subyek evaluasi pendidikan di sekolah kiranya perlu dikemukakan disini bahwa mengenai siapa yang disebut sebagai subyek evaluasi pendidikan itu akan sangat bergantung pada, atau ditentukan oleh suatu aturan yang menetapkan pembagian tugas untuk melakukan evaluasi tersebut. Jadi subyek evaluasi pendidikan itu dapat berbeda-beda orangnya.
Dalam kegiatan valuasi pendidikan dimana sasaran evalusinya adalah prestasi belajar siswa, maka subyek evaluasinya adalah guru atau dosen yang mengasuh mata pelajaran tertentu. jika evaluasi yang dilakukan itu sasarannya adalah sikap peserta didik, maka subyek evaluasinya adalah guru atau petugas yang sebelum melaksanakan evaluasi tentang sikap itu, terlebih dahulu telah memperoleh pendidikan atau latihan (training) mengenai cara-cara menilai sikap seseorang. Adapun apabila sasaran yang di evaluasi adalah kepribadian peserta didik, dimana pengukuran tentang kepribadian itu dilakukan dengan menggunakan instrument berupa test yang sifatnya baku. Maka subyek evaluasinya tidak bisa lain kecuali seorang psikolog.
I. RUANG LINGKUP EVALUASI PENDIDIKAN
Secara umum ruang lingkup dari evaluasi dalam bidang pendidikan di sekolah mencakup tiga komponen utama yaitu :
1. Evaluasi program pengajaran
Evaluasi atau penilaian terhadap program pengajaran akan mencakup tiga hal, yaitu:
a. Evaluasi terhadap tujuan pengajaran
b. Evaluasi terhdap isi program pngajaran
c. Evaluasi terhadap strategi belajar mengajar.
2. Evaluasi proses pelaksanaan pengajaran
Evaluasi mengenai proses peaksanaan pengajaran akan mencakup :
a. Kesesuaian antara proses belajar mengajar yang berlangsung, dengan garis-garis besar program pengajaran yang telah ditentukan.
b. Kesiapan guru dalam melaksanakan program pengajaran.
c. Kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.
d. Minat atau perhatian siswa didalam mengikuti pelajaran.
e. Keaktifan atau partisipasi siswa selama proses pembelajaran berlangsung.
f. Peranan bimbingan dan penyuluhan terhadap siswa yang memerlukannya.
g. Komunikasi dua arah antara guru dan murid selama proses pembelajaran berlangsung.
h. Pemberian dorongan atau motivasi terhadap siswa.
i. Pemberian tugas-tugas kepada siswa dalam rangka penerapan teori-teori yang diperoleh didalam kelas dan upaya menghilangkan dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah.
3. Evaluasi hasil belajar
Evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik ini mencakup:
a. Evaluasi mengenai tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai dalam unit-unit program pengajaran yang bersifat terbatas.
b. Evaluasi mengenai tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan-tujuan umum pengajaran.
DAFTAR PUSTAKA
Sudijono, Anas. 1996. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.
Sanjaya, Wina. 2008. Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: Prenada media Group.
Mudjijo. 1995. Tes Hasil Belajar. Jakarta: Bumi Aksara.
PENDAHULUAN
Filsafat dan ilmu adalah dua kata yang saling terkait, baik secara substansial maupun historis, karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan Filsafat, sebaliknya perkembangan ilmu memperkuat keberadaan Filsafat. Filsafat telah berhasil merubah pola pemikiran bangsa Yunani dan umat manusia dari pandangan mitosentris menjadi logosentris. Dengan Filsafat, pola fikir yang selalu tergantung pada dewa diubah menjadi pola pikir yang tergantung pada rasio.
Pada pekembangan selanjutnya ilmu terbagi dalam beberapa disiplin, yang membutuhkan pendekatan, sifat, obyek, tujuan dan ukuran yang berbeda antara disiplin ilmu yang satu dengan yang lainnya. Pada gilirannya, cabang ilmu semakin subur dengan segala viariasinya. Namun tidak dapat juga dipungkiri bahwa ilmu yang semakin terspesialisasi itu semakin menambah sekat-sekat antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lain, sehingga muncul arogansi ilmu yang satu terhadap ilmu yang lain. Tidak hanya sekedar sekat-sekat antar displin dan arogansi ilmu, tetapi yang terjadi adalah terpisahnya ilmu itu dengan nilai luhur ilmu, yaitu untuk menyejahterakan umat manusia. Bahkan tidak mustahil terjadi, ilmu menjadi bencana bagi kehidupan manusia, seperti pemanasan global dan dehumanisasi.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu sisi ilmu berkembang dengan pesat, disisi lain, timbul kekhawatiran yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu itu karena tidak ada seorangpun atau lembaga yang meiliki otoritas untuk menghambat implikasi negatif dari ilmu.
Ilmu dan tekhnologi dalam konteks itu kehilanga ruhnya yang fundamental karna ilmu kemudian mengeliminir peran manusia dan bahkan manusia tanpa sadar menjadi budak ilmu dan teknologi. Karena itu, Filsafat ilmu berusaha mengembalikan ruh dan tujuan luhur ilmu agar ilmu tidak menjadi boomerang bagi kehidupan umat manusia.
Adapun bagaimana perkembangan Filsafat ilmu dari segi historisnya, akan di bahas pada Bab selanjutnya.
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN FILSAFAT ILMU
A. Perkembangan Awal Pemikiran Filsafat Ilmu
Periode Filsafat Yunani merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia karena pada waktu ini terjadi perubahan pola fikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola fikir mitosentris adalah pola fikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Perubahan pola fikir itu terlihat sederhana tetapi implikasinya tidak sesederhana yang dibayangkan kerena selama ini alam ditakuti dan dijauhi kemudian di dekati bahkan dieksploitasi. Manusia yang dulunya pasif dalam menghadapi fenomena alam menjadi lebih proaktif dan kreatif sehingga alam dijadikan obyek penelitian dan pengkajian. Dari proses inilah kemudian ilmu berkembang dari rahim Filsafat, yang akhirnya kita nikmati dalam bentuk teknologi. Karena itu periode perkembangan Filsafat Yunani merupakan entri poin untuk memasuki peradaban baru umat manusia.
Terjadinya perubahan yang besar dalam lapangan pengetahuan empiris yang berdasarkan sikap receptive attitude mind. Bangsa Yunani tak dapat menerima empirirs tersebut secara pasif-reseptif karena bangsa Yunani memiliki sikap jiwa: “an inguiring attitude, an inguiring mind”. Dengan demikian lahirlah pengetahuan filsafat yang pada zaman itu mempunyai arti yang lebih luas dari pada sekarang, yaitu meliputi semua bidang ilmu sebagai induk ilmu pengetahuan (mater scientarum).
Seperti yang kita ketahui bahwa secara bahasa Filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan/ kebenaran/ pengetahuan. Mencintai pengetahuan adalah awal proses manusia mau menggunakan daya fikirnya, sehingga dia mampu membedakan mana yang riil dan mana yang ilusi. Orang Yunani awalnya sangat percaya pada dongeng dan takhayul, tetapi lama kelamaan, terutama setelah mereka mampu membedakan yang riil dan yang ilusi, mereka mampu keluar dari kungkungan mitologi dan mendapatkan dasar pengetahuan ilmiah. Inilah titik awal manusia menggunakan rasio untuk meneliti dan sekaligus mempertanyakan dirinya dan alam jagat raya.
Karena manusia selalu berhadapan dengan alam yang begitu luas dan penuh misteri, timbul rasa ingin mengetahui rahasia alam itu. Lalu timbul pertanyaan dalam pikirannya; dari mana datangnya alam ini, bagaimana kejadiannya, begaimana kemajuannya dan kemana tujuannya? Pertanyaan semacam inilah yang selalu menjadi pertanyaan dikalangan filosof Yunani, sehingga tidak heran kemudian mereka disebut dengan filosof alam karena perhatiannya yang begitu besar kepada alam. Filosof alam ini juga disebut filosof pra Socrates, sedangkan Socrates dan setelahnya disebut dengan filosof pasca Socrates yang tidak haya mengkaji tentang alam, tetapi manusia dan perilakunya.
Dalam buku Filsafat Umum-nya Ahmad Tafsir yang dikutip oleh Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A dalam bukunya Filsafat Ilmu, dikatakan bahwa filosof alam pertama yang mengkaji tentang asal usul alam adalah Thales (624-546SM). Pertanyaannya adalah “apa sebenarnya asal usul dari alam semessta ini?” pertanyaan ini sangat mendasar, terlepas apapun itu jawabannnya. Namun yang penting adalah pertanyaan itu dijawab dengan pendekatan rasional bukan dengan pendekatan mitos atau kepercayaan. Ia mengatakan asal alam adalah air karena air unsur yang sangat penting dalam kehidupan. Dan air dapat berubah menjadi gas, seperti uap dan benda padat seperti es, dan bumi juga berasal dari air.
Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A mengutip dari buku Sejarah Filsafat Yunani karangan K. Bertens dikatakan bahwa setelah Thales, muncul Anaximandros (610-540SM). Anaximandros mencoba menjelaskan bahwa substansi pertama itu bersifat kekal, tidak terbatas, dan meliputi segalanya. Dia tidak setuju unsur utama alam adalah salah satu dari unsur-unsur yang ada, seperti air atau tanah. Unsur utama alam harus yang mencakup segalanya di atas segalanya, yang dinamakan apeiron. Jika ia adalah air, maka air harus meliputi segalanya termasuk api yang merupakan lawannya. Padahal tidak mungkin air menyingkirkan unsur api. Karena itu Anaximandros tidak puas dengan mnunjukkan salah satu unsur sebagai prinsip alam, tetapi ia mencari yang lebih dalam yaitu zat yang tidak dapat diamati oleh panca indra.¬¬¬¬
Berbeda dengan Thales dan Anaximandros, Heraklitos (540-480SM) melihat alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah; sesuatu yang dingin berubah menjadi panas, yang panas berubah menjadi dingin. Itu berarti bahwa apa apabila kita hendak memahami kosmos, kita harus menyadari bahwa kosmos itu dinamis. Segala sesuatu yang saling bertentangan dan dalam pertentangan itulah kebenaran. Karena itu dia berkesimpulan, tidak ada satu pun yang benar-benar ada, semuanya menjadi. Ungkapan yang terkenal dari Heraklitos dalam menggambarkan perubahan ini adalah panta uden menei (semuanya mengalir dan tidak ada satupun yang tinnggal mantap).
Itulah sebabnya ia mempunyai kesimpulan bahwa yang mendasar dalam alam semesta ini adalah bukan bahannya, melainkan aktor dan penyebabnya, yaitu api. Api adalah unsur yang paling asasi dalam alam karena api dapat mengeraskan adonan roti dan dari sisi lain dapat melunakkan es. Artinya, api adalah aktor pengubah pada alam ini, sehingga api pantas dianggap sebagai symbol perubahan itu sendiri.
Filosof alam yang cukup berpengaruh adalah Parmanides (515-440SM) yang lebih muda umurnya dibandingkan Heraklitos. Pandangannya bertolak belakang dengan Heraklitos. Menurut Heraklitos, realitas seluruhnya bukanlah sesuatu yang lain dari pada gerak dan perubahan, sedangkan menurut parmanides, gerak dan perubahan tidak mungkin terjadi. Menurutnya realitas merupakan keseluruhan yang bersatu, tidak bergerak dan tidak berubah. Dia menegaskan bahwa yang ada itu ada. Inilah kebenaran. Coba bayangkan apa konsekuensi bila ada orang yang memungkiri kebenaran itu. Ada dua pengandaian, yang pertama adalah orang bisa mengemukakan bahwa yang ada itu tidak ada. Kedua, atau orang dapat mengemukakan bahwa yang ada itu serentak ada dan serentak tidak ada. Pengandaian pertama tertolak dengan sendirinya karena yang tidak ada memang tidak ada. Yang tidak ada tidak dapat dipikirkan dan menjadi obyek pembicaraan. Pengandaian yang kedua tidak dapat diterima karena antara ada dan tidak ada tidak terdapat jalan tengah, yang ada akan tetap ada dan yang tidak ada tidak mungkin menjadi ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang ada itu ada dan itulah satu-satunya kebenaran.
Phytagoras (580-500SM) mengembalikan segala sesuatu pada bilangan. Baginya tidak ada satu pun yang di alam ini terlepas dari bilangan. Semua realitas dapat diukur dengan bilangan (kuantitas). Karena itu ia berpendapat bahawa bilangan adalah unsur utama dari alam dan sekaligusa menjadi ukuran. Kesimpulan ini ditarik dari kenyataan bahwa realitas alam adalah harmoni antara bilangan dan gabungan antara dua hal yang berlawanan. Kalau segala-galanya adalah bilangan, itu berarti bahwa unsur bilangan merupakan juga unsur yang terdapat dalam segala sesuatu. Unsur-unsur bilangan itu adalah genap dan ganjil, terbatas dan tidak terbatas. Demikian juga seluruh jagad raya merupakan suatu harmoni yang mendamaikan hal-hal yang berlawanan. Artinya, segala sesuatu berdasarkan dan dapat dikembalikan pada bilangan.
Jasa Phytagoras ini sangat besar dalam perkembbangan ilmu, terutama ilmu pasti dan ilmu alam. Ilmu yang dikembangkan kemudian hari sampai hari ini sangat tergantung pada pendekatan matematika. Galileo menegaskan bahwa alam ditulis dalam bahasa matematika. Dalam Filsafat ilmu, matematika merupakan sarana ilmiah yang terpenting dan akurat karena dengan pendekatan matematikalah ilmu dapat diukur dengan benar dan akurat. Disamping itu, matematika dapat menyederhanakan uraian yang panjang dalam bentuk symbol sehingga lebih cepat dipahami.
Setelah berakhirnya masa filosof alam, maka muncul masa transisi, yakni penelitian terhadap alam tidak menjadi fokus utama tetapi sudah mulai menjurus pada memberikan jawaban yang memuaskan sehingga timbullah kaum sofis. Kaum sofis ini memluai kajian tentang manusia dan menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Tokoh uatamanya adalah Protagoras (481-411 SM). Ia menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Pernyataan ini merupakan cikal bakal humanisme. Pertanyaan yang muncul adalah apakah yang dimaksudnya itu manusia individu atau manusia secara umumnya. Memang dua hal itu menimbulkan konsekuensi yang sungguh berbeda. Namun tidak ada jawaban yang pasti, mana yang dimaksud oleh Protagoras. Yang jelas ia menyatakan bahwa kebenaran itu bersifat subyektif dan relative. Akibatnya tidak akan ada ukuran yang absolut dalam etika, metafisika, maupun agama, bahkan teori matematika tidak dianggapnya mempunyai kebenaran yang absolut.
Tokoh lain dari kaum sofis adalah Gorgias. Ia datang ke Athena pada tahun 427 SM dari Leontini. Menurutnya ada tiga proposisi: pertama, tidak ada yang ada, maksudnya relitas itu sebenarnya tidak ada. Pemikiran lebih baik tidak menyatakan apa-apa tentang realitas. Kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak akan dapat diketahui. Ini disebabkan oleh pengindraan itu tidak dapat dipercaya, pengindraan itu sumber ilusi. Akal tidak juga mampu meyakinkan kita bahwa semesta alam ini ada karena akal kita telah diperdaya oleh dilema subyektivitas. Dan ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain.
Pengruh positif kaum sofis cukup terasa karena mereka membangkitkan semangat berfilsafat. Mereka mengingatkan filosof bahwa persoalan pokok dalam Filsafat bukanlah alam melainkan manusia. Mereka juga membangkitkan jiwa humanism. Mereka tidak memberikan jawaban final tentang etika, agama dan metafisika. Ini membuka peluang bagi para filosof untuk lebih kreatif lagi dalam berfikir. Ilmu juga mendapat ruang yang sangat kondusif dalam pemikiran kaum sofis karena mereka memberi ruang untuk berspekulasi dan sekaligus merelatifkan teori ilmu, sehingga muncul sintesa baru. Dalam Filsafat ilmu, pandangan relative tentang kebenaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses mencari ilmu. Karena itu, ilmu itu terbatas, tetapi proses mencari ilmu tidak terbatas.
Namun para filosof setelah kaum sofis tidak setuju dengan pandangan tersebut, seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka menolak relativiasme kaum sofis. Menurut mereka, ada kebenaran obyektif yang bergantung pada manusia. Socrates membuktikan adanya kebenaran obyektif itu dengan menggunakan metode yang bersifat praktis dan dijalankan melalui percakapan-percakapan sehingga metode yang digunakannya biasanya disebut metode dialog karena dialog memiliki peranan penting dalam menggali kebenaran yang obyektif.
Socrates berpendapat bahwa kehidupan dan ajaran adalah hal yang satu dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu dasar dari segala penelitian dan pembahasan adalah pengujian diri sendiri. Bagi Socrates pengetahuan yang sangat berharga adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Semboyan yang paling digemarinya adalah apa yang tertera pada Kuil Delphi, yaitu: “kenalilah dirimu sendiri”.
Periode setelah Socrates disebut dengan zaman keemasan Filsafat Yunani karena pada zaman ini kajian-kajian yang muncul adalah perpaduan antara Filsafat alam dan Filsafat tentang manusia. Tokoh yang sangat menonjol adalah Plato yang sekaligus murid dari Socrates dan yang menulis ide-ide dari Socrates. Menurutnya, esensi itu mempunyai realitas dan realitasnya ada dalam alam idea. Kebenaran umum itu ada bukan dibuat-buat bahkan sudah ada di alam idea. Plato menggambarkan kebenaran umum adalah rujukan bagi alam empiris.
Plato berhasil mensintesakan pemikiran Heraklitos dan Parmanides. Menurut Heraklitos, segala sesuatu berubah, sedangkan menurut Parmanides, segala sesuatu diam. Untuk mendamaikan pandangan ini Plato berpendapat bahwa pandangan Heraklitos benar, tetapi hanya berlaku bagi alam empiris saja, dan pandangan Parmanides juga benar, tetapi hanya berlaku bagi idea-idea bersifat abadi dan idea inilah yang menjadi dasar bagi pengenalan yang sejati.
Puncak kejayaan Filsafat Yunani terjadi pada masa Aristoteles. Ia murid Plato, seorang filosof yang berhasil menemukan pemecahan persoalan-persoalan besar Filsafat yang dipersatukannya dalam suatu system; logika, matematika, fisika, dan metafisika. Logika Aristoteles berdasarkan pada analisis bahasa yang disebut silogisme. Pada dasarnya silogisme terdiri dari tiga premis: premis mayor, premis minor dan konklusi. Logika Aristoteles ini juga disebut dengan logika deduktif, yang mengukur valid atau tidaknya sebuah pemikiran.
Aristoteles yang pertamakali membagi Filsafat pada hal yang teoritis dan praktis. Yang teoritis mencakup logika, metafisika, fisika, sedangkan yang praktis mencakup etika, ekonomi dan politik. Pembagian ilmu inilah yang menjadi pedoman juga bagi klasifikasi ilmu dikemudian hari. Aristoteles dianggap bapak ilmu karena dia mampu meletakkan dasar-dasar metode ilmiah secara sistematis.
Filsafat Yunani yang rasional itu boleh dikatakan berakhir setelah Aristoteles menuangkan pemikirannya. Akan tetapi sifat rasional itu masih digunakan selama berabad-abad sesudahnya sampai sebelum Filsafat benar-benar memasuki dan tenggelam dalam abad pertengahan. Namun jelas, setelah periode ketiga filosof besar itu mutu filsfat semakin merosot, kemunduran Filsafat itu sejalan dengan kemunduran politik ketika itu, yaitu sejalan dengan terpecahnya kerajaan Macedonia menjadi pecahan-pecahan kecil setelah wafatnya Alexander The Great. Tepatnya pada ujung zaman helenisme, yaitu pada ujung sebelum masehi menjelang neo Platonisme, Filsafat benar-benar mengalami kemunduran.
B. Perkembangan Pemikiran Abad Pertengahan Filsafat Ilmu
Perkembangan pemikiran abad pertengahan Filsafat ilmu itu dapat juga disebut dengan perkembangan Filsafat ilmu di zaman Islam. Sebelum di uaraikan sejarah dan perkembangan ilmu dalam Islam, ada baiknya diuraikan sedikit tentang pandangan Islam terhadap ilmu. Hal ini penting untuk diketahui karena menjadi landasan bagi pengembangan ilmu di sepanjang sejarah kehidupan umat Islam.
Sejak awal kelahirannya, Islam sudah memberikan penghargaan yang begitu besar kepada ilmu. Sebagaimana sudah diketahui, bahwa Muhhammad saw ketika diutus oleh Allah sebagai Rasul, hidup dalam masyarakat yang terbelakang dimana paganism tumbuh menjadi sebuah identitas yang melekat pada masyarakat Arab pada masa itu. Kemudian Islam datang menawarkan cahaya penerang yang mengubah masyarakat Arab jahiliyyah menjadi masyarakat yang berilmu dan beradab.
Kalau dilacak akar sejarahnya, pandangan Islam tentang pentingnya ilmu tumbuh bersamaan dengan munculnya Islam itu sendiri. Ketika rasulullah menerima wahyu yang pertama yang mula-mula diperintahkan kepadanya adalah “membaca”. Dengan demikian, al-Qur'an dan hadis menjadi sumber ilmu yang dikembangkan oleh umat Islam dalam spectrum yang seluas-luasnya. Selanjutnya kita akan masuk kedalam inti pembahasan, yaitu tentang sejarah dan perkembangan ilmu dalam Islam. Untuk memudahkan pemahaman kita penulis mencoba membagi sejarah perkembangan ilmu dalam Islam dalam beberapa zaman, seperti uraian berikut:
1. Penyampaian Ilmu Dalam Filsafat Yunani Ke Dunia Islam
Pengalihan pengetahuan ilmiah dan Filsafat Yunani ke dunia Islam, dan penyerapan serta pengintegrasian pengetahuan itu oleh umat Islam, merupakan sebuah catatan sejarah yang unik. Dalam sejarah peradaban manusia, amat jarang ditemukan suatu kebudayaan asing dapat diterima sedemikian rupa oleh kebuadaan lain, yang kemudian menjadikannya landasan bagi perkembangan intelektual dan pemahaman filosofisnya.
Dalam perjalanan ilmu dan juga Filsafat di dunia Islam, pada dasarnya terdapat rekonsiliasi dalam arti mendekatkan dan mempertemukan dua pandangan yang berbeda, bahkan sering kali ekstrim antara pandangan Filsafat Yunani, seperti Filsafat Plato dan Aristoteles, dengan pandangan keagamaan dalam Islam yang sering kali menimbulkan benturan-benturan. Sebagai contoh konkret dapat disebutkan bahwa Plato dan Aristoteles telah memberikan pengaruh yang besar pada mazhab-mazhab Islam, khususnya mazhab eklektisisme. Al- FArabi dalam hal ini memiliki sikap yang jelas krena ia percaya pada kesatuan Filsafat dan bahwa tokoh-tokoh Filsafat harus bersepakat diantara mereka sepanjang yang menjadi tujuan mereka adalah kebenaran. Bahkan bisa dikatakan bahwa para filosof muslim mulai dari al-Kindi sampai Ibnu Rusyd terlibat dalam upaya rekonsiliasi tersebut, dengan cara mengemukakan pandangan-pandangan yang relative baru dan menarik. Usaha-usaha mereka pada gilirannya menjadi alat dalam penyebaran Filsafat dan penetrasinya ke dalam studi-studi keislaman lainnya, dan tak diragukan lagi, upaya-upaya rekonsiliasi oleh para filosof muslim ini menghasilkan afinitas dan ikatan yang kuat antara Filsafat Arab dan Filsafat Yunani.
Selanjutnya, ketika berbicara tentang proses penyampaian ilmu dan Filsafat Yunani ke dunia Islam, kita harus melihat sisi lain yang juga menunjang keberhasilan Islam dalam menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sisi lain itu adalah aktivitas penerjemahan. Menurut C. A. Qadir yang dikutip oleh Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A. dalam bukunya Filsafat Ilmu, proses penerjemehan dan penafsiran buku-buku Yunani di negri-negri Arab di mulai jauh sebelum lahirnya agama Islam atau penaklukkan Timur Dekat oleh bagsa Arab pada tahun 614M. Jauh sebelum umat Islam dapat menaklukkan daerah-daerah di Tmur Dekat, pada saat itu Suriah merupakan tempat bertemunya dua kekuasaan dunia, Romawi dan Persia. Atas dasar itu bangsa Suriah disebut-sebut memainkan peranan yang sangat penting dalam penyebaran budaya Yunani ke Timur dan Barat. Dikalangan umat Kristen di Suriah, terutama kaum Nestorian, ilmu pengetahuan Yunani dipelajari dan disebarluaskan melalui sekolah-sekolah mereka. Walaupun tujuan uatama mereka adalah menyebarluaskan pengetahuan injil, namun pengetahuan ilmiah seperti ilmu kedokteran banyak diminati oleh pelajar.
Selain itu pada masa ini juga didapati pusat-pusat ilmu pengetahuan seperti Ariokh, Ephesus, dan Iskandariyah di aman buku-buku Yunani Purba masih dibaca dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa.
2. Perkembangan ilmu pada masa Islam klasik
Sebagaimana telah disinggung diatas bahwa pentingnya ilmu pengetahuan sangat ditekankan oleh Islam sejak awal, mulai masa Nabi sampai dengan Khulafaurrasyidin, pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan berjalan dengan pesat seiring dengan tantangan zaman.
Selanjutnya, seperti yang dikutip oleh Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A., dari buku Kaki Langit Peradaban Islam karya Nurcholis Madjid, dikatakan bahwa satu hal yang patut dicatat dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan adalah peristiwa Fitnah Kubra, yang ternyata tidak hanya membawa konsekuensi, tetapi ternyata juga membawa perubahan besar bagi pertumbuhan dan perkembangan ilmu di dunia Islam. Pasca terjadinya Fitnatul Kubra muncul berbagai golongan yang berkembang kaarena alasan-alasan politis. Namun di luar konlik yang muncul saat itu, sejarah mencatat dua tokoh besar yang tidak ikut terlibat dalam perdebatan teologis yang cenderung mengkafirkan satu sama lain, tetapi justru mencurahkan perhatiannya pada bidang ilmu agama. Kedua tokoh itu adalah Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Yang pertama mencurahkan perhatianya pada ilmu hadis, sementara yang disebut belakangan lebih berkonsentrasi pada ilmu tafsir. Kedua tokoh tersebut sering dianggap sebagai pelopor tumbuhnya institusi keulamaan dalam Islam. Sekaligus berarti pelopor kajian mendalam dan sistematis dalam bidang ilmu agama Islam.
Tahap penting berikutnya dalam proses perkembangan dari tradisi keilmuan Islam adalah masuknya unsur-unsur dari luar ke dalam Islam, khusunya unsur-unsur budaya Perso-Semitik dan budaya Hellenisme. Yang disebut belakangan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pemikiran Islam ibarat pisau bermata dua. Satu sisi ia mendukung Jabariyah (antara lain oleh Jahm bin Safwan), sedang disisi lain ia mendukung Qadariyah (antara lain Washil bin Atha’, tokoh dan pendiri mu’tazilah). Dari adanya pandangan yang dikotomis antara keduanya, kemudian muncul usaha menengahi dengan menggunakan argument-argumen Hellenisme, terutama Filsafat Aristoteles. Sikap menengahi itu terutama dilakukan oleh Abu Hasan Al- Asy’ari dan al Maturidi yang juga menggunakan unsur Hellenisme.
Berdasarakan uraian di atas dapat ditarik hipotesa semntara bahwa pada masa awal Islam pengaruh Hellenisme dan juga Filsafat Yunani terhadap tradisi keilmuan Islam sudah sedemikian kental, sehingga pada saat selanjutnya pengaruh itupun terus mewarnai perkembangan ilmu pada masa-masa berikutnya.
3. Perkembangan Ilmu Pada Masa Kejayaan Islam
Pada masa kejayaan kekuasaan Islam, khusunya pada masa pemerintahan Dinasti Umayah dan Dinasti Abbasiyah, ilmu berkembang sangat maju dan pesat. Kemajuan ini membawa Islam pada masa keemasannya, dimana pada saat yang sama wilayah-wilayah yang jauh dari kekuasaan Islam masih berada pada masa kegelapan peradaban (dark age).
Dalam sejarah Islam, kita mengenal nama-nama seperti al-Mansur, Al-Ma’mun, dan Harun Al-Rasyid, yang memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Pada masa pemerintahan al-Mansur misalnya, proses penerjemahan karya-karya filosof Yunani kedalam bahasa Arab berjalan dengan pesat. Dikabarkan bahwa al-Mansur telah memerintahkan penerjemahan naskah-naskah Yunani mengenai Filsafat dan ilmu, dengan memberikan imbalan yang besar kepada para ahli bahasa (penerjemah). Pada masa Harun Al-Rasyid (786-809) proses penerjemahan itu juga masih terus berlangsung. Harun memerntahkan Yuhana (Yahya) Ibn Musawayh, seorang dokter istana, untuk menerjemahkan buku-buku kuno mengenai kedokteran. Di masa itu juga diterjemahkan karya-karya dalam bidang astronomi, seperti Siddhanta; sebuah risalah India yang diterjemahkan oleh Muhammad bin Ibrahim Al-Fajari. Pada masa selanjutnya oleh Al-Khawarizmi Siddhanta ini dibuat versi baru terjemahannya dan diberikan komentar-komentar.
Perkembangan ilmu selanjutnya berada pada masa pemerintahan al-Makmun (813-833). Ia adalah seorang pengikutnmu’tazilah dan seorang rasionalis yang berusaha memaksakan pandangannya kepada rakyat melalui mekanisme Negara. Walaupun begitu, ia telah berjasa besar dalam mengembangkan ilmu dalam dunia Islam dengan membangun baitul hikmah, yang terdiri dari sebuah perpustakaan, sebuah observatorium, dan sebuah departemen penerjemahan. Orang terpenting di baitul hikmah adalah Hunain, seorang murid al-Musawayh, yang telah berjasa menerjemahkan buku-buku Plato, Aristoteles, Gelenus, Appolonius, dan Archimides. Selanjutnya pada pertengahan abad ke 10 muncul dua penerjemah terkemuka yaitu Yahya Ibn A’di dan Abu Ali Isa bin Ishaq bin Zera. Yahya banyak member komentar dan memperbaiki terjemahan mengenai karya-karya Aristoteles.
Selanjutnya pada masa perkembangan ini terdapat pula tokoh-tokoh Filsafat yang bergerak secara serius dalam kajian-kajian di luar Filsafat. Hal ini bisa difahami karena adanya kenyataan bahwa mereka menganggap ilmu-ilmu rasional sebagai bagian Filsafat. Atas dasar inilah mereka memperlakukan persoalan-persoalan fisika sebagaimana mereka memperlakukan masalah-masalah yang bersifat metafisika. Salah satu bukti nyata dari hal ini adalah kitab as-Syifa, sebuah ensiklopedi Filsafat Arab yang terbesar, yang berisi empat bagian. Bagian I mengenai logika, bagian II tentang fisika, bagian III tentang matematika, dan bagian IV membahas tentang metafisika. Dalam bagian fisika, Ibnu Sina memasukkan ilmu-ilmu Psikologi, zoology, geologi, dan botani, dan pada matematika, ia membahas geometri, ilmu hitung, astronomi, dan musik.
Selain adanya perkembangan ilmu yang dapat dikategorikan ke dalam bidang eksakta, matematika, fisika, kimia, geometri, dan lain sebagainya, sejarah juga mencatat kemajuan ilmu-ilmu keislaman, baik dalam bidang tafsir, hadis, fiqih, ushul fiqih, dan disiplin ilmu keislaman lainnya.
C. Perkembangan Masa Renaissance Filsafat Ilmu
Renaisans merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Zaman ini juga merupakan penyempurnaan kesenian, keahlian, dan ilmu pengetahuan yang diwujudkan dalam diri jenius serba bisa, Leonaro da Vinci. Penemuan mesin percetakan dan ditemukannya benua baru oleh Colombus memberikan dorongan lebih keras untuk meraih kemajuan ilmu. Kelahiran kembali sastra di Inggris, Perancis dan Spanyol diwakili Shakespeare, Spencer, Rabelais, dan Ronsard. Adanya penemuan ahli perbintangan seperti Copernicus dan Galileo menjadi dasar bagi munculnya astronomi modern yang merupakan titik balik dalam pemikiran ilmu dan Filsafat.
Teori Copernicus yang mengemukakan bahwa matahari berada dipusat jagad raya yang biasa disebut dengan teori Heliosentrisme, melahirkan revolusi pemikiran tentang alam semesta, terutama astronomi. Bacon adalah pemikir yang seolah-olah meloncat keluar dari zamannya dengan melihat perintis Filsafat ilmu. Ucapan Bacon yang terkenal adalah Knowledge is power (pengetahuan adalah kekuasaan).
D. Perkembangan Masa Modern Filsafat Ilmu
Setelah Galileo, Fermat, Pascal, dan Keppler berhasil mengembangkan penemuan mereka dalam ilmu, maka pengetahuan yang terpencar-pencar itu jatuh ke tangan dua sarjana, yang dalam ilmu modern memegang peran yang sangat penting. Mereka adalah Issac Newton dan Leinbiz. Di tangan dua orang sarjana inilah sejarah ilmu modern dimulai.
Dimasa ini terjadi perkembangan ilmu kimia yang sangat pesat. Selain itu banyak ditemukan mesin-mesin tanpa ada dasar ilmunya melainkan atas dasar percobaan, misalnya mesin uap yang kemudian mendasari kereta api, percobaan-percobaan listrik dan lain-lain. Penemuan itu semuanya yang melandasi terjadinya revolusi industry terutama di Inggris yang kemudian meluas ke Eropa.
Secara singkat dapat ditarik sebuah sejarah ringkas ilmu yang lahir saat itu. Perkembangan ilmu pada abad ke 18 telah melahirkan ilmu seperti taksonomi ekonomi, kalkulus, dan statistika. Di abad ke 19 lahir semisal pharmakologi, geofisika, geormophologi, palaentologi, arkeologi, dan sosiologi. Abad ke 20 mengenal ilmu informasi, logika matematika, mekanika kuantum, fisika nuklir, kimia nuklir, radiobiology, oceanografi, antropologi budaya, psikologi dan sebagainya
Pada zaman modern Filsafat dari berbagai aliran muncul. Pada dasarnya corak keseluruhan Filsafat modern itu mengambil warna pmikiran Filsafat sufisme Yunani, sedikit pengecualian pada Kant. Paham-paham yang muncul garis besarnya adalah rasionalisme, idealism, dan empirisme.
Sedangkan pada abad 20 aliran Filsafat banyak sekali sehingga sulit digolongkan, karena makin eratnya kerjasama internasional. Namun sifat-sifat Filsafat pada abad ini lawannya abad 19, yaitu anti positivis, pluratis, antroposentrisme, dan pembentukan subyektivitas modern.
DAFTAR PUSTAKA
Bakhtiar, Amsal 2004. Filsafat Ilmu. Jakarta: PT. Raja Grafindo Utama.
Salam,Burhanuddin. 2004. Sejarah Filsafat Ilmu dan Teknologi. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
[ Read More ]
Filsafat dan ilmu adalah dua kata yang saling terkait, baik secara substansial maupun historis, karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan Filsafat, sebaliknya perkembangan ilmu memperkuat keberadaan Filsafat. Filsafat telah berhasil merubah pola pemikiran bangsa Yunani dan umat manusia dari pandangan mitosentris menjadi logosentris. Dengan Filsafat, pola fikir yang selalu tergantung pada dewa diubah menjadi pola pikir yang tergantung pada rasio.
Pada pekembangan selanjutnya ilmu terbagi dalam beberapa disiplin, yang membutuhkan pendekatan, sifat, obyek, tujuan dan ukuran yang berbeda antara disiplin ilmu yang satu dengan yang lainnya. Pada gilirannya, cabang ilmu semakin subur dengan segala viariasinya. Namun tidak dapat juga dipungkiri bahwa ilmu yang semakin terspesialisasi itu semakin menambah sekat-sekat antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lain, sehingga muncul arogansi ilmu yang satu terhadap ilmu yang lain. Tidak hanya sekedar sekat-sekat antar displin dan arogansi ilmu, tetapi yang terjadi adalah terpisahnya ilmu itu dengan nilai luhur ilmu, yaitu untuk menyejahterakan umat manusia. Bahkan tidak mustahil terjadi, ilmu menjadi bencana bagi kehidupan manusia, seperti pemanasan global dan dehumanisasi.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu sisi ilmu berkembang dengan pesat, disisi lain, timbul kekhawatiran yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu itu karena tidak ada seorangpun atau lembaga yang meiliki otoritas untuk menghambat implikasi negatif dari ilmu.
Ilmu dan tekhnologi dalam konteks itu kehilanga ruhnya yang fundamental karna ilmu kemudian mengeliminir peran manusia dan bahkan manusia tanpa sadar menjadi budak ilmu dan teknologi. Karena itu, Filsafat ilmu berusaha mengembalikan ruh dan tujuan luhur ilmu agar ilmu tidak menjadi boomerang bagi kehidupan umat manusia.
Adapun bagaimana perkembangan Filsafat ilmu dari segi historisnya, akan di bahas pada Bab selanjutnya.
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN FILSAFAT ILMU
A. Perkembangan Awal Pemikiran Filsafat Ilmu
Periode Filsafat Yunani merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia karena pada waktu ini terjadi perubahan pola fikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola fikir mitosentris adalah pola fikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Perubahan pola fikir itu terlihat sederhana tetapi implikasinya tidak sesederhana yang dibayangkan kerena selama ini alam ditakuti dan dijauhi kemudian di dekati bahkan dieksploitasi. Manusia yang dulunya pasif dalam menghadapi fenomena alam menjadi lebih proaktif dan kreatif sehingga alam dijadikan obyek penelitian dan pengkajian. Dari proses inilah kemudian ilmu berkembang dari rahim Filsafat, yang akhirnya kita nikmati dalam bentuk teknologi. Karena itu periode perkembangan Filsafat Yunani merupakan entri poin untuk memasuki peradaban baru umat manusia.
Terjadinya perubahan yang besar dalam lapangan pengetahuan empiris yang berdasarkan sikap receptive attitude mind. Bangsa Yunani tak dapat menerima empirirs tersebut secara pasif-reseptif karena bangsa Yunani memiliki sikap jiwa: “an inguiring attitude, an inguiring mind”. Dengan demikian lahirlah pengetahuan filsafat yang pada zaman itu mempunyai arti yang lebih luas dari pada sekarang, yaitu meliputi semua bidang ilmu sebagai induk ilmu pengetahuan (mater scientarum).
Seperti yang kita ketahui bahwa secara bahasa Filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan/ kebenaran/ pengetahuan. Mencintai pengetahuan adalah awal proses manusia mau menggunakan daya fikirnya, sehingga dia mampu membedakan mana yang riil dan mana yang ilusi. Orang Yunani awalnya sangat percaya pada dongeng dan takhayul, tetapi lama kelamaan, terutama setelah mereka mampu membedakan yang riil dan yang ilusi, mereka mampu keluar dari kungkungan mitologi dan mendapatkan dasar pengetahuan ilmiah. Inilah titik awal manusia menggunakan rasio untuk meneliti dan sekaligus mempertanyakan dirinya dan alam jagat raya.
Karena manusia selalu berhadapan dengan alam yang begitu luas dan penuh misteri, timbul rasa ingin mengetahui rahasia alam itu. Lalu timbul pertanyaan dalam pikirannya; dari mana datangnya alam ini, bagaimana kejadiannya, begaimana kemajuannya dan kemana tujuannya? Pertanyaan semacam inilah yang selalu menjadi pertanyaan dikalangan filosof Yunani, sehingga tidak heran kemudian mereka disebut dengan filosof alam karena perhatiannya yang begitu besar kepada alam. Filosof alam ini juga disebut filosof pra Socrates, sedangkan Socrates dan setelahnya disebut dengan filosof pasca Socrates yang tidak haya mengkaji tentang alam, tetapi manusia dan perilakunya.
Dalam buku Filsafat Umum-nya Ahmad Tafsir yang dikutip oleh Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A dalam bukunya Filsafat Ilmu, dikatakan bahwa filosof alam pertama yang mengkaji tentang asal usul alam adalah Thales (624-546SM). Pertanyaannya adalah “apa sebenarnya asal usul dari alam semessta ini?” pertanyaan ini sangat mendasar, terlepas apapun itu jawabannnya. Namun yang penting adalah pertanyaan itu dijawab dengan pendekatan rasional bukan dengan pendekatan mitos atau kepercayaan. Ia mengatakan asal alam adalah air karena air unsur yang sangat penting dalam kehidupan. Dan air dapat berubah menjadi gas, seperti uap dan benda padat seperti es, dan bumi juga berasal dari air.
Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A mengutip dari buku Sejarah Filsafat Yunani karangan K. Bertens dikatakan bahwa setelah Thales, muncul Anaximandros (610-540SM). Anaximandros mencoba menjelaskan bahwa substansi pertama itu bersifat kekal, tidak terbatas, dan meliputi segalanya. Dia tidak setuju unsur utama alam adalah salah satu dari unsur-unsur yang ada, seperti air atau tanah. Unsur utama alam harus yang mencakup segalanya di atas segalanya, yang dinamakan apeiron. Jika ia adalah air, maka air harus meliputi segalanya termasuk api yang merupakan lawannya. Padahal tidak mungkin air menyingkirkan unsur api. Karena itu Anaximandros tidak puas dengan mnunjukkan salah satu unsur sebagai prinsip alam, tetapi ia mencari yang lebih dalam yaitu zat yang tidak dapat diamati oleh panca indra.¬¬¬¬
Berbeda dengan Thales dan Anaximandros, Heraklitos (540-480SM) melihat alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah; sesuatu yang dingin berubah menjadi panas, yang panas berubah menjadi dingin. Itu berarti bahwa apa apabila kita hendak memahami kosmos, kita harus menyadari bahwa kosmos itu dinamis. Segala sesuatu yang saling bertentangan dan dalam pertentangan itulah kebenaran. Karena itu dia berkesimpulan, tidak ada satu pun yang benar-benar ada, semuanya menjadi. Ungkapan yang terkenal dari Heraklitos dalam menggambarkan perubahan ini adalah panta uden menei (semuanya mengalir dan tidak ada satupun yang tinnggal mantap).
Itulah sebabnya ia mempunyai kesimpulan bahwa yang mendasar dalam alam semesta ini adalah bukan bahannya, melainkan aktor dan penyebabnya, yaitu api. Api adalah unsur yang paling asasi dalam alam karena api dapat mengeraskan adonan roti dan dari sisi lain dapat melunakkan es. Artinya, api adalah aktor pengubah pada alam ini, sehingga api pantas dianggap sebagai symbol perubahan itu sendiri.
Filosof alam yang cukup berpengaruh adalah Parmanides (515-440SM) yang lebih muda umurnya dibandingkan Heraklitos. Pandangannya bertolak belakang dengan Heraklitos. Menurut Heraklitos, realitas seluruhnya bukanlah sesuatu yang lain dari pada gerak dan perubahan, sedangkan menurut parmanides, gerak dan perubahan tidak mungkin terjadi. Menurutnya realitas merupakan keseluruhan yang bersatu, tidak bergerak dan tidak berubah. Dia menegaskan bahwa yang ada itu ada. Inilah kebenaran. Coba bayangkan apa konsekuensi bila ada orang yang memungkiri kebenaran itu. Ada dua pengandaian, yang pertama adalah orang bisa mengemukakan bahwa yang ada itu tidak ada. Kedua, atau orang dapat mengemukakan bahwa yang ada itu serentak ada dan serentak tidak ada. Pengandaian pertama tertolak dengan sendirinya karena yang tidak ada memang tidak ada. Yang tidak ada tidak dapat dipikirkan dan menjadi obyek pembicaraan. Pengandaian yang kedua tidak dapat diterima karena antara ada dan tidak ada tidak terdapat jalan tengah, yang ada akan tetap ada dan yang tidak ada tidak mungkin menjadi ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang ada itu ada dan itulah satu-satunya kebenaran.
Phytagoras (580-500SM) mengembalikan segala sesuatu pada bilangan. Baginya tidak ada satu pun yang di alam ini terlepas dari bilangan. Semua realitas dapat diukur dengan bilangan (kuantitas). Karena itu ia berpendapat bahawa bilangan adalah unsur utama dari alam dan sekaligusa menjadi ukuran. Kesimpulan ini ditarik dari kenyataan bahwa realitas alam adalah harmoni antara bilangan dan gabungan antara dua hal yang berlawanan. Kalau segala-galanya adalah bilangan, itu berarti bahwa unsur bilangan merupakan juga unsur yang terdapat dalam segala sesuatu. Unsur-unsur bilangan itu adalah genap dan ganjil, terbatas dan tidak terbatas. Demikian juga seluruh jagad raya merupakan suatu harmoni yang mendamaikan hal-hal yang berlawanan. Artinya, segala sesuatu berdasarkan dan dapat dikembalikan pada bilangan.
Jasa Phytagoras ini sangat besar dalam perkembbangan ilmu, terutama ilmu pasti dan ilmu alam. Ilmu yang dikembangkan kemudian hari sampai hari ini sangat tergantung pada pendekatan matematika. Galileo menegaskan bahwa alam ditulis dalam bahasa matematika. Dalam Filsafat ilmu, matematika merupakan sarana ilmiah yang terpenting dan akurat karena dengan pendekatan matematikalah ilmu dapat diukur dengan benar dan akurat. Disamping itu, matematika dapat menyederhanakan uraian yang panjang dalam bentuk symbol sehingga lebih cepat dipahami.
Setelah berakhirnya masa filosof alam, maka muncul masa transisi, yakni penelitian terhadap alam tidak menjadi fokus utama tetapi sudah mulai menjurus pada memberikan jawaban yang memuaskan sehingga timbullah kaum sofis. Kaum sofis ini memluai kajian tentang manusia dan menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Tokoh uatamanya adalah Protagoras (481-411 SM). Ia menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Pernyataan ini merupakan cikal bakal humanisme. Pertanyaan yang muncul adalah apakah yang dimaksudnya itu manusia individu atau manusia secara umumnya. Memang dua hal itu menimbulkan konsekuensi yang sungguh berbeda. Namun tidak ada jawaban yang pasti, mana yang dimaksud oleh Protagoras. Yang jelas ia menyatakan bahwa kebenaran itu bersifat subyektif dan relative. Akibatnya tidak akan ada ukuran yang absolut dalam etika, metafisika, maupun agama, bahkan teori matematika tidak dianggapnya mempunyai kebenaran yang absolut.
Tokoh lain dari kaum sofis adalah Gorgias. Ia datang ke Athena pada tahun 427 SM dari Leontini. Menurutnya ada tiga proposisi: pertama, tidak ada yang ada, maksudnya relitas itu sebenarnya tidak ada. Pemikiran lebih baik tidak menyatakan apa-apa tentang realitas. Kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak akan dapat diketahui. Ini disebabkan oleh pengindraan itu tidak dapat dipercaya, pengindraan itu sumber ilusi. Akal tidak juga mampu meyakinkan kita bahwa semesta alam ini ada karena akal kita telah diperdaya oleh dilema subyektivitas. Dan ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain.
Pengruh positif kaum sofis cukup terasa karena mereka membangkitkan semangat berfilsafat. Mereka mengingatkan filosof bahwa persoalan pokok dalam Filsafat bukanlah alam melainkan manusia. Mereka juga membangkitkan jiwa humanism. Mereka tidak memberikan jawaban final tentang etika, agama dan metafisika. Ini membuka peluang bagi para filosof untuk lebih kreatif lagi dalam berfikir. Ilmu juga mendapat ruang yang sangat kondusif dalam pemikiran kaum sofis karena mereka memberi ruang untuk berspekulasi dan sekaligus merelatifkan teori ilmu, sehingga muncul sintesa baru. Dalam Filsafat ilmu, pandangan relative tentang kebenaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses mencari ilmu. Karena itu, ilmu itu terbatas, tetapi proses mencari ilmu tidak terbatas.
Namun para filosof setelah kaum sofis tidak setuju dengan pandangan tersebut, seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka menolak relativiasme kaum sofis. Menurut mereka, ada kebenaran obyektif yang bergantung pada manusia. Socrates membuktikan adanya kebenaran obyektif itu dengan menggunakan metode yang bersifat praktis dan dijalankan melalui percakapan-percakapan sehingga metode yang digunakannya biasanya disebut metode dialog karena dialog memiliki peranan penting dalam menggali kebenaran yang obyektif.
Socrates berpendapat bahwa kehidupan dan ajaran adalah hal yang satu dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu dasar dari segala penelitian dan pembahasan adalah pengujian diri sendiri. Bagi Socrates pengetahuan yang sangat berharga adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Semboyan yang paling digemarinya adalah apa yang tertera pada Kuil Delphi, yaitu: “kenalilah dirimu sendiri”.
Periode setelah Socrates disebut dengan zaman keemasan Filsafat Yunani karena pada zaman ini kajian-kajian yang muncul adalah perpaduan antara Filsafat alam dan Filsafat tentang manusia. Tokoh yang sangat menonjol adalah Plato yang sekaligus murid dari Socrates dan yang menulis ide-ide dari Socrates. Menurutnya, esensi itu mempunyai realitas dan realitasnya ada dalam alam idea. Kebenaran umum itu ada bukan dibuat-buat bahkan sudah ada di alam idea. Plato menggambarkan kebenaran umum adalah rujukan bagi alam empiris.
Plato berhasil mensintesakan pemikiran Heraklitos dan Parmanides. Menurut Heraklitos, segala sesuatu berubah, sedangkan menurut Parmanides, segala sesuatu diam. Untuk mendamaikan pandangan ini Plato berpendapat bahwa pandangan Heraklitos benar, tetapi hanya berlaku bagi alam empiris saja, dan pandangan Parmanides juga benar, tetapi hanya berlaku bagi idea-idea bersifat abadi dan idea inilah yang menjadi dasar bagi pengenalan yang sejati.
Puncak kejayaan Filsafat Yunani terjadi pada masa Aristoteles. Ia murid Plato, seorang filosof yang berhasil menemukan pemecahan persoalan-persoalan besar Filsafat yang dipersatukannya dalam suatu system; logika, matematika, fisika, dan metafisika. Logika Aristoteles berdasarkan pada analisis bahasa yang disebut silogisme. Pada dasarnya silogisme terdiri dari tiga premis: premis mayor, premis minor dan konklusi. Logika Aristoteles ini juga disebut dengan logika deduktif, yang mengukur valid atau tidaknya sebuah pemikiran.
Aristoteles yang pertamakali membagi Filsafat pada hal yang teoritis dan praktis. Yang teoritis mencakup logika, metafisika, fisika, sedangkan yang praktis mencakup etika, ekonomi dan politik. Pembagian ilmu inilah yang menjadi pedoman juga bagi klasifikasi ilmu dikemudian hari. Aristoteles dianggap bapak ilmu karena dia mampu meletakkan dasar-dasar metode ilmiah secara sistematis.
Filsafat Yunani yang rasional itu boleh dikatakan berakhir setelah Aristoteles menuangkan pemikirannya. Akan tetapi sifat rasional itu masih digunakan selama berabad-abad sesudahnya sampai sebelum Filsafat benar-benar memasuki dan tenggelam dalam abad pertengahan. Namun jelas, setelah periode ketiga filosof besar itu mutu filsfat semakin merosot, kemunduran Filsafat itu sejalan dengan kemunduran politik ketika itu, yaitu sejalan dengan terpecahnya kerajaan Macedonia menjadi pecahan-pecahan kecil setelah wafatnya Alexander The Great. Tepatnya pada ujung zaman helenisme, yaitu pada ujung sebelum masehi menjelang neo Platonisme, Filsafat benar-benar mengalami kemunduran.
B. Perkembangan Pemikiran Abad Pertengahan Filsafat Ilmu
Perkembangan pemikiran abad pertengahan Filsafat ilmu itu dapat juga disebut dengan perkembangan Filsafat ilmu di zaman Islam. Sebelum di uaraikan sejarah dan perkembangan ilmu dalam Islam, ada baiknya diuraikan sedikit tentang pandangan Islam terhadap ilmu. Hal ini penting untuk diketahui karena menjadi landasan bagi pengembangan ilmu di sepanjang sejarah kehidupan umat Islam.
Sejak awal kelahirannya, Islam sudah memberikan penghargaan yang begitu besar kepada ilmu. Sebagaimana sudah diketahui, bahwa Muhhammad saw ketika diutus oleh Allah sebagai Rasul, hidup dalam masyarakat yang terbelakang dimana paganism tumbuh menjadi sebuah identitas yang melekat pada masyarakat Arab pada masa itu. Kemudian Islam datang menawarkan cahaya penerang yang mengubah masyarakat Arab jahiliyyah menjadi masyarakat yang berilmu dan beradab.
Kalau dilacak akar sejarahnya, pandangan Islam tentang pentingnya ilmu tumbuh bersamaan dengan munculnya Islam itu sendiri. Ketika rasulullah menerima wahyu yang pertama yang mula-mula diperintahkan kepadanya adalah “membaca”. Dengan demikian, al-Qur'an dan hadis menjadi sumber ilmu yang dikembangkan oleh umat Islam dalam spectrum yang seluas-luasnya. Selanjutnya kita akan masuk kedalam inti pembahasan, yaitu tentang sejarah dan perkembangan ilmu dalam Islam. Untuk memudahkan pemahaman kita penulis mencoba membagi sejarah perkembangan ilmu dalam Islam dalam beberapa zaman, seperti uraian berikut:
1. Penyampaian Ilmu Dalam Filsafat Yunani Ke Dunia Islam
Pengalihan pengetahuan ilmiah dan Filsafat Yunani ke dunia Islam, dan penyerapan serta pengintegrasian pengetahuan itu oleh umat Islam, merupakan sebuah catatan sejarah yang unik. Dalam sejarah peradaban manusia, amat jarang ditemukan suatu kebudayaan asing dapat diterima sedemikian rupa oleh kebuadaan lain, yang kemudian menjadikannya landasan bagi perkembangan intelektual dan pemahaman filosofisnya.
Dalam perjalanan ilmu dan juga Filsafat di dunia Islam, pada dasarnya terdapat rekonsiliasi dalam arti mendekatkan dan mempertemukan dua pandangan yang berbeda, bahkan sering kali ekstrim antara pandangan Filsafat Yunani, seperti Filsafat Plato dan Aristoteles, dengan pandangan keagamaan dalam Islam yang sering kali menimbulkan benturan-benturan. Sebagai contoh konkret dapat disebutkan bahwa Plato dan Aristoteles telah memberikan pengaruh yang besar pada mazhab-mazhab Islam, khususnya mazhab eklektisisme. Al- FArabi dalam hal ini memiliki sikap yang jelas krena ia percaya pada kesatuan Filsafat dan bahwa tokoh-tokoh Filsafat harus bersepakat diantara mereka sepanjang yang menjadi tujuan mereka adalah kebenaran. Bahkan bisa dikatakan bahwa para filosof muslim mulai dari al-Kindi sampai Ibnu Rusyd terlibat dalam upaya rekonsiliasi tersebut, dengan cara mengemukakan pandangan-pandangan yang relative baru dan menarik. Usaha-usaha mereka pada gilirannya menjadi alat dalam penyebaran Filsafat dan penetrasinya ke dalam studi-studi keislaman lainnya, dan tak diragukan lagi, upaya-upaya rekonsiliasi oleh para filosof muslim ini menghasilkan afinitas dan ikatan yang kuat antara Filsafat Arab dan Filsafat Yunani.
Selanjutnya, ketika berbicara tentang proses penyampaian ilmu dan Filsafat Yunani ke dunia Islam, kita harus melihat sisi lain yang juga menunjang keberhasilan Islam dalam menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sisi lain itu adalah aktivitas penerjemahan. Menurut C. A. Qadir yang dikutip oleh Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A. dalam bukunya Filsafat Ilmu, proses penerjemehan dan penafsiran buku-buku Yunani di negri-negri Arab di mulai jauh sebelum lahirnya agama Islam atau penaklukkan Timur Dekat oleh bagsa Arab pada tahun 614M. Jauh sebelum umat Islam dapat menaklukkan daerah-daerah di Tmur Dekat, pada saat itu Suriah merupakan tempat bertemunya dua kekuasaan dunia, Romawi dan Persia. Atas dasar itu bangsa Suriah disebut-sebut memainkan peranan yang sangat penting dalam penyebaran budaya Yunani ke Timur dan Barat. Dikalangan umat Kristen di Suriah, terutama kaum Nestorian, ilmu pengetahuan Yunani dipelajari dan disebarluaskan melalui sekolah-sekolah mereka. Walaupun tujuan uatama mereka adalah menyebarluaskan pengetahuan injil, namun pengetahuan ilmiah seperti ilmu kedokteran banyak diminati oleh pelajar.
Selain itu pada masa ini juga didapati pusat-pusat ilmu pengetahuan seperti Ariokh, Ephesus, dan Iskandariyah di aman buku-buku Yunani Purba masih dibaca dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa.
2. Perkembangan ilmu pada masa Islam klasik
Sebagaimana telah disinggung diatas bahwa pentingnya ilmu pengetahuan sangat ditekankan oleh Islam sejak awal, mulai masa Nabi sampai dengan Khulafaurrasyidin, pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan berjalan dengan pesat seiring dengan tantangan zaman.
Selanjutnya, seperti yang dikutip oleh Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A., dari buku Kaki Langit Peradaban Islam karya Nurcholis Madjid, dikatakan bahwa satu hal yang patut dicatat dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan adalah peristiwa Fitnah Kubra, yang ternyata tidak hanya membawa konsekuensi, tetapi ternyata juga membawa perubahan besar bagi pertumbuhan dan perkembangan ilmu di dunia Islam. Pasca terjadinya Fitnatul Kubra muncul berbagai golongan yang berkembang kaarena alasan-alasan politis. Namun di luar konlik yang muncul saat itu, sejarah mencatat dua tokoh besar yang tidak ikut terlibat dalam perdebatan teologis yang cenderung mengkafirkan satu sama lain, tetapi justru mencurahkan perhatiannya pada bidang ilmu agama. Kedua tokoh itu adalah Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Yang pertama mencurahkan perhatianya pada ilmu hadis, sementara yang disebut belakangan lebih berkonsentrasi pada ilmu tafsir. Kedua tokoh tersebut sering dianggap sebagai pelopor tumbuhnya institusi keulamaan dalam Islam. Sekaligus berarti pelopor kajian mendalam dan sistematis dalam bidang ilmu agama Islam.
Tahap penting berikutnya dalam proses perkembangan dari tradisi keilmuan Islam adalah masuknya unsur-unsur dari luar ke dalam Islam, khusunya unsur-unsur budaya Perso-Semitik dan budaya Hellenisme. Yang disebut belakangan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pemikiran Islam ibarat pisau bermata dua. Satu sisi ia mendukung Jabariyah (antara lain oleh Jahm bin Safwan), sedang disisi lain ia mendukung Qadariyah (antara lain Washil bin Atha’, tokoh dan pendiri mu’tazilah). Dari adanya pandangan yang dikotomis antara keduanya, kemudian muncul usaha menengahi dengan menggunakan argument-argumen Hellenisme, terutama Filsafat Aristoteles. Sikap menengahi itu terutama dilakukan oleh Abu Hasan Al- Asy’ari dan al Maturidi yang juga menggunakan unsur Hellenisme.
Berdasarakan uraian di atas dapat ditarik hipotesa semntara bahwa pada masa awal Islam pengaruh Hellenisme dan juga Filsafat Yunani terhadap tradisi keilmuan Islam sudah sedemikian kental, sehingga pada saat selanjutnya pengaruh itupun terus mewarnai perkembangan ilmu pada masa-masa berikutnya.
3. Perkembangan Ilmu Pada Masa Kejayaan Islam
Pada masa kejayaan kekuasaan Islam, khusunya pada masa pemerintahan Dinasti Umayah dan Dinasti Abbasiyah, ilmu berkembang sangat maju dan pesat. Kemajuan ini membawa Islam pada masa keemasannya, dimana pada saat yang sama wilayah-wilayah yang jauh dari kekuasaan Islam masih berada pada masa kegelapan peradaban (dark age).
Dalam sejarah Islam, kita mengenal nama-nama seperti al-Mansur, Al-Ma’mun, dan Harun Al-Rasyid, yang memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Pada masa pemerintahan al-Mansur misalnya, proses penerjemahan karya-karya filosof Yunani kedalam bahasa Arab berjalan dengan pesat. Dikabarkan bahwa al-Mansur telah memerintahkan penerjemahan naskah-naskah Yunani mengenai Filsafat dan ilmu, dengan memberikan imbalan yang besar kepada para ahli bahasa (penerjemah). Pada masa Harun Al-Rasyid (786-809) proses penerjemahan itu juga masih terus berlangsung. Harun memerntahkan Yuhana (Yahya) Ibn Musawayh, seorang dokter istana, untuk menerjemahkan buku-buku kuno mengenai kedokteran. Di masa itu juga diterjemahkan karya-karya dalam bidang astronomi, seperti Siddhanta; sebuah risalah India yang diterjemahkan oleh Muhammad bin Ibrahim Al-Fajari. Pada masa selanjutnya oleh Al-Khawarizmi Siddhanta ini dibuat versi baru terjemahannya dan diberikan komentar-komentar.
Perkembangan ilmu selanjutnya berada pada masa pemerintahan al-Makmun (813-833). Ia adalah seorang pengikutnmu’tazilah dan seorang rasionalis yang berusaha memaksakan pandangannya kepada rakyat melalui mekanisme Negara. Walaupun begitu, ia telah berjasa besar dalam mengembangkan ilmu dalam dunia Islam dengan membangun baitul hikmah, yang terdiri dari sebuah perpustakaan, sebuah observatorium, dan sebuah departemen penerjemahan. Orang terpenting di baitul hikmah adalah Hunain, seorang murid al-Musawayh, yang telah berjasa menerjemahkan buku-buku Plato, Aristoteles, Gelenus, Appolonius, dan Archimides. Selanjutnya pada pertengahan abad ke 10 muncul dua penerjemah terkemuka yaitu Yahya Ibn A’di dan Abu Ali Isa bin Ishaq bin Zera. Yahya banyak member komentar dan memperbaiki terjemahan mengenai karya-karya Aristoteles.
Selanjutnya pada masa perkembangan ini terdapat pula tokoh-tokoh Filsafat yang bergerak secara serius dalam kajian-kajian di luar Filsafat. Hal ini bisa difahami karena adanya kenyataan bahwa mereka menganggap ilmu-ilmu rasional sebagai bagian Filsafat. Atas dasar inilah mereka memperlakukan persoalan-persoalan fisika sebagaimana mereka memperlakukan masalah-masalah yang bersifat metafisika. Salah satu bukti nyata dari hal ini adalah kitab as-Syifa, sebuah ensiklopedi Filsafat Arab yang terbesar, yang berisi empat bagian. Bagian I mengenai logika, bagian II tentang fisika, bagian III tentang matematika, dan bagian IV membahas tentang metafisika. Dalam bagian fisika, Ibnu Sina memasukkan ilmu-ilmu Psikologi, zoology, geologi, dan botani, dan pada matematika, ia membahas geometri, ilmu hitung, astronomi, dan musik.
Selain adanya perkembangan ilmu yang dapat dikategorikan ke dalam bidang eksakta, matematika, fisika, kimia, geometri, dan lain sebagainya, sejarah juga mencatat kemajuan ilmu-ilmu keislaman, baik dalam bidang tafsir, hadis, fiqih, ushul fiqih, dan disiplin ilmu keislaman lainnya.
C. Perkembangan Masa Renaissance Filsafat Ilmu
Renaisans merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Zaman ini juga merupakan penyempurnaan kesenian, keahlian, dan ilmu pengetahuan yang diwujudkan dalam diri jenius serba bisa, Leonaro da Vinci. Penemuan mesin percetakan dan ditemukannya benua baru oleh Colombus memberikan dorongan lebih keras untuk meraih kemajuan ilmu. Kelahiran kembali sastra di Inggris, Perancis dan Spanyol diwakili Shakespeare, Spencer, Rabelais, dan Ronsard. Adanya penemuan ahli perbintangan seperti Copernicus dan Galileo menjadi dasar bagi munculnya astronomi modern yang merupakan titik balik dalam pemikiran ilmu dan Filsafat.
Teori Copernicus yang mengemukakan bahwa matahari berada dipusat jagad raya yang biasa disebut dengan teori Heliosentrisme, melahirkan revolusi pemikiran tentang alam semesta, terutama astronomi. Bacon adalah pemikir yang seolah-olah meloncat keluar dari zamannya dengan melihat perintis Filsafat ilmu. Ucapan Bacon yang terkenal adalah Knowledge is power (pengetahuan adalah kekuasaan).
D. Perkembangan Masa Modern Filsafat Ilmu
Setelah Galileo, Fermat, Pascal, dan Keppler berhasil mengembangkan penemuan mereka dalam ilmu, maka pengetahuan yang terpencar-pencar itu jatuh ke tangan dua sarjana, yang dalam ilmu modern memegang peran yang sangat penting. Mereka adalah Issac Newton dan Leinbiz. Di tangan dua orang sarjana inilah sejarah ilmu modern dimulai.
Dimasa ini terjadi perkembangan ilmu kimia yang sangat pesat. Selain itu banyak ditemukan mesin-mesin tanpa ada dasar ilmunya melainkan atas dasar percobaan, misalnya mesin uap yang kemudian mendasari kereta api, percobaan-percobaan listrik dan lain-lain. Penemuan itu semuanya yang melandasi terjadinya revolusi industry terutama di Inggris yang kemudian meluas ke Eropa.
Secara singkat dapat ditarik sebuah sejarah ringkas ilmu yang lahir saat itu. Perkembangan ilmu pada abad ke 18 telah melahirkan ilmu seperti taksonomi ekonomi, kalkulus, dan statistika. Di abad ke 19 lahir semisal pharmakologi, geofisika, geormophologi, palaentologi, arkeologi, dan sosiologi. Abad ke 20 mengenal ilmu informasi, logika matematika, mekanika kuantum, fisika nuklir, kimia nuklir, radiobiology, oceanografi, antropologi budaya, psikologi dan sebagainya
Pada zaman modern Filsafat dari berbagai aliran muncul. Pada dasarnya corak keseluruhan Filsafat modern itu mengambil warna pmikiran Filsafat sufisme Yunani, sedikit pengecualian pada Kant. Paham-paham yang muncul garis besarnya adalah rasionalisme, idealism, dan empirisme.
Sedangkan pada abad 20 aliran Filsafat banyak sekali sehingga sulit digolongkan, karena makin eratnya kerjasama internasional. Namun sifat-sifat Filsafat pada abad ini lawannya abad 19, yaitu anti positivis, pluratis, antroposentrisme, dan pembentukan subyektivitas modern.
DAFTAR PUSTAKA
Bakhtiar, Amsal 2004. Filsafat Ilmu. Jakarta: PT. Raja Grafindo Utama.
Salam,Burhanuddin. 2004. Sejarah Filsafat Ilmu dan Teknologi. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
PENDAHULUAN
Pembaharuan yang dilakukan dalam tanzimat belum dapat meraih hasil seperti yang di harapkan. Lebih jauh malah mendapatkan kritikan-kritikan dari luar kaum cendikiawan. Kegagalan oleh tanzimat dalam mengganti konstitusi yang absolut merupakan cambuk untuk usaha-usaha selanjutnya. Untuk mengubah kekuasaan yang absout maka timbullah usaha atau gerakan dari kaum cendikiawan dalam melanjutkan usaha-usaha tanzimat.
Sementara itu, menurut L. Stoddard yang dikutip Badriyatim kemudian dikutip kembali oleh Dr. H. A. Fattah Wibisono, M.A dalam bukunya Pemikiran Para Lokomotif Pembaharuan di Dunia Islam, Eropa dalam abad ke Sembilan belas sudah jauh maju meninggalkan Dunia Islam. Eropa sudah dipersenjatai dengan ilmu modern dan penemuan yang membuka rahasia alam. Satu demi satu negri Islam yang sedang rapuh itu jatuh ke tangan Barat. Dalam waktu yang tidak lama, kerajaan-kerajaan besar Eropa telah membagi bagi Dunia islam. Inggris merebut india dan Mesir. Rusia menyebrangi Kaukasus dan menguasai Asia Tenggara. Prancis menguasai Afrika Utara, dan bangsa-bangsa Eropa.
USMANI MUDA DAN TURKI MUDA
A. USMANI MUDA
Golongan intelegensia Kerajaan Usmani yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan di kenal dengan nama usmani muda (yeni usmanlilar-Young Ottoman). Pemikiran-pemikiran yang diajukan pemuka-pemuka usmani muda-lah yang mempengaruhi pembaharuan yang diadakan sesudah zaman Tanzimat.
Usmani muda pada asalnya merupakan perkumpulan rahasia yang didirikan di tahun 1865 dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan absolut kerajaan Usmani menjadi pemerintahan konstitusional.
Menurut Niyyazi Berkes, seorang guru besar Islamic Studies di McGill University, Canada yang kami kutip dari Dr. H. A. Fattah Wibisono, M.A dalam bukunya Pemikiran Para Lokomotif Pembaharuan di Dunia Islam, bahwa gerakan usmani muda atau ittipaki-Humavat mula-mula muncul tahuk 1865. Mereka bertujuan untuk mengadakan perlawanan secara rahasia terhadap kekuasaan absolut sultan. Terutama sekali atas pemberlakuan pemerinatahan absolut menjadi pemerintahan konstitusional. Para tokoh Usmani Muda banyak yang melakukan gerakan rahasia dalam menentang kekuasaan absolut sultan. Namun akhirnya sikap politik mereka diketahui oleh sultan. Akhirnya mereka banyak yang lari ke Eropa dan disanalah mereka menyusun kekuatan. Di Eropa mereka kemudian mendapat sebutan Usmani Muda. Setelah situasi Turki aman kembali, mereka pun banyak yang pulang ke tanah air untuk melakukan pembaharuan, sebuah cita-cita yang sempat tersendat.
Gagasan pemikiran yang dikembangkan Usmani Muda ini banyak memiliki pengaruh terhadap pembaharuan yang dilakukan di turki pasca periode Tanzimat. Pergaulan tokoh-tokoh Usmani Muda dengan pemikir-pemikir dari Perancis dan Inggris yang cukup liberal sedikit banyak membawa pengaruh bagi gerakan Usmani Muda ini. Maka beberapa pembaharuan mereka pun cukup bersifat liberal. Untuk melancarkan usaha pembaharuannya ini, kalangan Usmani Muda memanfaatkan media masa sebagai saluran penyebarannya. Antara lain surat kabar Tasvir-i-Efkar (gambaran pemikiran) yang didirikan Ibrahim Sinasi Effendi. Ketika Ibrahim lari ke luar negri karena tekanan dari sultan, surat kabar ini dipimpin oleh Namik Kemal, salah satu tokoh Usmani Muda yang lain.
Setelah mengalami perjuangan yang berat dengan pemuka-pemuka kerajaan, maka pada tanggal 23 Desember 1876 tercapaiah persetujuan tentang konstitusi sebagai Undang-Undang dasar yang baru bagi Turki, akan tetapi isinya masih otokrasi sehingga masih belum sesuai dengan apa yang diarapkan. Dan akhirnya Undang-Undang yang baru bagi Turki itu dilanggar juga oleh Sultan Abdul Hamid II II yakni dengan membubarkan parlemen dan para pemuka-pemukanya ditangkap dengan demikian maka berakhirlah riwayat perjuangan Usmani Muda.
Beberapa tokoh dan para pembaharu dalam gerakan Usmani Muda antara lain sebagai berikut:
1. Ziya Pasha
Zia lahir pada tahun 1825 di Istanbul dan meninggal pada tahun 1880. Ia anak seorang pegawai Kantor Bea Cukai Istanbul. Setelah menyelesaikan pelajaran pada sekolah Sulaymaniye, yang didirikan Sultan Mahmud II ini diangkat menjadi pegawai pemerintah selagi masih berusia muda. Atas usaha Mustafa Rasyid Pasha. Pada tahun 1854 ia diterima menjadi salah satu sekrtaris sultan. Namun permusuhannya dengan Ali Pasha membuat ia terpaksa pergi ke Eropa di tahun 1867 dan tinggal disana selama lima tahun.
Usaha-usaha pembaharuannya antara lain bahwa kerajaan Usmani menurut pendapatnya harus dibangun dengan system pemerinatahan konstitusional, tidak dengan kekuasaan absolut. Menurutnya Negara Eropa maju disebabkan tidak adanya lagi pemerinatahan yang absolut, semuanya dengan system pemerintahan konstitusional. Dalam system kontitusional, harus ada Dewan Perwakilan Rakyat. Alasan perlua adanya DPR ini adalah agar perbedaan pendapat dapat ditampung dan kritik terhadap pemerintah diperlukan untuk kepentingan pemerintah dan rakyat. DPR-lah yang nantinya memperjuangkan perbedaan pendapat diakalangan umat Islam. Sebagai orang yang taat menjalankan agama Islam, Ziya sebenarnya tidak sepenuhnya setuju terhadap pembaharuan yang hanya mencomot ide-ide barat tanpa sikap kritis. Menurutnya, umat Islam harus tetap mengkritisi setiap kebudayaan barat dan nilai-nilai kemajuan yang dibawanya. Itulah sebabnya ia lebih menilik kepada keseuaian antara kepentingan rakyat dengan ide pembaharuan yang datangnya dari barat. Dalam hal demikian, ia juga tidak sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa agama Islam dapat dianggap sebagai penghalang kemajuan.
2. Midhat Pasya
Nama lengkapnya Hafidz Ahmad Syafiq Midat Pasya. Ia lahir pada tahun 1822 M di Istambul Turki dan wafat pada tahun 1884 M. Pendidikan agamanya diperoleh dari ayahnya sendiri. Dalam usia 10 tahun ia telah hafiz al-Qur'an. Oleh karena itu ia digelari al-Hafidz. Pendidikannya yang tertinggi adalah pada Universitas al-Fatih.
Kemudian dalam usia belasan tahun ia menjadi pegawai di Biro Perdana Mentri. Di tahun 1858 ia diberi cuti untuk berkunjung selama enam bulan ke Eropa. Kemudian ia diangkat beberapa kali sebagai Gubernur di berbagai daerah. Dalam jabatan ini ia menunjukkan kecakapan luar biasa. Di tahun 1872 ia diangkat oleh Sultan Abdul Aziz menjadi perdana mentri. Tetapi karena selalu mengalami bentrokan dengan kekuasaan absolut sultan, ia diberhentikan beberapa bulan kemudian.
Sebagai tokoh gerakan Usmani Muda, oleh sahabat seperjuangannya ia dipercayakan memegang pemerintahan dan sekaligus memperjuangkan cita-cita gerakan ittu. Maka ia, selain menjadi Gubernur di Balkan dan Baghdad, pada Tahun 1872 berhasil menjadi menteri Kehakiman dan kemudian menjadi Perdana Mentri.
Midhat Pasha adalah Mentri Kehakiman dalam Kabinet Muhammad Rusydie Pasha pada masa Kekhalifahan Abdul Aziz. Dia pernah membujuk Khalifah Abdul Aziz untuk menyusun suatu rancangan konstitusi berdasarkan system demokrasi barat. Dia pernah menulis surat pada khalifah dan mendorongnya memperbaiki status quo dengan menetapkan suatu konstitusi baru.
Sultan Abdul Aziz menemui Midhat Pasha sebagaimana mestinya dan menerima suratnya tersebut. Setelah membaca surat tersebut, Abdul Aziz sangat murka. Ia memerintahkan untuk segera memecat Midhat Pasha dari pemerintahan dan mengasingkannya sebagai wali (gubernur) di Salonika. Namun demikian, ia tidak tinggal lama disana dan segera kembali ke Istanbul. Ia bersekongkol dengan Husni Awni Pasha _Mentri Kepolisian Negara_untuk memberhentikan Sultan Abdul Aziz dari kursi kekuasaan. Akhirnya, pada malam tanggal 30 Mei 1876 Sultan Abdul Aziz di berhentikan dengan tanda pembacaan fatwa pemberhentian dari Syaikhul Islam. Pada malam itu juga Murad V diangkat sebagai Khalifah.
Setelah diangkat menjadi perdana mentri pada masa Sultan Abdul Hamid II, Midhat Pasha mengumumkan berlakunya sebuah Undang-Undang yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan unsur agama atau apapun. Karena menurutnya, segala perbaikan yang dilakukan oleh Daulah Usmaniyyah harus berdasarkan atas hukum demokrasi. Untuk itu perlu dibentuk Undang-Undang dan Majelis Perwakilan Rakyat yang mewakili semua unsur masyarakat. Dengan demikian, rakyatlah yang menentukan suatu hukum, bukan sultan maupun penguasa. Dan setiap penguasa harus bertanggungjawab didepan majelis. Inilah yang dimaksudkan dalam Islam sebagai prinsip syura, yang oleh Barat disebut sebagai parlemen. Akhirnya pada tanggal 23 Desember 1876 lairlah sebuah konstitusi yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan sultan.
Konstitusi Turki Usmaniyah yang pertama ini mengambil model konstitusi Perancis dan Belgia mengatur system kerajaan konstitusional yang terdiri dari dua parlemen, yaitu Balai Tinggi dan Balai Rendah. Namun pada prkateknya, banyak kendala yang menyertainya. Sultan Abdul Hamid II tampaknya hanya mau mereformasi bidang militer pada bidang politik. Beberapa pasalnya bahkan membuat kekuasaan sultan semain kuat. Ia menolak dibatasi kekuasaannya, bahkan menghidupkan kembali sebutan Khalifah untuknya, dan menuntut dukungan kaum muslim untuk menghalau pemberontak nasionalis Kristen yang muncul diwilayah Balkan. Dan akhirnya sultan ini pun menindak dan menangkap tokoh-tokoh reformasi, tidak terkecuali Midhat Pasha.
Dibidang pertahanan, Midhat melihat bahwa Usmaniyah adalah salah satu tanah tersubur didunia. Akan tetapi kenyataannya sangat kontradiktif dengan rakyatnya yang tetap miskin. Menurut Midhat, penerapan pajak yang memberatkan dan kerakusan Negara-negara Eropa yang selalu menghalangi kemajuan Turki Usmani adalah salah satu penyebabnya. Dikepalanya, Midhat memiliki banyak pemikiran yang berupaya untuk memulihkan kondisi ini. Sayangnya beberapa pihak menentang upaya dan cita-citanya ini. Sultan yang merasa posisinya terancam para ulama yang menganggap bahwa pembaharuan adalah hal yang bertentangan dengan agama, juga Negara asing yang terncam kepentingannya di Turki Usmani. Ahirnya Midhat Pasha seorang pribadi yang didalamnya bersatu jiwa ketaqwaan dan kemoderenan pun harus disingkirkan, dibuang dan dibunuh di tempat pembuangannya pada tahun 1884 M.
3. Namik Kemal
Namik Kemal lahir di Rhodosto pada 21 Desember 1840 dan meninggal pada 2 Desember 1888 di Mytilene. Ia adalah serang penyair utama Turki, tokoh utama Turki modern, pecipta bahasa modern sejarah satra Turki. Disamping itu, ia juga adalah seorang jurnalis sebuah suarat kabar berbahasa Turki “Taswir Efkar”. Taswir bertujuan untuk melakukan pencerahan di bidang poitik, kesusastraan dan ilmu pengetahuan bangsa Turki.
Keterlibatannya dalam gerakan politik berawal ketika ia bergabung dengan komite Usmani Muda yang didirikan oleh Ziya Pasha. Dan ketika para petinggi kelompok muda ini dibayang-bayangi penangkapan oleh pihak pemerintah, ia bersama Ziya, Nuri, Rif’at, dan Ali Su’awi meninggalkan Turki dan pergi bersama ke London guna meneruskan perjuangan. Di London ia menerbitkan surat kabar Mukhbir yang kemudian diganti dengan nama Hurriyet ketika basis perjuangan mereka berpindah ke Perancis.
Dimata pemerintah, ia termasuk orang yang kurang disukai, teruatam ketika ia mempergelarkan lakon panggung Watha yang menimbulkan kerusuhan. Akhirnya ia dikucilkan di Famagusta, Cyprus. Ketika sultan Murad berkuasa, ia dibebaskan tetapi gerak geriknya kembali di awasi oleh Sultan Abdul Hamid II II ketika ia naik tahta setelah sultan Murad yang berkuasa hanya 93 hari. Bersama Midhat Pasha dan Ziya Pasha, ia menyiapkan Undang-Undang dan proses liberalisasi. Ia sendiri sebenarnya amat menyadari beberapa kesulitan yang akan menghadangnya dikemudian hari. Tetapi ia juga yakin bahwa ia akan bebrhasil.
Kritik Namik Kemal terhadap pembaharu Turki pada periode tanzimat adalah adopsi mereka secara besar-besaran terhadap pembaharuan yang ada didunia Barat, sehingga menjurus ke sekulerisasi yang belum tentu sejalan dengan ajaran Islam dan kebutuhan masyarakat Turki. Padahal menurut Namik bahwa landasan yang semestinya dalam pembaharuan kelembagaan dapat ditemukan dalam berbagai ajaran Islam. Ia berkeyakinan bahwa Islam dapat disejajarkan dengan peradaban modern. Syari’at Islam mamapu membenahi bentuk pemerintahan dan menghadapi gempuran dunia barat.
Adapun sebab-sebab yang membawa kemunduran kerajaan Usmani, menurutnya terletak pada keadaan ekonomi dan politik yang tidak beres. Jalan pertama yang harus ditempuh untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan politik ialah perubahan system pemerintahan abosolut menjadi pemerintahan konstitusional.
B. TURKI MUDA
Gerakan turki muda merupakan kelanjutan pembaharuan yang dilakukan serangkaian para tokoh pembaharu sebelumnya. Cara Sultan Abdul Hamid II memerintah di Turki kian hari makin otoriter dan absolut. Demokratisasi hanya merupakan sembonyan dan slogan belaka. Namun dalam prakteknya, sikap demokrasi sama sekali tidak ada. Rakyat tidak mempunyai kebebasan berpendapat. Kritik dan kecemasan atas kekuasaan sultan yang demikian besar tidak saja datang dan kalangan umum tapi juga kaum intelegensia dan kalangan akademik. Mereka melihat tindakn-tindakan penguasa sudah banyak yang menyimpang dan perUndang-Undangan dan jauh dari memperjuangkan kepentingan rakyat.
Menurut Harun Nasution, dalam suasana demikian timbullah berbagai gerakan oposisi terhadap pemerintah absolut Sultan Abdul Hamid II, sebagaimana halnya dimasa lampau dengan Sultan Abdul Aziz oposisi dikalangan pergururan tinggi mengambil bentuk perkumpulan-perkumpulan rahasia. Dikalangan para intelektual para pemimpinnya lari ke luar negeri dan dari sana melanjutkan oposisi mereka. Sedangkan dikalangan militer menjelma dalam bentuk komite-komite rahasia. Oposisi dan berbagai kelompok inilah yang kemudian dikenalkan dengan nama Turki Usmani.
Namun begitu, perlu diingat bahwa sejak pertama para pendukung gerakan Turki Muda ini telah terbagi dalam dua kelompok. Pertama, kelompok liberal yang menginginkan desentralisasi dan pemberian beberapa hak khusus bagi kelompok minoritas. Kedua adalah kelompok nasionalis, yang menginginkan dominan bangsa Turki dan kekuasaan yang terpusat. Kelompok kedua inilah yang menggunakan CPU (Comitee on Union and Progress) sebagai alat secara terbuka untuk memperoleh kekuasaan.
Dalam perjalanan selanjutnya, kelompok Turki Muda dikenal sebagai kelompok pembaharu pertama yang merencanakan industrialisasi. Hal itu kemudian dilegalformalkan dalm Undang-Undang tentang industry pada tahun 1909 yang kemudian diperbaharu pada tahun 1915. Meskipun mereka hanya mendapatkan keberhasilan yang kecil dalam bidang industri, namun paling tidak Turki telah memiliki jaringan kerja bagi rencana pembangunan ekonomi masa mendatang. Disamping itu tentunya, pasti dalam pembaharuan bidang pendidikan. Terutama pendidikan tingkat dasar yang selama ini nyaris diabaikan
Adapun beberapa tokoh yang memainkan peran penting dalam pembaharuan pada masa Turki Muda antara lain, adalah:
1) Ahmad Riza (1859-1930)
Ahmad Riza adalah anak dari seorang bekas anggota parlemen bernama Injilid Ali. Dalam pendidikannya dia sekolah dipertanian untuk kelak dapat bekerja dan berusaha mengubah nasib para petani yang malang. Dan studinya ini diteruskan ke Perancis. Sekembalinya dari Perancis ia bekerja di Kementrin Pertanian, tetapi ternyata hubungan kementrian dengan para petani yang miskin minim sekali, karena kementrian itu lebih banyak disibukkan dengan birokrasi. Kemudian dia pindah ke Kementrian Pendidikn namun disini juga ia disibukkan dengan birokrasi, kurang perhatian terhadap bidang pendidikan.
Pembaharuan yang dilakukan oleh Ahmad Riza antara lain adalah ingin mengubah pemerintah yang absolut kepada pemerintah konstitusional. Karena menurutnya yang akan menyelamatkan kerajaan Usmani dari keruntuhan adalah bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan positif dan bukan dengan teologi atau metafisika. Adanya dan terlaksanamya program pendidikan yang baik akan berhajat pada pemerintahan yang kontitusional
2) Mehmed Murad (1853-1912)
Mehmed Murad berasal dari Kaukasus dan lari ke Istambul. Pada tahun 1873 yakni setelah gagalnya pemberontakan Syekh Syamil di daerah itu. Ia belajar di Rusia dan disanalah ia berjumpa dengan ide-ide barat, namun pemikiran Islam masih berpengaruh pada dirinya.
Ia berpendapat bahwa bukanlah Islam yang menjadi penyebab mundurnya kerajaan Usmani dan bukan pula rakyatnya. Namun sebab kemunduran itu terletak pada Sultan yang memerintah secara absolut. Oleh karena itu menurutnya kekuasaan Sultan harus dibatasi. Dalam hal ini ia berpendapat bahwa musyawarah dalam Islam sama dengan konstitusional didunia barat. Ia mengusulkan didirikan satu badan pengawas yang tugasnya mengawasi jalannya Undang-Undang agar tidak dilanggar oleh pemerintah. Disamping itu diadakan pula Dewan Syari’at Agung yang anggotanya tersusun dari wakil-wakil Negara Islam di Afrika dan Asia yang ketuanya adalah Syekh Al- Islam kerajaan Usmani.
Mehmed Murad mempunyai paham Pan-Islamisme, karena ia melihat bahwa salah satu sebab bagi kelemahan kerajaan Usmani adalah renggangnya hubungan Istambul dengan daerah-daerah lainnya. Utamanya daerah yang ada di bawah kekuasaan Turki.
3) Pangeran Sahabuddin (1887-1949)
Pangeran Sahabuddin adalah keponakan Sultan Abdul Hamid II dari pihak ibunya, sedang dari pihak bapaknya adalah cucu dari Sultan Mahmud II, oleh karena itu ia keturunan raja. Namun ibu dan bapaknya lari ke Eropa menjauhkan diri dari kekuasaan Abdul Hamid, maka dengan demikian kehidupan Sahabuddin lebih banyak diengaruhi oleh pemikiran barat.
Pemikiran Sahabuddin dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran sosiologi sehingga problema yang dihadapi oleh kerajaan Usmani ia tinjau dari segi sosiolagi.
Menurutnya yang pokok adalah perubahan social, bukan penggantian Sultan. Masyarakat Turki sebagaimana masyarakat timur lainnya mempunyai corak kolektif, dan masyarakat kolektif tidak mudah berubah dalam menuju kemajuan. Dalam masyarakat kolektif orang tidak percaya diri sendiri, oleh karena itu mereka tidak dapat berdiri sendiri, mereka tergantung pada kelompoknya, baik kelompok itu berbentuk keluarga atau suku bangsa, atau pemerintah dsb. Sedangkan masyarakat maju adalah masyarakat yang tidak banyak tergantung kepada orang lain, tetapi sanggup berdiri sendiri dan berusaha sendiri untuk melakukan transformasi dalam berbagai aspek dan dimensi.
Menurut Sahabuddin selam masyarakat Turki masih kolektif, maka Sultan tetap akan mempunyai kekuasaan absolute. Karena itu, sebagai jalan untuk mengatasi kekuasaan absolut ini ia menganjurkan supaya diadakan desentralisasi dalam bidang pemerintahan. Disamping itu jalan yang ampuh untuk mengubah masyarakat yang kolektif adalah dengan memajukan sector pendidikan. Rakyat Turki harus dilatih dan dididik dapat berdiri sendiri untuk mengubah nasibnya. Sahabuddin juga mendirikan dan menerbitkan majalah sendiri yang diberi nama Terekki (kemajuan).
Sungguhpun ada perbedaan dan politik antara ketiga pemuka diatas beserta pengikutnya masing-masing, mereka sepekat untuk menggulingkan Sultan Abdul Hamid II, keputusan ini diambil setelah diadakannya dua kali konferensi di Eropa dan yang terakhir di Paris pada tahun 1970 M.
Akhirnya revolusi tidaklah dapat diletakkan lagi dan pada tanggal 23 Juli 1908 kekuasaan Sultan berakhir dan mulailah diberlakukan konstitusi baru.
Karena pembela-pembela kontitusi yang baru tidak banyak dan lemah, maka dalam perkembangan selanjutnya akhirnya pemerintah mengalami degenerasi kedalam satu bentuk militer dari pemimpin-pemimpin Turki Muda yang sama sekali tidak menerima kritikan-kritikan darri pihak lain, dan bahkan semua gerakan oposisi dibubarkan dan pemimpin-pemimpinnya dibuang.
Perjuangan Turki Muda tidak banyak berhasil, hanya berhasil dalam menggulingkan Sultan, namun tidak berhasil dalam mencapai tujuannya, kekuasaan mereka tidaklah teratur dengan rapi. Kekuasaan mereka menjadi berantakan.
DAFTAR PUSTAKA
Asmuni,M. Yusran. 2001. Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Nasution, Harun.1991. Pembaharuan dalam Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
Wibisono, A. Fattah. 2009. Pemikiran Para Lokomotif Pembaharuan di Dunia Islam. Jakarta: Rabbani Press.
Zallum, Abdul Qadim. 2007. Kaifa Hudimatil Khilafah (Malapetaka Runtuhnya Daulah Khilafah). Bogor: Al-Azhar Press, 2007.
[ Read More ]
Pembaharuan yang dilakukan dalam tanzimat belum dapat meraih hasil seperti yang di harapkan. Lebih jauh malah mendapatkan kritikan-kritikan dari luar kaum cendikiawan. Kegagalan oleh tanzimat dalam mengganti konstitusi yang absolut merupakan cambuk untuk usaha-usaha selanjutnya. Untuk mengubah kekuasaan yang absout maka timbullah usaha atau gerakan dari kaum cendikiawan dalam melanjutkan usaha-usaha tanzimat.
Sementara itu, menurut L. Stoddard yang dikutip Badriyatim kemudian dikutip kembali oleh Dr. H. A. Fattah Wibisono, M.A dalam bukunya Pemikiran Para Lokomotif Pembaharuan di Dunia Islam, Eropa dalam abad ke Sembilan belas sudah jauh maju meninggalkan Dunia Islam. Eropa sudah dipersenjatai dengan ilmu modern dan penemuan yang membuka rahasia alam. Satu demi satu negri Islam yang sedang rapuh itu jatuh ke tangan Barat. Dalam waktu yang tidak lama, kerajaan-kerajaan besar Eropa telah membagi bagi Dunia islam. Inggris merebut india dan Mesir. Rusia menyebrangi Kaukasus dan menguasai Asia Tenggara. Prancis menguasai Afrika Utara, dan bangsa-bangsa Eropa.
USMANI MUDA DAN TURKI MUDA
A. USMANI MUDA
Golongan intelegensia Kerajaan Usmani yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan di kenal dengan nama usmani muda (yeni usmanlilar-Young Ottoman). Pemikiran-pemikiran yang diajukan pemuka-pemuka usmani muda-lah yang mempengaruhi pembaharuan yang diadakan sesudah zaman Tanzimat.
Usmani muda pada asalnya merupakan perkumpulan rahasia yang didirikan di tahun 1865 dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan absolut kerajaan Usmani menjadi pemerintahan konstitusional.
Menurut Niyyazi Berkes, seorang guru besar Islamic Studies di McGill University, Canada yang kami kutip dari Dr. H. A. Fattah Wibisono, M.A dalam bukunya Pemikiran Para Lokomotif Pembaharuan di Dunia Islam, bahwa gerakan usmani muda atau ittipaki-Humavat mula-mula muncul tahuk 1865. Mereka bertujuan untuk mengadakan perlawanan secara rahasia terhadap kekuasaan absolut sultan. Terutama sekali atas pemberlakuan pemerinatahan absolut menjadi pemerintahan konstitusional. Para tokoh Usmani Muda banyak yang melakukan gerakan rahasia dalam menentang kekuasaan absolut sultan. Namun akhirnya sikap politik mereka diketahui oleh sultan. Akhirnya mereka banyak yang lari ke Eropa dan disanalah mereka menyusun kekuatan. Di Eropa mereka kemudian mendapat sebutan Usmani Muda. Setelah situasi Turki aman kembali, mereka pun banyak yang pulang ke tanah air untuk melakukan pembaharuan, sebuah cita-cita yang sempat tersendat.
Gagasan pemikiran yang dikembangkan Usmani Muda ini banyak memiliki pengaruh terhadap pembaharuan yang dilakukan di turki pasca periode Tanzimat. Pergaulan tokoh-tokoh Usmani Muda dengan pemikir-pemikir dari Perancis dan Inggris yang cukup liberal sedikit banyak membawa pengaruh bagi gerakan Usmani Muda ini. Maka beberapa pembaharuan mereka pun cukup bersifat liberal. Untuk melancarkan usaha pembaharuannya ini, kalangan Usmani Muda memanfaatkan media masa sebagai saluran penyebarannya. Antara lain surat kabar Tasvir-i-Efkar (gambaran pemikiran) yang didirikan Ibrahim Sinasi Effendi. Ketika Ibrahim lari ke luar negri karena tekanan dari sultan, surat kabar ini dipimpin oleh Namik Kemal, salah satu tokoh Usmani Muda yang lain.
Setelah mengalami perjuangan yang berat dengan pemuka-pemuka kerajaan, maka pada tanggal 23 Desember 1876 tercapaiah persetujuan tentang konstitusi sebagai Undang-Undang dasar yang baru bagi Turki, akan tetapi isinya masih otokrasi sehingga masih belum sesuai dengan apa yang diarapkan. Dan akhirnya Undang-Undang yang baru bagi Turki itu dilanggar juga oleh Sultan Abdul Hamid II II yakni dengan membubarkan parlemen dan para pemuka-pemukanya ditangkap dengan demikian maka berakhirlah riwayat perjuangan Usmani Muda.
Beberapa tokoh dan para pembaharu dalam gerakan Usmani Muda antara lain sebagai berikut:
1. Ziya Pasha
Zia lahir pada tahun 1825 di Istanbul dan meninggal pada tahun 1880. Ia anak seorang pegawai Kantor Bea Cukai Istanbul. Setelah menyelesaikan pelajaran pada sekolah Sulaymaniye, yang didirikan Sultan Mahmud II ini diangkat menjadi pegawai pemerintah selagi masih berusia muda. Atas usaha Mustafa Rasyid Pasha. Pada tahun 1854 ia diterima menjadi salah satu sekrtaris sultan. Namun permusuhannya dengan Ali Pasha membuat ia terpaksa pergi ke Eropa di tahun 1867 dan tinggal disana selama lima tahun.
Usaha-usaha pembaharuannya antara lain bahwa kerajaan Usmani menurut pendapatnya harus dibangun dengan system pemerinatahan konstitusional, tidak dengan kekuasaan absolut. Menurutnya Negara Eropa maju disebabkan tidak adanya lagi pemerinatahan yang absolut, semuanya dengan system pemerintahan konstitusional. Dalam system kontitusional, harus ada Dewan Perwakilan Rakyat. Alasan perlua adanya DPR ini adalah agar perbedaan pendapat dapat ditampung dan kritik terhadap pemerintah diperlukan untuk kepentingan pemerintah dan rakyat. DPR-lah yang nantinya memperjuangkan perbedaan pendapat diakalangan umat Islam. Sebagai orang yang taat menjalankan agama Islam, Ziya sebenarnya tidak sepenuhnya setuju terhadap pembaharuan yang hanya mencomot ide-ide barat tanpa sikap kritis. Menurutnya, umat Islam harus tetap mengkritisi setiap kebudayaan barat dan nilai-nilai kemajuan yang dibawanya. Itulah sebabnya ia lebih menilik kepada keseuaian antara kepentingan rakyat dengan ide pembaharuan yang datangnya dari barat. Dalam hal demikian, ia juga tidak sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa agama Islam dapat dianggap sebagai penghalang kemajuan.
2. Midhat Pasya
Nama lengkapnya Hafidz Ahmad Syafiq Midat Pasya. Ia lahir pada tahun 1822 M di Istambul Turki dan wafat pada tahun 1884 M. Pendidikan agamanya diperoleh dari ayahnya sendiri. Dalam usia 10 tahun ia telah hafiz al-Qur'an. Oleh karena itu ia digelari al-Hafidz. Pendidikannya yang tertinggi adalah pada Universitas al-Fatih.
Kemudian dalam usia belasan tahun ia menjadi pegawai di Biro Perdana Mentri. Di tahun 1858 ia diberi cuti untuk berkunjung selama enam bulan ke Eropa. Kemudian ia diangkat beberapa kali sebagai Gubernur di berbagai daerah. Dalam jabatan ini ia menunjukkan kecakapan luar biasa. Di tahun 1872 ia diangkat oleh Sultan Abdul Aziz menjadi perdana mentri. Tetapi karena selalu mengalami bentrokan dengan kekuasaan absolut sultan, ia diberhentikan beberapa bulan kemudian.
Sebagai tokoh gerakan Usmani Muda, oleh sahabat seperjuangannya ia dipercayakan memegang pemerintahan dan sekaligus memperjuangkan cita-cita gerakan ittu. Maka ia, selain menjadi Gubernur di Balkan dan Baghdad, pada Tahun 1872 berhasil menjadi menteri Kehakiman dan kemudian menjadi Perdana Mentri.
Midhat Pasha adalah Mentri Kehakiman dalam Kabinet Muhammad Rusydie Pasha pada masa Kekhalifahan Abdul Aziz. Dia pernah membujuk Khalifah Abdul Aziz untuk menyusun suatu rancangan konstitusi berdasarkan system demokrasi barat. Dia pernah menulis surat pada khalifah dan mendorongnya memperbaiki status quo dengan menetapkan suatu konstitusi baru.
Sultan Abdul Aziz menemui Midhat Pasha sebagaimana mestinya dan menerima suratnya tersebut. Setelah membaca surat tersebut, Abdul Aziz sangat murka. Ia memerintahkan untuk segera memecat Midhat Pasha dari pemerintahan dan mengasingkannya sebagai wali (gubernur) di Salonika. Namun demikian, ia tidak tinggal lama disana dan segera kembali ke Istanbul. Ia bersekongkol dengan Husni Awni Pasha _Mentri Kepolisian Negara_untuk memberhentikan Sultan Abdul Aziz dari kursi kekuasaan. Akhirnya, pada malam tanggal 30 Mei 1876 Sultan Abdul Aziz di berhentikan dengan tanda pembacaan fatwa pemberhentian dari Syaikhul Islam. Pada malam itu juga Murad V diangkat sebagai Khalifah.
Setelah diangkat menjadi perdana mentri pada masa Sultan Abdul Hamid II, Midhat Pasha mengumumkan berlakunya sebuah Undang-Undang yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan unsur agama atau apapun. Karena menurutnya, segala perbaikan yang dilakukan oleh Daulah Usmaniyyah harus berdasarkan atas hukum demokrasi. Untuk itu perlu dibentuk Undang-Undang dan Majelis Perwakilan Rakyat yang mewakili semua unsur masyarakat. Dengan demikian, rakyatlah yang menentukan suatu hukum, bukan sultan maupun penguasa. Dan setiap penguasa harus bertanggungjawab didepan majelis. Inilah yang dimaksudkan dalam Islam sebagai prinsip syura, yang oleh Barat disebut sebagai parlemen. Akhirnya pada tanggal 23 Desember 1876 lairlah sebuah konstitusi yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan sultan.
Konstitusi Turki Usmaniyah yang pertama ini mengambil model konstitusi Perancis dan Belgia mengatur system kerajaan konstitusional yang terdiri dari dua parlemen, yaitu Balai Tinggi dan Balai Rendah. Namun pada prkateknya, banyak kendala yang menyertainya. Sultan Abdul Hamid II tampaknya hanya mau mereformasi bidang militer pada bidang politik. Beberapa pasalnya bahkan membuat kekuasaan sultan semain kuat. Ia menolak dibatasi kekuasaannya, bahkan menghidupkan kembali sebutan Khalifah untuknya, dan menuntut dukungan kaum muslim untuk menghalau pemberontak nasionalis Kristen yang muncul diwilayah Balkan. Dan akhirnya sultan ini pun menindak dan menangkap tokoh-tokoh reformasi, tidak terkecuali Midhat Pasha.
Dibidang pertahanan, Midhat melihat bahwa Usmaniyah adalah salah satu tanah tersubur didunia. Akan tetapi kenyataannya sangat kontradiktif dengan rakyatnya yang tetap miskin. Menurut Midhat, penerapan pajak yang memberatkan dan kerakusan Negara-negara Eropa yang selalu menghalangi kemajuan Turki Usmani adalah salah satu penyebabnya. Dikepalanya, Midhat memiliki banyak pemikiran yang berupaya untuk memulihkan kondisi ini. Sayangnya beberapa pihak menentang upaya dan cita-citanya ini. Sultan yang merasa posisinya terancam para ulama yang menganggap bahwa pembaharuan adalah hal yang bertentangan dengan agama, juga Negara asing yang terncam kepentingannya di Turki Usmani. Ahirnya Midhat Pasha seorang pribadi yang didalamnya bersatu jiwa ketaqwaan dan kemoderenan pun harus disingkirkan, dibuang dan dibunuh di tempat pembuangannya pada tahun 1884 M.
3. Namik Kemal
Namik Kemal lahir di Rhodosto pada 21 Desember 1840 dan meninggal pada 2 Desember 1888 di Mytilene. Ia adalah serang penyair utama Turki, tokoh utama Turki modern, pecipta bahasa modern sejarah satra Turki. Disamping itu, ia juga adalah seorang jurnalis sebuah suarat kabar berbahasa Turki “Taswir Efkar”. Taswir bertujuan untuk melakukan pencerahan di bidang poitik, kesusastraan dan ilmu pengetahuan bangsa Turki.
Keterlibatannya dalam gerakan politik berawal ketika ia bergabung dengan komite Usmani Muda yang didirikan oleh Ziya Pasha. Dan ketika para petinggi kelompok muda ini dibayang-bayangi penangkapan oleh pihak pemerintah, ia bersama Ziya, Nuri, Rif’at, dan Ali Su’awi meninggalkan Turki dan pergi bersama ke London guna meneruskan perjuangan. Di London ia menerbitkan surat kabar Mukhbir yang kemudian diganti dengan nama Hurriyet ketika basis perjuangan mereka berpindah ke Perancis.
Dimata pemerintah, ia termasuk orang yang kurang disukai, teruatam ketika ia mempergelarkan lakon panggung Watha yang menimbulkan kerusuhan. Akhirnya ia dikucilkan di Famagusta, Cyprus. Ketika sultan Murad berkuasa, ia dibebaskan tetapi gerak geriknya kembali di awasi oleh Sultan Abdul Hamid II II ketika ia naik tahta setelah sultan Murad yang berkuasa hanya 93 hari. Bersama Midhat Pasha dan Ziya Pasha, ia menyiapkan Undang-Undang dan proses liberalisasi. Ia sendiri sebenarnya amat menyadari beberapa kesulitan yang akan menghadangnya dikemudian hari. Tetapi ia juga yakin bahwa ia akan bebrhasil.
Kritik Namik Kemal terhadap pembaharu Turki pada periode tanzimat adalah adopsi mereka secara besar-besaran terhadap pembaharuan yang ada didunia Barat, sehingga menjurus ke sekulerisasi yang belum tentu sejalan dengan ajaran Islam dan kebutuhan masyarakat Turki. Padahal menurut Namik bahwa landasan yang semestinya dalam pembaharuan kelembagaan dapat ditemukan dalam berbagai ajaran Islam. Ia berkeyakinan bahwa Islam dapat disejajarkan dengan peradaban modern. Syari’at Islam mamapu membenahi bentuk pemerintahan dan menghadapi gempuran dunia barat.
Adapun sebab-sebab yang membawa kemunduran kerajaan Usmani, menurutnya terletak pada keadaan ekonomi dan politik yang tidak beres. Jalan pertama yang harus ditempuh untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan politik ialah perubahan system pemerintahan abosolut menjadi pemerintahan konstitusional.
B. TURKI MUDA
Gerakan turki muda merupakan kelanjutan pembaharuan yang dilakukan serangkaian para tokoh pembaharu sebelumnya. Cara Sultan Abdul Hamid II memerintah di Turki kian hari makin otoriter dan absolut. Demokratisasi hanya merupakan sembonyan dan slogan belaka. Namun dalam prakteknya, sikap demokrasi sama sekali tidak ada. Rakyat tidak mempunyai kebebasan berpendapat. Kritik dan kecemasan atas kekuasaan sultan yang demikian besar tidak saja datang dan kalangan umum tapi juga kaum intelegensia dan kalangan akademik. Mereka melihat tindakn-tindakan penguasa sudah banyak yang menyimpang dan perUndang-Undangan dan jauh dari memperjuangkan kepentingan rakyat.
Menurut Harun Nasution, dalam suasana demikian timbullah berbagai gerakan oposisi terhadap pemerintah absolut Sultan Abdul Hamid II, sebagaimana halnya dimasa lampau dengan Sultan Abdul Aziz oposisi dikalangan pergururan tinggi mengambil bentuk perkumpulan-perkumpulan rahasia. Dikalangan para intelektual para pemimpinnya lari ke luar negeri dan dari sana melanjutkan oposisi mereka. Sedangkan dikalangan militer menjelma dalam bentuk komite-komite rahasia. Oposisi dan berbagai kelompok inilah yang kemudian dikenalkan dengan nama Turki Usmani.
Namun begitu, perlu diingat bahwa sejak pertama para pendukung gerakan Turki Muda ini telah terbagi dalam dua kelompok. Pertama, kelompok liberal yang menginginkan desentralisasi dan pemberian beberapa hak khusus bagi kelompok minoritas. Kedua adalah kelompok nasionalis, yang menginginkan dominan bangsa Turki dan kekuasaan yang terpusat. Kelompok kedua inilah yang menggunakan CPU (Comitee on Union and Progress) sebagai alat secara terbuka untuk memperoleh kekuasaan.
Dalam perjalanan selanjutnya, kelompok Turki Muda dikenal sebagai kelompok pembaharu pertama yang merencanakan industrialisasi. Hal itu kemudian dilegalformalkan dalm Undang-Undang tentang industry pada tahun 1909 yang kemudian diperbaharu pada tahun 1915. Meskipun mereka hanya mendapatkan keberhasilan yang kecil dalam bidang industri, namun paling tidak Turki telah memiliki jaringan kerja bagi rencana pembangunan ekonomi masa mendatang. Disamping itu tentunya, pasti dalam pembaharuan bidang pendidikan. Terutama pendidikan tingkat dasar yang selama ini nyaris diabaikan
Adapun beberapa tokoh yang memainkan peran penting dalam pembaharuan pada masa Turki Muda antara lain, adalah:
1) Ahmad Riza (1859-1930)
Ahmad Riza adalah anak dari seorang bekas anggota parlemen bernama Injilid Ali. Dalam pendidikannya dia sekolah dipertanian untuk kelak dapat bekerja dan berusaha mengubah nasib para petani yang malang. Dan studinya ini diteruskan ke Perancis. Sekembalinya dari Perancis ia bekerja di Kementrin Pertanian, tetapi ternyata hubungan kementrian dengan para petani yang miskin minim sekali, karena kementrian itu lebih banyak disibukkan dengan birokrasi. Kemudian dia pindah ke Kementrian Pendidikn namun disini juga ia disibukkan dengan birokrasi, kurang perhatian terhadap bidang pendidikan.
Pembaharuan yang dilakukan oleh Ahmad Riza antara lain adalah ingin mengubah pemerintah yang absolut kepada pemerintah konstitusional. Karena menurutnya yang akan menyelamatkan kerajaan Usmani dari keruntuhan adalah bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan positif dan bukan dengan teologi atau metafisika. Adanya dan terlaksanamya program pendidikan yang baik akan berhajat pada pemerintahan yang kontitusional
2) Mehmed Murad (1853-1912)
Mehmed Murad berasal dari Kaukasus dan lari ke Istambul. Pada tahun 1873 yakni setelah gagalnya pemberontakan Syekh Syamil di daerah itu. Ia belajar di Rusia dan disanalah ia berjumpa dengan ide-ide barat, namun pemikiran Islam masih berpengaruh pada dirinya.
Ia berpendapat bahwa bukanlah Islam yang menjadi penyebab mundurnya kerajaan Usmani dan bukan pula rakyatnya. Namun sebab kemunduran itu terletak pada Sultan yang memerintah secara absolut. Oleh karena itu menurutnya kekuasaan Sultan harus dibatasi. Dalam hal ini ia berpendapat bahwa musyawarah dalam Islam sama dengan konstitusional didunia barat. Ia mengusulkan didirikan satu badan pengawas yang tugasnya mengawasi jalannya Undang-Undang agar tidak dilanggar oleh pemerintah. Disamping itu diadakan pula Dewan Syari’at Agung yang anggotanya tersusun dari wakil-wakil Negara Islam di Afrika dan Asia yang ketuanya adalah Syekh Al- Islam kerajaan Usmani.
Mehmed Murad mempunyai paham Pan-Islamisme, karena ia melihat bahwa salah satu sebab bagi kelemahan kerajaan Usmani adalah renggangnya hubungan Istambul dengan daerah-daerah lainnya. Utamanya daerah yang ada di bawah kekuasaan Turki.
3) Pangeran Sahabuddin (1887-1949)
Pangeran Sahabuddin adalah keponakan Sultan Abdul Hamid II dari pihak ibunya, sedang dari pihak bapaknya adalah cucu dari Sultan Mahmud II, oleh karena itu ia keturunan raja. Namun ibu dan bapaknya lari ke Eropa menjauhkan diri dari kekuasaan Abdul Hamid, maka dengan demikian kehidupan Sahabuddin lebih banyak diengaruhi oleh pemikiran barat.
Pemikiran Sahabuddin dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran sosiologi sehingga problema yang dihadapi oleh kerajaan Usmani ia tinjau dari segi sosiolagi.
Menurutnya yang pokok adalah perubahan social, bukan penggantian Sultan. Masyarakat Turki sebagaimana masyarakat timur lainnya mempunyai corak kolektif, dan masyarakat kolektif tidak mudah berubah dalam menuju kemajuan. Dalam masyarakat kolektif orang tidak percaya diri sendiri, oleh karena itu mereka tidak dapat berdiri sendiri, mereka tergantung pada kelompoknya, baik kelompok itu berbentuk keluarga atau suku bangsa, atau pemerintah dsb. Sedangkan masyarakat maju adalah masyarakat yang tidak banyak tergantung kepada orang lain, tetapi sanggup berdiri sendiri dan berusaha sendiri untuk melakukan transformasi dalam berbagai aspek dan dimensi.
Menurut Sahabuddin selam masyarakat Turki masih kolektif, maka Sultan tetap akan mempunyai kekuasaan absolute. Karena itu, sebagai jalan untuk mengatasi kekuasaan absolut ini ia menganjurkan supaya diadakan desentralisasi dalam bidang pemerintahan. Disamping itu jalan yang ampuh untuk mengubah masyarakat yang kolektif adalah dengan memajukan sector pendidikan. Rakyat Turki harus dilatih dan dididik dapat berdiri sendiri untuk mengubah nasibnya. Sahabuddin juga mendirikan dan menerbitkan majalah sendiri yang diberi nama Terekki (kemajuan).
Sungguhpun ada perbedaan dan politik antara ketiga pemuka diatas beserta pengikutnya masing-masing, mereka sepekat untuk menggulingkan Sultan Abdul Hamid II, keputusan ini diambil setelah diadakannya dua kali konferensi di Eropa dan yang terakhir di Paris pada tahun 1970 M.
Akhirnya revolusi tidaklah dapat diletakkan lagi dan pada tanggal 23 Juli 1908 kekuasaan Sultan berakhir dan mulailah diberlakukan konstitusi baru.
Karena pembela-pembela kontitusi yang baru tidak banyak dan lemah, maka dalam perkembangan selanjutnya akhirnya pemerintah mengalami degenerasi kedalam satu bentuk militer dari pemimpin-pemimpin Turki Muda yang sama sekali tidak menerima kritikan-kritikan darri pihak lain, dan bahkan semua gerakan oposisi dibubarkan dan pemimpin-pemimpinnya dibuang.
Perjuangan Turki Muda tidak banyak berhasil, hanya berhasil dalam menggulingkan Sultan, namun tidak berhasil dalam mencapai tujuannya, kekuasaan mereka tidaklah teratur dengan rapi. Kekuasaan mereka menjadi berantakan.
DAFTAR PUSTAKA
Asmuni,M. Yusran. 2001. Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Nasution, Harun.1991. Pembaharuan dalam Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
Wibisono, A. Fattah. 2009. Pemikiran Para Lokomotif Pembaharuan di Dunia Islam. Jakarta: Rabbani Press.
Zallum, Abdul Qadim. 2007. Kaifa Hudimatil Khilafah (Malapetaka Runtuhnya Daulah Khilafah). Bogor: Al-Azhar Press, 2007.